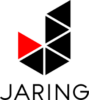Asap rokok mengepul silih berganti memenuhi warung milik keluarga Mastono (44), Jumat, 7 Februari 2025. Warung Mastono berdinding anyaman bambu dengan rak kayu yang dipenuhi makanan ringan dan aneka kopi instan. Sekitar delapan orang duduk di teras warung, mayoritas laki-laki paruh baya. Beberapa dari mereka menikmati kopi hitam dan pisang goreng sambil mendengarkan suara hujan memukuli warung yang berada di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.
Cuaca di Pulau Pari hari itu memang terbilang buruk. Hujan terus menerus turun sedari pagi sampai sore. Akibatnya, beberapa perjalanan kapal dari Muara Angke ke Pulau Pari maupun sebaliknya sempat batal. Pun dengan jadwal keberangkatan K.M Jelajah yang hendak kami tumpangi dari Angke. Kapal bercat biru putih itu seharusnya lepas dari pelabuhan Pukul 8 pagi, tapi karena hujan disertai gelombang tinggi kapal baru melaju jam 1 tengah hari. Perjalanan yang biasanya hanya 1 jam pun molor hingga menjelang Salat Asar. “Pesan kopi pak,” ucap kami sembari berteduh ke pemilik warung.
Tak lama setelah segelas kopi dibawakan ke meja, kami mulai mengobrol macam-macam, utamanya terkait perlawanan warga Pulau Pari terhadap proyek yang selama ini merusak ekosistem laut. Pulau Pari yang luasnya sekitar 43 hektar menjadi saksi bisu perlawan warga, termasuk Mastono.
Lelaki yang akrab disapa Tono ini tidak hanya menghabiskan hari-harinya sebagai penjaga warung, seringkali ia melaut buat menambah pemasukannya. “Sudah berbagai macam lautan dan pulau saya arungi,” ungkapnya menceritakan pengalaman puluhan tahun melaut di pelagai perairan di Indonesia. Dari perairan Bangka Belitung sampai wilayah perikanan di Timur Indonesia sudah pernah ia singgahi. Tapi, menurutnya, perairan Jawa dan Pulau Pari adalah rumah. “Pernah beberapa waktu di daerah Bangka Belitung, memang banyak ikannya namun tetap saja inginnya kembali ke Pulau Pari, tanah kelahiran sendiri,” ia menambahkan.
Bukan tanpa alasan Tono selalu ingin kembali Pulau Pari. Menurutnya, gugusan pulau yang merupakan surga biota laut ini sudah banyak memberi penghidupan bagi warga. Bahkan di pinggir pantai sekalipun, Rajungan maupun Baronang mudah ditemui. “Tapi itu dulu,” tegas Tono.
Kini ia tak lagi mudah mendapatkan ikan di sekitaran pantai. Pun dengan budidaya ikan sulit dilakukan karena rawan terkena jamur. “Jadi sekarang nelayan semakin sulit. Saat sudah ada reklamasi, pasir laut dikeruk untuk dijadikan daratan baru. Hasil tangkapan juga menurun. Sepuluh tahun lalu bisa menyentuh angka 80-100 kilogram, namun sekarang hanya 30 kilogram saja,” keluhnya.
Kondisi hari-hari ini bertambah sulit ketika warga Pulau Pari kerap berhadapan dengan para pengusaha. PT Bumi Pari Asri (PT BPA)—yang mengklaim “pemilik tanah sah,” melakukan pelbagai cara untuk menggusur warga. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang dipenjara hanya karena ingin mempertahankan tanah yang sudah berpuluhan tahun mereka tinggali. Kejadian itu terjadi pada 7 November 2017, dimana tiga warga divonis enam bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mereka dianggap bersalah karena mengutip uang perawatan pantai dan masjid sebesar Rp2,5 juta. Terakhir saat warga menghentikan paksa pengerukan pasir dangkal pada 17 Januari 2025 lalu.
Mimpi buruk warga Pulau Pari tersebut, menurut Tono, sudah berlangsung lama. Sejauh yang dia ingat, dimulai setelah warga mengajukan pendaftaran tanah dalam bentuk surat girik pada 1985. Ketika itu seorang staf dari kelurahan meminta surat girik dan dokumen warga dengan alasan untuk dilakukan pembaruan. Warga kemudian menyerahkan surat-surat itu tanpa prasangka buruk. Namun dokumen tersebut justru tak kunjung dikembalikan. Sejak saat itu, sejumlah perusahaan mulai mengklaim tanah warga. Seingat Tono, perusahaan pertama yang masuk dan melakukan pembangunan di Pulau Pari adalah PT Bumi Raya Utama pada 1989.
“Sudah banyak perusahaan yang masuk dan melakukan pembangunan, seingat saya ada empat perusahaan besar, seperti PT BPA, lalu ada PT Bumi Griya Nusa, PT Sui dan yang terbaru PT Central Pondok Sejahtera (CPS). Tapi selain perusahaan besar itu, banyak anak perusahaan mereka yang masuk juga,” jelasnya.
Puncaknya, ketika PT BPA mengklaim kepemilikan 90% lahan di Pulau Pari pada 2015. Klaim sepihak PT BPA direspon perlawanan oleh masyarakat Pulau Pari, mereka melakukan pelaporan dan gugatan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Akhirnya, setelah dilakukan penyelidikan, Ombudsman mengeluarkan laporan dugaan maladministrasi pada 2018. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Administrasi Jakarta Utara diduga menyalahgunakan wewenang atas penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.210 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHG) No.9 tahun 2015 milik PT BPA.
“Sebelum akhirnya terbukti ada maladministrasi oleh PT BPA, di 2017 terjadi bentrok antar masyarakat dengan Polisi, Tentara dan Satpol PP. Saat itu, diduga PT BPA mengerahkan mereka untuk melakukan penyegelan di Pulau Pari. Bentroknya banyak membuat masyarakat terluka, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak,” cerita Tono.
Sekalipun begitu, upaya perenggutan ruang hidup masyarakat Pulau Pari tak hanya sebatas perusahaan, namun juga Negara. Lewat Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025, Pulau Pari ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Di samping itu Kepulauan Seribu ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan rencana pembangunan yang disebut sebagai “Negeri Seribu Pulau” pada 2022. “Warga tidak pernah diajak berdiskusi,” katanya.
Tono mengungkapkan bahwa masyarakat Pulau Pari tidak menghendaki daerahnya dijadikan kawasan wisata kelas dunia. Warga tidak ingin status tersebut malah mengorbankan kelestarian lingkungan laut yang selama ini dilakukan dan dipertahankan warga. “Kita sudah mengajukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, daerah Pulau Pari dijadikan daerah khusus budidaya saja. Sebab di sini tempatnya budidaya rumput laut, lamun, dan ikan kerapu milik masyarakat. Namun tidak digubris dan malah ingin diproyeksikan sebagai wisata saja,” tutupnya.
Masyarakat Pulau Pari kembali melakukan perlawanan terhadap perusahaan yang terbukti melakukan reklamasi ilegal. Ia dan masyarakat lain akan terus bersolidaritas dan mempertahankan ruang hidup mereka dari perampasan oleh perusahaan maupun Negara, bahkan sampai saat ini.
Asmania (42) masih mengingat peristiwa hilangnya ribuan bakau milik masyarakat Pulau Pari yang dijaga secara swadaya selama tiga tahun terakhir. Perempuan yang akrab disapa Aas itu merasa sedih dan kecewa sebab sampai hari ini, belum ada pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. “Pekerja PT CPS tidak mengakui bahwa mereka yang melakukan pencabutan. Saat melakukan pengerukan pasir, bakaunya sudah tidak ada,” jelasnya pada Jumat, 7 Februari 2025.
Di tengah panasnya terik matahari, sambil mencabuti rumput sisa panen di kebun bersama ibu-ibu dari Kelompok Perempuan Pulau Pari, Aas melanjutkan ceritanya tentang permasalahan dengan perusahaan lain, yakni PT CPS yang telah menghantui masyarakat Pulau Pari beberapa bulan terakhir. “Ekskavator pertama datang tanggal 1 November 2024, namun karena penolakan masyarakat, berhasil ditahan tidak sampai naik ke daratan. Bahkan, kami menyegel ekskavator tersebut dengan kain kafan bertuliskan beko ini disegel masyarakat Pulau Pari,” jelasnya.
Setelah datangnya ekskavator pertama, masyarakat melakukan demonstrasi menolak reklamasi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Saat itu, “kami membawa pasir pantai dan menumpahkan di depan kantor KKP sebagai bentuk protes. Reklamasi yang terjadi merusak lingkungan kami,” ujar Aas.
Alih-alih reklamasi berhenti, pada 17 Januari 2025 lalu ekskavator milik perusahaan malah kembali beroperasi di Pulau Pari. Saat kami menyambangi lokasi reklamasi, ekskavator berkelir biru tosca tak lagi beroperasi. Namun masih terlihat jelas bagaimana dampak dari pengerukan pasir. Kedalaman laut di sekitar gundukan menjadi lebih dalam sekira 18 meter jika dibandingkan bagian lain yang secara alami tergolong dangkal. Sementara area yang diurug sudah mulai nampak daratan menyembul dari permukaan laut. “Saat ekskavator kedua beroperasi, kami tidak sempat mencegahnya. Saat itu kami juga kehilangan 40.000 tanaman bakau yang selama ini dijaga,” lanjutnya.
Barulah setelah mangrove hilang dan galian membekas, proyek tersebut dihentikan pada 20 Januari 2025 oleh KKP. Tidak lama setelah itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq beserta jajarannya turut menyambangi daerah proyek, dan secara resmi menyatakan reklamasi tersebut ilegal dan dihentikan.
Meski begitu, langkah penghentian proyek reklamasi tidak sepenuhnya dianggap positif oleh warga Pulau Pari. Aas menduga proyek tersebut hanya dihentikan sementara. “Polanya nanti perusahaan bayar denda, mengurus izin kembali, dan bisa dilanjutkan proyeknya,” terangnya.
Aas mendorong agar warga tetap waspada. “Harapannya tidak usah ada pembangunan, perusahaan dan Negara tidak usah ikut campur. Biarkan masyarakat sendiri yang mengolah, menempati dan menentukan jalan nasib tanahnya sendiri. Tidak ada pihak yang lebih bisa mengelola Pulau Pari tanpa merusaknya, selain masyarakat sendiri,” tutup Aas.
Muhammad Aminullah dari Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta pun skeptis dengan penyegelan proyek reklamasi ilegal oleh pemerintah. “Agak rumit jika membahas perizinan proyek, sebab diketahui yang menerbitkan izin proyek adalah KKP, namun yang menyegel adalah KLH. Sampai saat ini, baru ada rencana pemberian sanksi administratif kepada PT CPS. Biasanya setelah membayar denda dan menerima sanksi administratif, mereka akan membuat izin baru dan akan dilanjutkan proyeknya,” ungkap Amin ketika ditemui di Sekretariat Walhi Jakarta pada Kamis, 13 Februari 2025.
Lelaki yang akrab disapa Anca itu turut menyayangkan penetapan wilayah Kepulauan Seribu sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan fokus pengembangan pariwisata. Menurutnya, ambisi untuk menjadikan Pulau Pari wisata kelas dunia, hanya akan mengorbankan kelestarian lingkungan. “Proyeksi negara terhadap Pulau Pari akhirnya membuka celah terjadi banyak reklamasi ilegal yang merusak lingkungan. Kerusakan terumbu karang, padang lamun, hilangnya mangrove, akhirnya masyarakat yang terdampak. Selain karena ruang penghidupannya yang tercemar, mereka juga dihantui bencana banjir rob,” lanjutnya.
Padahal bagi masyarakat Pulau Pari, mangrove tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung alami pulau dari abrasi. Sementara padang lamun berperan sebagai penyerap karbon yang signifikan. Penelitian oleh Marine Ecology Progress Series (2022) mencatat bahwa setiap hektar padang lamun dapat menyerap hingga 83 metrik ton karbon per tahun.
“Dalam hal ini Negara tidak punya kekuatan yang cukup melawan perusahaan, karena pasti takut mereka tidak mau lagi menggelontorkan uangnya untuk proyek pembangunan. Akhirnya kan ada konflik kepentingan, negara butuh modal dan perusahaan butuh ruang bisnis, terjadi transaksi yang akhirnya mengenyampingkan masyarakat,” keluhnya.
Dosen Prodi Biologi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Isnin Noer punya pendapat yang sama. Menurutnya, perubahan yang tampak di Pulau Pari saat ini adalah terhadap terumbu karang dan Bintang laut. “Ini akibat dari jejaring ekosistemnya terganggu, sebab seharusnya ada hubungan mutualistik antara makhluk. Karena ada perubahan, misal karena pengerukan pasir menyebabkan tingkat sedimentasinya tinggi, akhirnya banyak tumbuhan air mati. Selain itu, hewan di sekitarnya juga akan berkurang, karena tumbuhan air adalah makanan mereka,” ia melanjutkan.
Isnin juga menyayangkan hilangnya padang bakau milik warga. Menurutnya, bakau merupakan sebuah ekosistem yang memayungi banyak hewan dan tumbuhan di sekelilingnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan banyak hal, tidak hanya dari ekowisata, tapi juga lingkungan, sosial maupun ekonomi masyarakat. Tanpa itu, musykil kegiatan ekowisata di Pulau Pari bisa berjalan. “Pembangunan harus dilihat lagi secara bijaksana, dan melihat berbagai macam aspek, tidak hanya ekosistem. Harus dilihat juga secara konteks sejarah, karena Pulau Pari merupakan induk dari perkembangan pengetahuan terutama biologi,” pungkasnya. (Zahra Pramuningtyas & Lalu Adam Farhan Alwi)