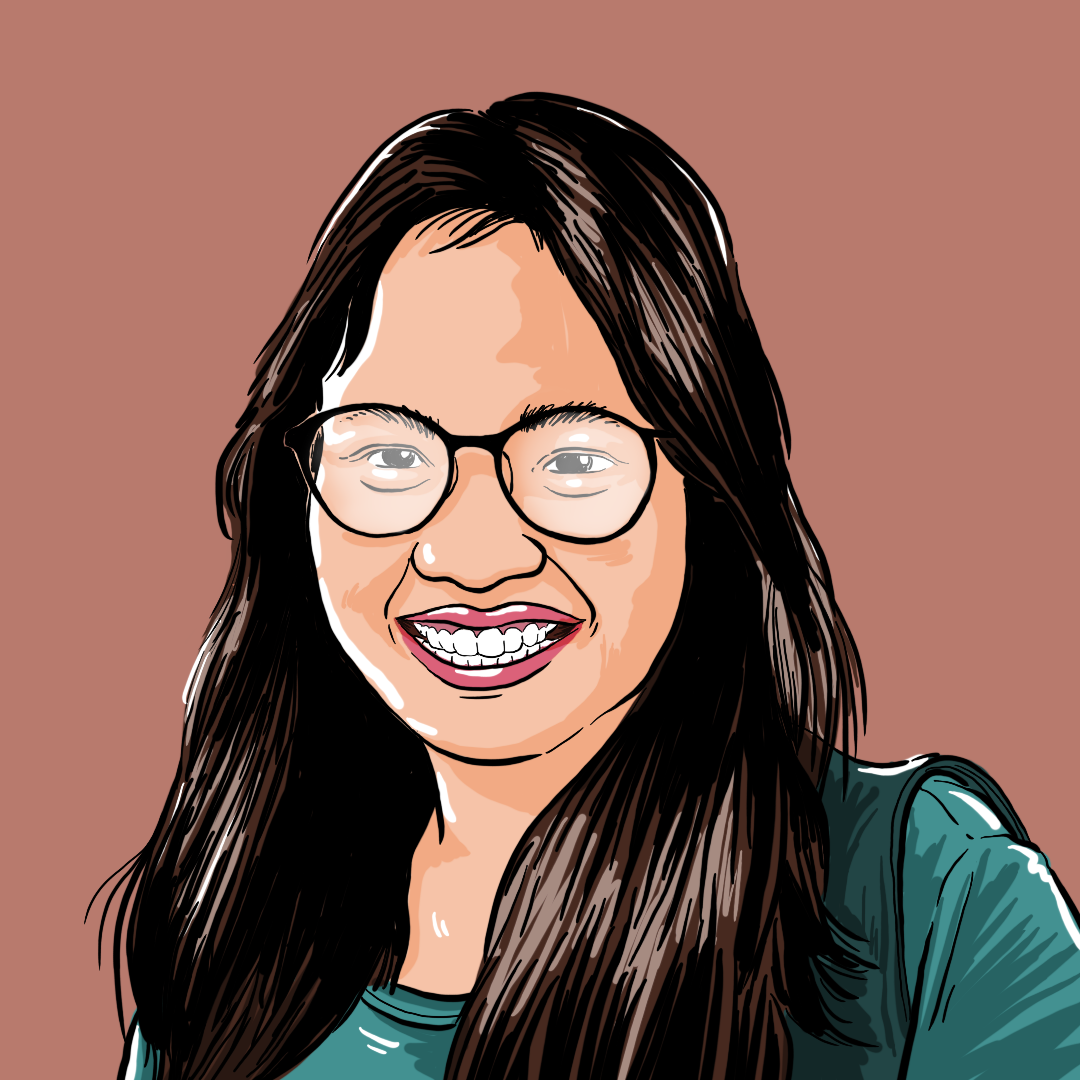Kantor berita Prancis France Inter dan Mediapart pada Mei 2016 mengungkap skandal kekerasan seksual yang dilakukan Wakil Ketua Parlemen Prancis, Denis Baupin. Laporan yang memuat delapan pengakuan korban tersebut berhasil mendesak Denis untuk mundur dari jabatannya.
“Kami bisa menerbitkan cerita itu karena kami punya delapan korban, dengan empat di antaranya on the record,” kata jurnalis Mediapart, Lenaig Bredoux dalam seminar daring Global Investigative Jounalism Network (GIJN) bertajuk Investigating Sexual Abuse: Reporting Tips & Tools pada Kamis, 12 November 2020.
Dalam peliputan kekerasan seksual, menurut Bredoux, pengakuan korban merupakan salah satu penentu keberhasilan. Jurnalis perlu menemukan sebanyak-banyaknya korban, sekalipun kasus tersebut sudah berlalu bertahun-tahun. Dengan begitu jurnalis dapat menemukan pola dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik, seperti Denis Baupin.
“Memang akan sangat sulit jika hanya ada satu testimoni korban,” paparnya.
Pengakuan para korban, lanjutnya, bisa dikonfirmasi lewat bukti-bukti dokumen seperti laporan resmi institusi, pesan teks, surat elektronik, kontak masuk sosial media, pesan suara, foto, maupun catatan harian korban. Apabila dokumen tersebut tak dapat diraih, maka upaya konfirmasi bisa dilakukan kepada saksi yang mengetahui kejadian.
“Penyintas kerap menghapus pesan mereka dengan pelaku, tetapi lebih sering mereka menceritakan itu kepada orang terdekatnya. Kamu bisa menemukan percakapan tentang kekerasan itu dengan orang lain,” katanya.
Menemui banyak korban, kata Bredoux, sama pentingnya dengan menemui banyak saksi. Dalam hal ini, keterangan saksi tak harus selalu berkaitan dengan peristiwa. Latar belakang pelaku yang kerap melancarkan percakapan maupun candaan seksis tentang tubuh dan pakaian perempuan juga bisa digunakan untuk memperkuat cerita tentang kejahatan seksual.
Bredoux membedakan antara peliputan kejahatan seksual dengan investigasi kasus lain. Dalam kasus kekerasan seksual, korban merupakan sumber utama. Karenanya jurnalis tetap perlu menjaga jarak, skeptis sembari memahami bagaimana kondisi psikologis korban. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendapat kepercayaan korban ialah keterbukaan. Para jurnalis disarankan untuk menyampaikan secara terbuka kepada korban tentang bagaimana kasus tersebut akan diungkap.
“Anda harus menyampaikan bahwa aku percaya, tetapi aku perlu mengumpulkan bukti. Mengapa bukti-bukti itu perlu sebab di ujung kamu akan wawancara pelaku,” ungkapnya.
Pendekatan serupa juga dilakukan jurnalis lepas di China, Sophia Huang. Menurutnya, jurnalis harus mengungkap perihal sumber berita yang akan digunakan, apakah itu keterangan rekan-rekan, keluarga maupun orang-orang terdekat korban.
“Risiko juga harus disampaikan, misalnya orang bisa saja menyalahkan korban dan mengecek kehidupan personal korban setelah tulisan dipublikasi,” katanya.
Situasi kekerasan seksual di China, menurutnya, sangat memprihatinkan. Pada 2017, ia menemukan 416 atau 83,7 persen jurnalis mengalami kekerasan seksual di tempat kerja. Dari kasus tersebut, hanya 3,2 persen yang melapor kepada institusi maupun pihak berwajib. Sementara, hanya ada tiga kasus yang terpublikasi. Kondisi tersebut tak berbeda jauh dengan lingkungan kampus. Hasil survei terhadap 6.000 mahasiswa menunjukkan bahwa sekitar 70 persen dari mereka mengalami kekerasan seksual.
Sayangnya, menurut Sophia, tidak semua korban mampu bicara. Oleh sebab itu, menjadi tugas jurnalis untuk meyakinkan para korban bahwa yang menimpanya lebih dari masalah pribadi.
“Hindari menyalahkan korban, pahami faktor struktural dari pelecehan. Jangan tanyakan mengapa kamu tidak menghentikan pelaku, mengapa kamu tidak panggil polisi. Saya tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu,” ia menyarankan.
Sebab lain yang membikin penyintas kejahatan seksual di China membisu ialah praktik pembungkaman yang dilakukan pemerintah. Gerakan #MeToo di China pada Juli 2018 lalu dianggap mengganggu stabilitas dan keamanan negara karena memprovokasi penyintas bicara terbuka lewat media sosial maupun membikin laporan polisi. Pemerintah China kemudian menghapus pengakuan korban di internet dan melabeli mereka sebagai ancaman keamanan nasional.
Selain para korban, sejumlah pihak yang membantu korban juga diancam pasal terkait pencemaran nama baik. “Anda harus pergi ke pengacara, meminta nasihat. Ada banyak kasus temannya membantu menyebarkan informasi tapi dikenai pencemaran nama baik,” katanya.
Sementara di India, jurnalis lepas, Ashwaq Masoodi mengungkapkan bagaimana pembagian kelas sosial dan budaya masih menghambat pelaporan kejahatan seksual. Padahal sejak 2012, India sudah merevisi Undang-Undang Kekerasan Seksual dan Pemerkosaan. Dalam UU ini, definisi pemerkosaan diperluas sehingga dapat menjerat pelaku penetrasi selain alat kelamin. Menurutnya, penetrasi jari tanpa konsensus dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan. Meski begitu, tidak sedikit korban yang memilih bungkam.
”Beberapa lapisan yang dia kenal (keluarga atau organisasi sipil) harus saya cari,” ujarnya.
Itu sebab, Ashwaq mengaku bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mendekati para korban. Ia kerap mengerem kehendak untuk langsung menanyakan seputar kasus.
”Dalam melakukan liputan, saya secara konstan mengingatkan diri saya bahwa mereka yang berbaik hati pada saya dan pembaca saya dengan menceritakan kisah mereka. Itu membantu saya menghormati hak mereka memilih bercerita atau tidak. Itu pilihan mereka,” paparnya. (Debora Blandina Sinambela)