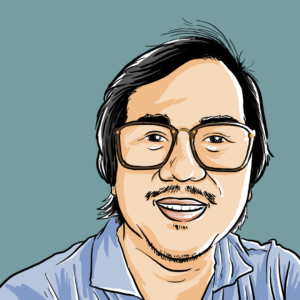Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Perkara ini bernomor 79/PUU-XVII/2019. Mahkamah menilai dalil pemohon tidak beralasan seturut hukum. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara virtual, Selasa, 4 Mei 2021.
Sebelumnya, mantan Ketua KPK Agus Rahardjo dan sejumlah bekas pimpinan KPK periode sebelumnya, seperti Laode M. Syarif, Saut Situmorang, Erry Riyana Hardjapamekas, Moch. Jasin dan lainnya mengajukan permohonan uji formil terhadap UU KPK. Mereka menilai revisi UU KPK tidak memenuhi rambu-rambu pembentukan undang-undang. Antara lain tidak melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pembahasan yang tidak transparan dan tidak melibatkan publik, rapat paripurna DPR yang tidak kuorum, hingga tidak ditandatanganinya UU KPK oleh Presiden Joko Widodo.
Dalam putusannya, Hakim MK menyebut DPR sudah membuka ruang diskusi terhadap revisi UU KPK sejak 2017. Dengan begitu, tidak adanya partisipasi publik dianggap tidak beralasan. Di samping itu, Hakim MK menyebut UU KPK juga sudah masuk prolegnas.
Sementara mengenai tidak ditandatanganinya UU KPK oleh Presiden Jokowi, Mahkamah menyatakan UU itu konstitusional karena sudah lewat 30 hari sejak disetujui DPR dan Presiden. “Dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum,” kata Hakim MK lain, Saldi Isra.
Satu Pendapat Beda Hakim MK
Meski begitu, keputusan Hakim MK dalam perkara ini tidak bulat. Salah satu hakim, Wahiddudin Adams menyatakan dissenting opinion atas putusan uji formil UU KPK yang diajukan sejumlah orang termasuk Agus Rahardjo. Wahiduddin menyoroti singkatnya waktu pembahasan revisi UU KPK. Padahal revisi tersebut mengubah banyak hal, termasuk struktur dan fungsi KPK secara fundamental.
“Perubahan ini sangat nampak sengaja dilakukan dalam jangka waktu yang relatif sangat singkat serta dilakukan pada momentum yang spesifik,” kata Wahiduddin membacakan pandangannya, Selasa, 4 Mei 2021.
Wahiduddin menjelaskan momentum spesifik itu antara lain pengesahan yang dilakukan jelang masa bakti DPR periode 2014-2019 berakhir dan beberapa pekan sebelum Joko Widodo-Jusuf Kalla mengakhiri jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Akibatnya, masyarakat tidak punya banyak waktu berpartisipasi dalam pembentukan UU baru KPK tersebut. “Serta sangat minimnya kajian dampak analisis terhadap pihak yang akan melaksanakan undang-undang a quo, in casu KPK,” kata dia.
Meski begitu, Wahiduddin mengakui bahwa hal itu tidak secara langsung menyebabkan UU KPK hasil revisi inkonstitusional. Sebab prosedur pembentukan UU KPK telah ditempuh oleh pembentuk UU. “Namun yang sejatinya terjadi adalah hampir pada setiap tahapan prosedur pembentukan undang-undang a quo terdapat berbagai persoalan konstitusionalitas dan moralitas yang cukup serius. Dalam konteks ini diperlukan suatu pembacaan mendalam guna menilai konstitusionalitas pembentukan undang-undnag a quo,” tambahnya.
Wahiduddin juga mengaku tidak mendapat penjelasan yang dapat diterima akal sehat terkait percepatan penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM). Ia bertolok pada kronologi rapat kerja pertama pembahasan revisi UU KPK pada 12 September 2019, sedangkan rapat panitia kerja pertama digelar sehari setelahnya. Penyusunan DIM yang super cepat itu, katanya, mengakibatkan berkurangnya partisipasi masyarakat. Padahal sesuai Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Presiden punya waktu selama 60 hari setelah menerima RUU tersebut untuk merumuskan pendapat maupun DIM.
“Saya tidak menemukan argumentasi dan justifikasi apapun yang dapat diterima common sense bahwa suatu perubahan yang begitu banyak dan bersifat fundamental terhadap lembaga sepenting KPK disiapkan dalam bentuk DIM kurang dari 24 jam,” ujarnya.
Mantan Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM ini juga menyoroti sikap Presiden Jokowi yang tidak menandatangani UU KPK hasil revisi. Serta tidak singkronnya naskah akademik dengan revisi UU KPK. “(Ini) menyebabkan terjadinya absurditas praktik ketatanegaraan dan semakin terpeliharanya praktik pembentukan undang-undang yang tidak didasarkan pada budaya yang membiasakan adanya justifikasi,” turut Wahiduddin.
Selain Agus Rahardjo dkk, ada enam pemohon lain yang mengajukan uji konstitusionalitas UU KPK hasil revisi. Salah satunya ialah Fathul Wahid, Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada perkara bernomor 70/PUU-XVII/2019 ini, MK mengabulkan separuh gugatan. Salah satunya Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b dan Pasal 47 ayat (2) UU KPK terkai Dewan Pengawas KPK. Menurut MK, frasa ‘dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga MK mengubahnya menjadi:
“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungiawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diberitahukan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.”
Sementara terkait penghentian penyidikan alias SP3 oleh KPK, Mahkamah menilai lembaga antirasuah tetap perlu memiliki kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU KPK. “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun,” begitu bunyi Pasal 40 ayat (1). MK menilai aturan batas waktu maksimal 2 tahun dalam pasal tersebut tidak jelas, sehingga MK menambahkan frasa “dihitung sejak terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP),” dalam keputusannya.
MK Pertahankan Status ASN
Mahkamah Konstitusi dalam putusanya hari ini, Selasa, 4 Mei 2021 menegaskan bahwa KPK berada dalam rumpun eksekutif. Namun, MK mengubah Pasal 1 (3) UU KPK yang sebelumnya berbunyi “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang Undang ini” menjadi “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi, bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”
Dengan demikian, lembaga antirasuh akan tetap melanjutkan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sesuai UU Nomor 19/2019, alih status pegawai KPK menjadi ASN diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN. Pegawai KPK yang ingin menjadi ASN harus melaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak bersedia menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat beralih menjadi PPPK dengan jabatan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” sebagaimana tertuang dalam Perkom 1/2021.
Terkait alih status ini, MK memerintahkan agar pemerintah memberikan jaminan kepastian kepada pegawai KPK. Pasalnya selama ini pegawai KPK telah berdedikasi memberantas tindak pidana korupsi. “Mahkamah perlu menegaskan dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana UU 19/2019 tidak boleh merugikan hak pegawai KPK,” kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih di Gedung MK, Selasa, 4 Mei 2021.
Tercatat sudah ada lebih dari 1.300 pegawai KPK yang mengikuti seleksi menjadi ASN. Bahkan hasil seleksi yang dimulai pada Maret lalu itu telah diserahkan kepada KPK pada akhir April lalu. Disinyalir sedikitnya ada puluhan orang yang tidak lolos seleksi menyangkut wawasan kebangsaan (TWK), Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.
Menanggapi hal itu Direktur Eksekutif Amnesty International di Indonesia, Usman Hamid menilai seleksi pegawai di KPK harus dilakukan dalam koridor kompetensi. Artinya, tes wawasan kebangsaan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menyingkirkan pegawai KPK yang punya pandangan politik berbeda dengan pemerintah. “Itu sama saja mundur ke era pra-reformasi. Tepatnya pada 1990 ketika setiap pegawai negeri harus melalui litsus atau penelitian khusus atau bersih lingkungan yang diskriminatif,” ujar Usman dalam siaran pers yang diterima Jaring.id.
Hal ini, menurut Usman, sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional maupun hukum di Indonesia di mana pekerja harusnya dinilai berdasarkan kinerja dan kompetensinya. Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menjamin hak pekerja untuk mendapatkan kesempatan sesuai dengan kemampuannya. “Hak atas kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan.”
Selain itu, hak individu untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan telah dijamin Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang isinya: “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.”
Sementara dalam hukum nasional, hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan berkeyakinan telah dijamin dalam Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 29 (2) tentang kebebasan beragama dan beribadah dan pasal 28E (2) tentang kebebasan berkeyakinan di mana setiap orang berhak menyatakan pikiran dan sikap mereka sesuai dengan hati nuraninya.
Sedangkan Pasal 153 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebut bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja dengan alasan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). “Berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan.”
Definisi tentang diskriminasi ini juga telah dijabarkan dalam Konvensi ILO tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1999. “Mendiskriminasi pekerja karena pemikiran dan keyakinan agama atau politik pribadinya jelas merupakan pelanggaran atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan berkeyakinan. Ini jelas melanggar hak sipil dan merupakan stigma kelompok yang sewenang-wenang,” tegas pengajar HAM di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ini.