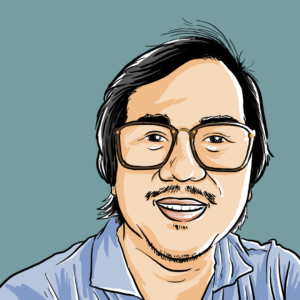Pelanggaran atas kebebasan sipil di Papua begitu dekat dengan budaya kekerasan, dan impunitas. Hal itu bisa terlihat dari kasus-kasus pelanggaran hak asasi. Mulai dari aksi teror terhadap jurnalis, duka warga sipil dalam konflik, penembakan dan pembunuhan sistematis, pembungkaman lewat pasal makar, sampai penggunaan pasal karet UU ITE dalam kasus rasisme. Sampai hari ini, tidak sedikit pembela HAM yang terjerat pasal-pasal karet. Di antaranya pernah menimpa Assa Asso. Ia harus dihukum 10 bulan penjara karena dianggap menghasut massa untuk berdemonstrasi pada 2019 lalu.
Di atas secarik kertas berukuran A5 Assa Asso menulis “I’m Not Monkey. I’m Makar.” Pernyataan itu ditulisnya menggunakan tinta saat ditahan di rumah tahanan Polda Papua empat tahun lalu. “Ini tulisan sa saat dipenjara,” kata Yally—panggilan akrabnya, lewat Whatsapp disertai emoticon tertawa.
Yally ditangkap polisi pada Senin, 23 September 2019. Sineas yang juga fotografer Papuan Voice’s tersebut dituding melakukan makar dan penghasutan lewat media sosial. Ia kemudian divonis penjara selama 10 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Abepura, Jayapura. “Saya itu sebenarnya kena UU ITE, tapi karena kapasitas penyidik yang kurang baik jadi saya dikenai Pasal Makar,” ungkapnya kepada Jaring.id dan Suara.com, pada Senin, 14 Agustus 2023.
Penangkapan Yally terjadi siang di Jalan Raya Abepura. Saat itu, Yally Tengah mengendarai sepeda motor setelah mengantar seorang kawan ke Bandara Sentani. “Waktu itu flight pagi. Pukul enam waktu Papua,” jelasnya. Jelang siang, Yally memacu sepeda motornya ke arah Kota Jayapura. Jarak antara bandara dengan Jayapura tidak terlalu jauh. Sekira hampir 30 kilometer. Tapi di tengah jalan ia melihat sejumlah polisi dan tentara bersiaga di perbatasan Kota dan Kabupaten Jayapura.
Penjagaan yang dilakukan pasukan gabungan itu merupakan imbas dari gelombang aksi demonstrasi warga dan mahasiswa di pelbagai wilayah di Papua dan Papua Barat. Aksi protes berlangsung sejak pertengahan Agustus hingga akhir September 2019. Pihak polisi menganggap bahwa situasi masih mencekam setelah terjadi huru-hara di kota.
Di Abepura, ratusan mahasiswa di sejumlah daerah berkumpul di Auditorium Universitas Cenderawasih (Uncen). Sementara di Kota Jayapura, Sorong, dan Merauke massa melakukan long march memprotes tindakan kekerasan terhadap sejumlah mahasiswa di Asrama Mahasiswa Papua, Kalasan, Surabaya, Jawa Timur yang terjadi Jumat, 16 Agustus 2019. Para pengunjuk rasa juga menuntut polisi agar membebaskan mahasiswa Papua yang ditahan.
Kemarahan warga Papua atas tindakan rasial tersebut berangsur memanas. Mula-mula terjadi di Manokwari pada 19 Agustus 2019. Kerusuhan berikutnya pecah di kota-kota lain seperti Sorong, Fakfak, Timika, Deiyei, dan Jayapura hingga September. Beberapa kendaraan dan bangunan dibakar massa. Antara lain gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat dan ruang pamer mobil di Manokwari.
“Putar balik! Putar balik!” teriak polisi saat Yally melintas menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro ke arah Kota Jayapura. Yally kemudian memilih memutar arah.
Empat polisi berpakaian preman lantas mengejarnya hingga Jalan Sentani. Mereka menghadang laju sepeda motor Yally menggunakan mobil Toyota Avanza, lalu turun menodongkan pistol ke kepala. “Dalam perjalanan saya diikuti Polisi. Setelah dikejar dan saat ditangkap saat itu mereka bilang ko ni juga salah satu orang Papua yang ikut demo-demo di sana? Mengapa ko mau jalan,” tuturnya menirukan perkataan polisi.
“Abang sa ini tidak ikut terlibat di aksi,” jawab Yally sambil mengangkat kedua tangan. “Sa dari Bandara Sentani di batas kota disuruh balik, sa balik. Sore kalau su kondusif sa akan balik ke Abepura,” jelasnya dengan dialek setempat.
“Hei, ko diam! Nanti ko bicara di sana saja!” timpal polisi merujuk Mako Brimob Kotaraja, seperti ditirukan Yally.
Namun, “karena sa sendiri, sa diam. Sa ikuti dong pu mau,” ungkapnya menceritakan kronologis kejadian penangkapan saat itu. “Ternyata ada dua teman di dalam itu, ditangkap di jalan juga. Padahal orang yang tidak terlibat dalam aksi tanggal 23 September,” lanjutnya.
Dua polisi kemudian menghampiri Yally, mereka menariknya ke ruang interogasi di sebuah ruangan di kantor pemerintahan setempat. Mereka ditahan selama tiga jam di sana. Sekitar pukul 14.30 Yally dibawa ke Mako Brimob Kotaraja. “Sa dapat pukul empat kali. Dia tendang kaki sa dua kali, di belakang dua kali,” ungkapnya menceritakan tindak kekerasan interogasi selama 8 jam di sebuah ruangan khusus.
Sore hari itu ratusan mahasiswa sudah dikumpulkan di lapangan Mako Brimob Kotaraja saat Yally diturunkan dari mobil. Polisi berpakaian preman kembali menghardik. “Buka baju ko,” cetusnya. Yang diperintah duduk di lapangan bergabung bersama ratusan mahasiswa yang ditangkap.
Di lokasi tampak Pangdam XVII/Cenderawasih, saat itu, Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab. Sekira pukul 17.30 WIT jenderal asli Papua itu memanggil Yally. “Nanti adik-adik sebentar pulang, tidak ditahan,” ucapnya.
Meski begitu, Yally dan tujuh orang lain tak dibiarkan pulang. Penyidik menuduh Yally sebagai dalang di balik aksi demonstrasi berujung ricuh di sekitar kantor gubernur Papua pada 29 Agustus 2019 lalu. ”Saya tidak terlibat aksi,” ia bersikukuh untuk kesekian kali, tapi polisi bergeming.
“Kalau tanggal 19 Agustus 2019 memang sa turut ikut, karena itu aksi yang damai kami lakukan,” tambahnya.
Polisi kemudian mengangkut Yally bersama tujuh orang lain menggunakan mobil tahanan dengan tangan diborgol. Sekitar pukul 02.30 WIT mereka tiba Polda Papua. “Kami disuruh tidur di dalam satu ruang penyidik. Tangan kami diikat dengan kursi. Jadi satu orang diikat tangan dengan kursi,” ungkapnya. “Kami di sana itu hari tidak diberi makan satu pun,” lanjutnya.
Keesokan harinya, Selasa, 24 September 2019, tiga penyidik Polda Papua melanjutkan pemeriksaan pada pukul 9.00 WIT. Kata dia, pemeriksaan kali kedua itu berlangsung lebih dari 15 jam atau hingga pukul setengah satu malam waktu setempat. Polisi mencecar Yally dengan pertanyaan yang tak sanggup ia jawab. Antara lain terkait keberadaan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), hingga keterlibatan orang-orang dalam perjuangan Papua Merdeka. “Saya diinterogasi. Tanpa didampingi pengacara.” imbuhnya.
Yally ditahan di dalam ruang berukuran 3×5 meter bersama 13 tahanan lain setelah interogasi maraton. “Di sel Rutan Polda Papua,” jelasnya. Karena ruang sel yang teramat sempit membuat para tahan tidur dalam kondisi duduk. Ada pula yang tidur berdiri sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Rabu, 25 September 2019.
Hari itu, penyidik memeriksa sejumlah akun media sosial Yally. Mulai dari Facebook, Instagram, Twitter hingga Whatsapp. “Silakan periksa saja. Karena HP di tangan abang dorang,” ucap Yally. “Sa tidak terlibat sama sekali dengan aksi. Apapun juga upload di tanggal 19 Agustus tidak ada sama sekali,” ujarnya menegaskan.
Malang baginya ketika mengetahui ada 13 pasal yang hendak menjerat. Antara lain Pasal 106 KUHP, Pasal 87 KUHP, Pasal 110 KUHP, Pasal 14 Ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 66 UU Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 160 KUHP, Pasal 187 KUHP, Pasal 365 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 2 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 64 KUHP, dan Pasal 29 KUHP.
“Nah di sini ada pasal penghasutan, makar, pemalangan, perusakan, pembawaan alat tajam. Itu semua masuk dalam 13 pasal,” beber Yally.
Salah satu barang bukti yang dijadikan dasar penyidik ialah unggahan status di Facebook. Yally sempat menulis status berisi ajakan untuk berunjuk rasa. “Besok wajib libur diri dan lumpuhkan kota para kapital & colonialism Indonesia. Jika Anda merasa diri martabat direndahkan, kau adalah sesungguhnya ciptaan yang mulia dan sempurna,” begitu tulisnya.
Meski begitu, Yally kukuh tidak terlibat mengorganisasi aksi 29 Agustus 2019. “Karena sa itu lagi di Papua Nugini.”
***
Sehari sebelum peringatan kemerdekaan Indonesia pada 2019, sejumlah mahasiswa Papua yang tinggal di asrama Jalan Kalasan Nomor 10, Tambaksari, Surabaya mengalami tindakan rasisme berupa makian ’monyet.’ Tindakan rasis itu terjadi setelah mahasiswa dikepung massa reaksioner lantaran dituduh merusak bendera merah putih yang dipasang aparatur daerah setempat di sekitar asrama.
Selama masa pengepungan, para mahasiswa mengalami pelbagai tindak kekerasan. Aparatur keamanan menembakkan gas air mata beberapa kali ke dalam asrama. Hingga puncaknya 43 mahasiswa digelandang ke Polrestabes Surabaya. Wakapolrestabes Surabaya, saat itu, AKBP Leonardus Simarmata menyebut penangkapan sebagai upaya polisi memeriksa dugaan perusakan bendera. ”Kami lakukan upaya penegakan hukum terhadap peristiwa terhadap lambang negara, yaitu bendera merah putih yang ditemukan patah kemudian jatuh ke got,” kata Leo, Sabtu, 17 Agustus 2019.
Sebelum pengepungan dan penangkapan tersebut sempat terjadi peristiwa lain di asrama yang sama. Sejumlah polisi, TNI, Satpol PP, beserta camat setempat malam-malam mendatangi asrama yang tengah menggelar diskusi tentang film “Biak Berdarah.” Mereka beralasan hendak melaksanakan operasi yustisi terhadap warga luar Surabaya.
Niat tersebut sontak membikin orang-orang yang ke acara diskusi mempertanyakan. Salah satunya ialah Anindya Shabrina. Ia bersama rekannya, Isabella didampingi oleh Muhammad Soleh pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya berusaha menanyakan surat tugas pelaksanaan operasi yustisia. Alih-alih menunjukkan surat tugas, aparat keamanan malah makin berkeras membubarkan diskusi. Mula-mula, hanya Isabella dan Soleh yang diseret paksa menjauh dari pintu gerbang asrama. Lalu Anin diperlakukan serupa sembari dibentak dengan kata-kata kasar. Bahkan ia mengalami pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh polisi.
Tak terima dengan perlakuan aparat, Anin kemudian mengambil telepon genggamnya sembari membuka laman akun Facebook. Di sana ia mengunggah kronologi intimidasi, tindak kekerasan dan pelecehan yang menimpa dirinya. Pengakuan daring ini yang kemudian viral dan dibaca ribuan kali dalam kurun waktu sehari. ”Saat itu saya unggah karena banyak berteman dengan jurnalis. Setelah itu banyak jurnalis datang ke lokasi kejadian,” ujar Anin pada Jumat, 18 Agustus 2023.
Tapi pihak Polrestabes Surabaya malah menerbitkan surat perintah penyidikan tanpa meminta keterangan dari Anin. Anin dituduh melakukan pencemaran nama baik sesuai Pasal 27 ayat 3 UU ITE jo. Pasal 45 ayat 3 UU ITE dan menyebarkan kebencian sesuai Pasal 28 ayat 2 jo. Pasal 45A ayat 2 UU ITE. Ia diperiksa penyidik sebanyak 7 kali. Namun, kasusnya tidak pernah selesai.
Makar tak Makar asal Makar
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Maria Magdalena Sitanggang menjatuhi vonis 10 bulan penjara kepada Yally pada Jumat, 3 Juli 2020. Namun dalam putusan tersebut, Yally dianggap tak melakukan tindak pidana makar. Ia hanya bersalah melakukan penghasutan seperti diatur dalam Pasal 160 KUHP.
“Di Papua ini tanah statusnya politik. Jadi siapapun orang Papua entah itu bicara Papua merdeka atau tidak, aktivis atau bukan, ketika ditangkap dalam situasi seperti itu, pasal makar adalah jalan satu-satunya yang biasa mereka gunakan,” tutur Yally.
“Karena bukti yang mereka ambil itu melalui handphone. Foto-foto atau gambar bermotif Bintang Kejora ketika sudah dapat di handphone berarti itu sudah masuk di makar,” ia menambahkan.
Aparat penegak hukum, kata Yally, tidak pernah melihat siapa melakukan apa. Apalagi mempertimbangkan konstruksi pasal yang mesti diterapkan terhadap orang-orang yang ditangkap berdasar perbuatannya. “Namanya orang Papua itu wajib hukumnya itu makar,” seloroh Yally tertawa.
Perkara makar sekaligus ITE yang menimpa Yally ialah satu dari sekian banyak kasus di Papua. Lembaga pemerhati HAM, Amnesty International Indonesia mencatat sedikitnya 61 kasus yang melibatkan 111 orang Papua. Mereka didakwa dengan pasal makar sepanjang 2016-2019. Sementara pada awal Januari-Juli 2023 sudah ada tiga mahasiswa Papua, yakni Ambros Fransiskus Elopere, Devio Tekege, dan Yoseph Ernesto Matuan yang ditangkap lalu didakwa melakukan tindak pidana makar.
Ambros, Devio, dan Yoseph ditangkap usai menggelar mimbar bebas bersama sekelompok mahasiswa lainnya di halaman Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) pada 10 November 2022. Kegiatan yang mereka gelar secara damai ditanggapi dengan aksi kekerasan dan penangkapan oleh aparat keamanan.
Sebelumnya, ada nama Ferry Pakage dan juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo. Victor dihukum 8 bulan penjara sekalipun lepas dari tuduhan makar. Ia dinilai hanya menyebarkan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia. Sementara kasus yang menimpa Ferry bermula dari siaran langsung lewat Facebook. Ketika itu, Ferry dianggap memprovokasi mahasiswa Universitas Cenderawasih melakukan pembakaran bendera putih saat berunjuk rasa pada Oktober 2020. Ia dijerat dengan pasal terkait SARA dalam UU ITE.
Nama lain yang sempat tersangkut pasal karet ITE di Papua ialah Jefry Wenda. Juru bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) ini diciduk polisi bersama beberapa orang lain karena mengunggah percakapan dengan Kasat Intelkam Polresta Jayapura mengenai izin berunjuk rasa terkait rencana pemekaran Papua Tengah dan Pegunungan. Beruntung, kasus tersebut tidak berlanjut. Jefry dibebaskan tidak lebih dari sehari. ”Itu tidak lama. Karena langsung dibebaskan. Hanya 1X24 jam karena minim bukti,” ungkap Jefry saat dihubungi Jaring.id akhir November 2022.
Sementara kasus makar yang menimpa Ambrosius Mulait bermula dari sebuah peristiwa di depan Istana Negara pada 28 Agustus 2019. Ambo—begitu ia disapa, bersama lima orang lain; Surya Anta Ginting, Anes Tabuni alias Dano Anes Tabuni, Charles Kossay, Ariana Elopere alias Wenebita Gwijangge, dan Isay Wenda dianggap melanggar Pasal 160 Juncto Pasal 110 KUHP karena mengibarkan bendera Bintang Kejora di tengah aksi masyarakat dan mahasiswa Papua memprotes rasisme.
“Sampai hari ini juga saya belum tahu orang siapa yang bawa bendera, karena tiba-tiba bendara naik,” ungkap Ambo.
***
“Dano dan Charles ditangkap, dibawa ke Polda Metro Jaya,” tulis Yumilda Kaciana alias Chika dalam grup WhatsApp bernama “Monyet se-Jakarta” pada Jumat, 30 Agustus 2019 malam.
Grup WA tersebut berisi mahasiswa Papua di Jakarta, sengaja dibuat untuk memudahkan koordinasi menyikapi tindakan rasialis yang terjadi terhadap kawan-kawan mereka di Asrama Mahasiswa Papua, Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, pada 16 Agustus 2019.
Setelah menyebar informasi itu, Chika dan 14 penghuni asrama Lanny Jaya di Depok, Jawa Barat menyusul suaminya Dano dan Charles ke Polda Metro Jaya.
Setibanya di Mapolda Metro Jaya, Chika diterima oleh Kasubdit Keamanan Negara Ajun Komisaris Besar Dwi Asih. “Kami mau ketemu Dano dan Charles,” pinta Chika. “Tidak bisa, mereka baru bisa ditemui sesudah satu kali dua puluh empat jam.” Dwi Asih menolak.
Chika tak mau buang-buang waktu berdebat. Mereka langsung beranjak keluar dan menunggu di trotoar depan Mapolda Metro Jaya. Seorang polisi berpakaian preman sempat menghampiri, meminta Chika dan rekan-rekannya pulang. Bahkan, polisi itu mengakui bersedia menanggung biaya taksi untuk pulang.
“Pulang saja. Kamu kan cewek, kasihan kalau begini,” katanya. “Yang ditahan itu suami saya. Masa saya pulang sebelum lihat dia,” sanggah Cika yang saat itu harus menunggu semalaman hingga sore sehari berselang.
Lalu salah seorang polisi mengizinkan lima perwakilan korban penangkapan masuk. Mereka adalah Isay Wenda, Ambrosius Mulait, Musa Mabel, Sehi Hillapok, dan Felis dari KontraS.
“Ini Ambros ya? Kamu Isay?” tanya penyidik menunjuk Ambo dan Isay. “Sudah yang lain keluar.” Penyidik memperlihatkan surat dan langsung menangkap mereka.
“Jadi statusnya saya dan Isay sudah tersangka. Pasal 106 makar Juncto 110 KUHP,” ungkap Ambo mengingat kejadian sore itu. Negara mungkin berpikir setelah menangkap dan melabelinya dengan status penjahat ‘politik’ akan menghentikan aktivisme Ambo dalam memperjuangan hak-hak kebebasan orang Papua. Tapi kenyataannya tidak.
“Setelah ada penangkapan yang lainnya itu saya pikir justru saya tambah jadi berani untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah di Papua,” jelas Ambo.
Negara menurutnya melakukan cara-cara itu untuk membungkam kritik atas ketidakadilan yang terjadi di Papua. Tak hanya kepada orang asli Papua, tapi juga terjadi kepada orang luar. Ia kemudian menyebut nama Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty. “Jadi memang upaya negara ini secara sistematis dilakukan di Papua,” kata Ambo.
Haris dan Fatia yang disebut Ambo ialah dua orang pembela HAM yang mesti menghadapi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam kasus dugaan pencemaran nama. Mereka didakwa dengan Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, Pasal 14 Ayat 2 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, serta Pasal 310 KUHP.
Kasus ini terkait dengan konten video di akun YouTube milik Haris berjudul ‘Ada lord Luhut di bali relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam’. Dalam video tersebut Haris dan Fatia membahas kajian cepat dari Koalisi Bersihkan Indonesia bertajuk ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya.’ Kasus Haris dan Fatia sampai saat ini masih berlangsung.
Pada Jumat, 24 April 2020, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Purwanto memvonis bersalah lima terdakwa makar. Kecuali Isay, Ambo dan beberapa kawannya dipenjara selama 9 bulan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat.
“Saya kehilangan momen waktu anak saya lahir,” ungkapnya lirih mengingat kelahiran Alfiora Astrella Wenearek Harhege Mulait yang lahir 10 Mei 2020 atau 16 hari sebelum Ambo bebas.
Beda Makna ITE di Papua
Maraknya penggunaan pasal makar dan ITE di pelbagai daerah, termasuk di Papua dianggap berlawanan dengan komitmen Negara memperbaiki situasi hak asasi manusia. Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid mengatakan kondisi HAM terakhir terbilang suram karena kebebasan sipil menyusut. Sementara budaya kekerasan dan impunitas terutama di Papua dan Papua Barat meningkat. “Negara masih menunjukkan sikap represif atas warganya di Papua yang hanya menggunakan hak mereka dalam berekspresi dan berkumpul yang dijamin di konstitusi,” ungkap Direktur Eksekutif AII, Usman Hamid.
Oleh sebab itu, ia menyerukan agar pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencabut Pasal 106 dan 110 KUHP. Ia berharap pasal-pasal tersebut tidak lagi digunakan untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, di luar batas yang diizinkan hukum HAM Internasional. “Kami memandang pembatasan hak atas kebebasan berekspresi yang dikenakan Pasal 106 dan 110 KUHP melampaui pembatasan yang diizinkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia,” ujar Usman.
Alih-alih menimbulkan efek gentar terhadap aktivisme politik mahasiswa dan aktivis Papua, penggunaan pasal makar justru akan menguatkan persepsi publik bahwa negara telah melakukan kesewenang-wenangan. “Selain itu juga menegaskan kegagalan aparat keamanan negara dalam membedakan perlakuan terhadap aktivis yang menyuarakan aspirasi politiknya di Papua melalui ekspresi pendapat yang damai dan mereka yang mengejar tujuannya melalui penggunaan atau ancaman kekerasan,” tutur Usman.
“Amnesty International tidak mengambil posisi apa pun tentang status politik provinsi mana pun di Indonesia, termasuk seruan kemerdekaan. Namun, menurut kami, kebebasan berekspresi termasuk hak untuk secara damai mengadvokasi kemerdekaan atau solusi politik lainnya, asal tidak melontarkan hasutan dengan tujuan mendiskriminasi, memusuhi atau menyulut kekerasan,” imbuhnya.
Senada dengan Usman, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay menilai penggunaan pasal makar maupun ITE sebagai bentuk diskriminasi terhadap orang-orang Papua. “Pasal makar ini dalam penerapannya menggunakan sistem peradilan pidana yang saya simpulkan itu dipraktekkan secara diskriminatif,” ujarnya.
”Ketika pasal makar ini digunakan polisi untuk menjerat orang-orang yang bicara isu Papua atau orang Papua, itu sangat cepat dan langsung berujung pada putusan pengadilan,” ia menambahkan.
Ia berharap pemerintah tidak lagi menggunakan pasal karet UU ITE dan pasal terkait makar untuk menjerat orang-orang Papua. Ia meyakinkan bahwa pendekatan hukum tidak akan menuntaskan pelbagai masalah yang ada di Bumi Cendrawasih. ”Semestinya Negara ini sudah tidak harus menggunakan pasal makar untuk menyelesaikan konflik politik di Papua. Negara ini harus berpikir lebih maju. Apalagi negara ini sudah berpengalaman menyelesaikan konflik politik di Aceh, konflik politik di Timor Leste,” ia menerangkan.
Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi lembaga pemerhati hak-hak digital, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Nenden Sekar Arum mengungkapkan motif penggunaan UU ITE di Papua lebih spesifik ketimbang daerah lain di luar Papua. “Apa sih motif atau background-nya sehingga seseorang itu dilaporkan dengan UU ITE?”.
Bila di Jawa kasus ITE berawal dari konflik antar tetangga, pelayanan publik, dan bisnis, maka di Papua sebagian besar kasus lebih ke arah politis. “Sedangkan kalau di Papua sendiri walaupun kita lihat biasanya memang sangat politis. Jadi karena perbedaan pandangan politiknya lah kemudian dia sangat rentan dilaporkan dengan UU ITE atau pasal makar atau pasal-pasal lain yang berpotensi untuk mengkriminalisasi ekspresi,” ungkap Nenden.
Selama tahun 2022 ini, UU ITE digunakan pada setidaknya 37 kasus pelanggaran atas kebebasan berekspresi dengan 46 korban. Sebelas kasus diantaranya merupakan hasil patroli polisi virtual.
Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Polisi Ignatius Benny Ady Prabowo mengklaim tidak ada perlakuan berbeda maupun pengamanan khusus polisi di Papua. Dalam hal pengamanan demonstrasi, misalnya, kepolisian menggunakan pola dan skema yang sama seperti daerah lain. “Secara umum sama. Artinya kita melihat kekuatan dari massa. Jadi minimal itu harus sebanding kekuatan,” kata Benny.
Adapun pelibatan aparat TNI, kata Benny, itu dikhususkan untuk membantu mengamankan objek-objek vital. Dalam pelaksanaannya dilakukan bersama anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital atau Ditpam Obvit. “Kita juga siapkan kekuatan cadangan, itu untuk mengantisipasi apabila butuh tambahan di lapangan,” katanya.
Benny mengakui pola pengamanan yang digunakan banyak mengambil pelajaran dari pengalaman aksi demonstrasi besar-besaran 2019 lalu. Salah satunya pola penyekatan terhadap titik-titik lokasi yang biasa dijadikan tempat berkumpul massa.
“Pengalam dari kejadian di 2019 itu upaya yang tetap kita terapkan sampai sekarang itu penyekatan. Jangan sampai mereka berkumpul menjadi satu, mereka kan biasa tempat berkumpulnya di beberapa titik ya. Jadi itu kita sekat jangan sampai bergeser, berkumpul dengan titik-titik lainnya menjadi kekuatan yang lebih besar,” ungkapnya. “Kita juga patroli siber ada, dan kalau memang ini ditemukan yang memprovokasi ya kita pasti melakukan upaya penegakan hukum,” imbuhnya.
Namun, Benny mengklaim penegakkan hukum harus didasari dengan bukti. Ia menampik adanya kriminalisasi. “Semuanya pasti harus ada bukti-bukti. Kita memang benar-benar bukan dengan upaya kekerasan. Tapi memang kita benar-benar penegakkan hukum,” tegasnya.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi peliputan antara Jaring.id dan Suara.com yang mendapat dukungan dari Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN).
Tim Kolaborasi
Penanggung Jawab: Fransisca Ria Susanti (Jaring.id); Reza Gunadha (Suara.com)
Penulis: Abdus Somad (Jaring.id); Agung Sandy Lesmana dan Muhammad Yasir (Suara.com)
Penyunting: Damar Fery Ardiyan (Jaring.id); Reza Gunadha (Suara.com)
Ilustrasi: Ali (Jaring.id); Suara.com