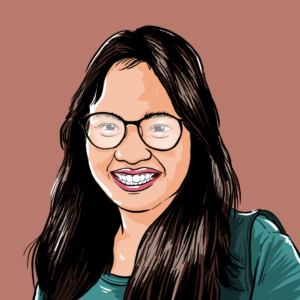Jakarta, JARING.id – Gubernur Jambi Zumi Zola terseret kasus suap dan korupsi setelah tiga anak buahnya terciduk Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) November 2017 lalu. Ia diduga menerima uang dari kontraktor dan memberikannya sebagai “uang ketok” kepada anggota DPRD Jambi ketika pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi (RAPBD) Jambi Tahun 2018.
Zumi adalah satu dari dua kepala daerah yang ditangkap karena korupsi, sekaligus penyuapan anggota DPRD. Kasus sama pernah menimpa mantan walikota Bekasi Mochtar Mohamad pada 2011 lalu.
Berselang dua minggu pengumuman Zumi sebagai tersangka oleh lembaga anti rasuah itu, giliran Bupati Lampung Tengah Mustafa ikut jejaknya. Mustafa resmi menjadi tahanan KPK sejak 16 Februari 2018. Polanya hampir sama, diawali penangkapan anak buah dan anggota DPRD yang menerima suap, lalu menyusul si kepala daerah.
Kejadian ini membuat semakin panjang daftar kepala daerah dan anggota legislatif yang ditangkap KPK. Dari data KPK yang dikumpulkan JARING dalam rentang 2011-2018, sudah 8 kepala daerah ditangkap karena memberikan suap dalam pembahasan APBD kepada 58 anggota legislatif daerah. Pembahasan APBD menjadi kasus dengan total tersangka paling banyak, mencapai 66 orang yang didominasi anggota DPRD.
Sementara kepala daerah mendominasi kasus korupsi seperti menerima hadiah atau janji dari proses perizinan, promosi jabatan, pengadaan barang dan jasa, mark-up proyek dan penyalahgunaan APBD. Kepala daerah yang ditangkap karena kasus ini mencapai 34 orang, sementara anggota DPRD 2 orang. Total tersangka kasus korupsi ini sebanyak 36 orang yang didominasi kepala daerah.
Di luar itu, 12 kepala daerah ditangkap karena kasus lain seperti penyuapan jaksa atau hakim dalam perkara pidana dan sengketa pemilihan kepala daerah. Sehingga dari seluruh kasus, total 57 kepala daerah dan 60 anggota legislatif yang ditangkap KPK. Artinya sudah 117 aktor politik daerah menjadi tersangka korupsi dalam rentang 8 tahun.
Anomali Dukungan Mayoritas
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, mengatakan jika melihat pola korupsi secara institusional, kepala daerah cenderung berperan sebagai pemberi suap dan anggota DPRD sebagai penerima. Salah satu penyebabnya karena metode untuk menghasilkan peraturan daerah (perda) terkait APBD atau non-APBD diutamakan melalui konsensus, bukan voting.
Metode konsensus mendorong kepala daerah mengupayakan dukungan sebanyak-banyaknya dari fraksi di DPRD. Upaya mendapat dukungan inilah sering jadi alasan kepala daerah menyuap fraksi dengan mengandalkan sumber-sumber dana “ilegal” seperti korupsi dalam perizinan, lelang jabatan, pengadaan barang dan jasa, proyek, mark up, dan penyalahgunaan APBD.
“Kalau perizinan dan segala macam, itu wilayahnya eksekutif. Kalau di DPRD, sumber institusional dia untuk memperoleh pendapatan tidak resmi atau ilegal memang dari persetujuan APBD. Jadi wajar anggota DPRD yang korupsi banyak terkait dengan pengesahan APBD,” kata Djayadi saat dihubungi Selasa, 27 Februari 2018.
Apabila persoalan dukungan menjadi alasan yang memaksa kepala daerah menyuap anggota DPRD, semestinya kepala daerah yang diusung partai dengan kursi mayoritas di dewan, tak perlu terseret suap menyuap.
Misalnya Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari, 5 partai yang mengusungnya maju di Pilkada 2011 berhasil memenangkan 28 dari 45 kursi di pemilihan legislatif 2014. Artinya persentase dukungannya mencapai 62 persen di legislatif, ketika dia dan 12 orang anggota dewan ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus suap pengesahan LPJ 2014 dan pengesahan APBD 2015.
Walaupun jumlah kursi di dewan tampak berpihak padanya, tetap saja Pahri kesulitan mengambil keputusan sehingga harus mengandalkan uang “pelicin”. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pernah melakukan analisis tingkat kesulitan pengambilan keputusan menggunakan indeks effective number party in parliement (ENPP). Semakin kecil indeks ENPP (<3) maka lebih mudah mengambi keputusan karena partai dominan tidak lebih dari tiga. Sebaliknya, semakin besar indeks ENPP (>5) , maka semakin sulit pengambilan keputusan karena banyaknya partai dominan di DPRD. Dengan memakai formula matematis yang diajukan Laakso dan Taagepera (1979), Indeks ENPP Musi Banyuasin mencapai 8.
Secara teoritis, tingginya indeks ENPP berakibat dua hal, pertama konflik antara eksekutif-legislatif berkepanjangan yang berujung pada deadlock. Kedua, terjadinya korupsi politik yang melibatkan eksekutif dan legislatif dalam wujud sistem kepartaian yang terkartelisasi. Dalam konteks Indonesia, deadlock dalam perumusan kebijakan publik kepala daerah dengan DPRD hampir jarang terjadi.
“Dengan kata lain, suap kebijakan dilakukan untuk mempermudah pembahasan kebijakan publik di tengah kondisi DPRD yang tidak sepaham. Suap ini dapat dijadikan instrumen dasar bagi kepala daerah terpilih untuk memuluskan perda ataupun APBD yang diusulkan oleh pemerintah daerah dan memerlukan persetujuan DPRD,” demikian rilis Perludem berjudul Prospek Pemerintahan Hasil Pilkada Serentak 2015 pada 29 Februari 2016.
Akan tetapi muncul masalah baru lagi ketika anggota legislatif dari 5 partai pendukung Pahri juga ikut menerima suap. Seharusnya Pahri tidak perlu menyuap partai pengusungnya, cukup menyuap partai oposisi dalam kondisi tingginya fragmentasi partai di DPRD. Kepala daerah yang memberikan suap kepada koalisinya dalam pengesahan APBD juga terjadi di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara.
Politik Berbiaya Tinggi
Direktur Eksekutif Sindikasasi Pemilu dan Demokrasi, August Melasz, berpendapat salah satu penyebab tingginya korupsi di daerah sebagai dampak dari sistem pemilu yang mahal. Sistem pemilu yang dibangun saat ini lebih menonjolkan personalisasi aktor, sehingga kandidat kepala daerah atau calon anggota legislatif harus menanggung biaya pencitraannya agar populer dan dipilih.
Ditambah lagi, Indonesia tidak punya skema pendanaan partai politik yang jelas. Ketika pemilu, biaya kampanye dibebankan pada kandidat. Partai perannya hanya sebagai kendaraan.
“Pada akhirnya orang dipaksa untuk mencari sumber pendanaan apapun, apakah yang berasal dari konsesi dan cukong-cukong di daerah ataupun yang sudah punya jabatan harus menegoisasikan dengan pihak yang memang terlibat dalam proses formal pengambilan kebijakan,” katanya ketika dihubungi Selasa 27 Februari 2018.
Apabila data 34 kepala daerah yang korupsi diuraikan lebih rinci, 13 diantaranya masih terkait dengan pemilu. Ada yang baru terpilih, mencalonkan kembali atau salah satu anggota keluarganya mencalonkan. Akan tetapi sebagian besar, 21 kepala daerah tidak dalam tahun pemilu.
August menambahkan kebutuhan politik para politis tidak hanya saat pemilu saja. Tapi merawat kosntituen sebagai kebutuhan interaksi politik membutuhkan komponen pembiayaan. Sampai sekarang tidak pernah diketahui bagaimana kebutuhan itu terbiayai. Pendanaan partai, kontestasi pemilu dan interaksi dengan konstituen masih dianggap sebagai tanggung jawab kandidat.
Partai juga tidak membangun skema pelibatan publik dalam pendanaan. Sependapat dengan itu, Djayadi menilai sistem keanggotaan partai tidak berkembang sehingga masyarakat tidak mau menyumbang partai. Apalagi jika ditarik ke masalah ekonomi, kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat masih bermasalah.
“Beda kalau kita pergi ke Amerika. Di Amerika kalau ada calon kepala daerah atau calon legislatif yang bagus, maka dia akan ngomong ke masyarakat dan masyarakat akan ramai-ramai membiayai. Ini kebalik,” katanya.
Meskipun bantuan keuangan partai politik naik menjadi seribu rupiah per suara, bantuan itu hanya menutup 10 persen keperluan operasional partai. Selebihnya, selama ini publik hanya bisa menduga-duga dan cenderung berburuk sangka terhadap sumber keuangan partai, selain dari setoran-setoran kepala daerah dan anggota legislatif.
Pendanaan Partai dari Negara
August menilai harus ada kenaikan bantuan kepada partai dari negara secara bertahap. Bantuan tidak harus berupa pendanaan, namun bisa komponen lain yang setara nilainya dengan kebutuhan partai.
Di antara banyaknya komponen pendanaan partai harus diprioritaskan mana yang terlebih dahulu didanai. Misalnya tahap awal, pemerintah memberikan pendidikan profesionalitas. Tahap berikutnya, pemerintah bisa intervensi pendanaan musyawarah-musyawarah partai di daerah.
Parpol juga harus mengubah strategi untuk kursi publik dan jabatan politik. Kalau selama ini dibebankan pada kandidat, porsinya harus dikurangi dan diambil alih partai. Mengenai mahalnya sistem pemilu saat ini, alternatifnya mengubah sistem atau mahalnya sistem itu kemudian diminimalisir.
“Sistem pemilu kita berbiaya mahal dan itu bebannya ke personal. Makanya untuk membiayai itu semua, kalau nggak ada skema yang baku dan terbuka, kita nggak akan pernah tahu. Situasi semacam ini akan terus muncul dan percayalah daftar di KPK akan tetap numpuk,” paparnya.
Arie Sujito, sosiolog Universitas Gadjah Mada dan Peneliti Senior IRE, mengatakan, kenyataannya sistem pilkada langsung berdampak pada tingginya biaya politik. Calon maupun partai politik harus didorong melakukan biaya politik rendah dan adanya sistem yang mendorong partai bertanggung jawab terhadap kadernya yang terlibat korupsi.
Agar tidak semakin banyak pemerintah daerah yang terjerat korupsi, perlu upaya pencegahan yang melibatkan sebuah sistem dan tidak hanya terfokus pada penindakan. Penindakan semata tidak akan pernah mengurangi pelaku korupsi.
Tren penangkapan pejabat daerah oleh KPK sejak 2011-2018 secara umum mengalami kenaikan signifikan. Dalam rentang tahun 2013-2014, grafik sempat mengalami penurunan, namun kembali naik dari 2015-2017. Bahkan hingga awal Februari 2018, sudah ada 10 kasus penangkapan.