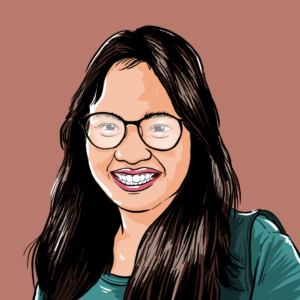Meski menyoroti pasal-pasal karet UU ITE, Presiden Joko Widodo enggan memasukkan revisi UU ITE dalam daftar prioritas program legislasi nasional di DPR. Pemerintah mengklaim pembahasan revisi UU ITE akan dilakukan setelah tim kajian merampungkan proses publik hearing.
Upaya mediasi antara dua pengajar di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Aceh, Saiful Mahdi dan Taufiq Saidi berakhir buntu. Saiful yang merupakan dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik karena kritiknya di sebuah grup Whatsapp. Ia dilaporkan ke polisi oleh Taufiq yang kini menjabat Dekan Fakultas Teknik di universitas yang sama dengan Pasal 27 (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Kasus Saiful sendiri bermula pada Maret 2019 ketika ia mengkritik hasil penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala melalui grup WhatsApp ‘Unsyiah Kita’ pada 2018 lalu. Kepada Jaring.id, Saiful mengaku tengah menunggu proses kasasi di Mahkamah Agung. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis dirinya tiga bulan penjara dengan denda Rp 10 juta subsider 1 bulan penjara dalam 18 kali sidang.
Dalam proses persidangan itu, Saiful mengatakan sempat meminta agar Taufiq menarik gugatan. Namun, mediasi yang difasilitasi sejumlah aktivis di Banda Aceh tersebut tak berbuah hasil. Dari tiga poin kesepakatan yang disodorkan, menurut Saiful, hanya dua yang disepakati. Pertama ialah ralat secara terbuka dan masing-masing pihak menyampaikan permohonan maaf tanpa perlu menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Sementara yang ketiga, yakni penarikan laporan dari kepolisian maupun kampus ditolak.
“Saya sama pelapor hampir setuju (berdamai), tetapi di akhir pelapor menarik diri dari kesepakatan dengan alasan poin ketiga tidak bisa dipenuhi,” ujar Saiful mengenang proses hukum yang dialami pada 2019 lalu, ketika diwawancara pada Kamis, 25 Februari 2021.
Pertemuan di Banda Aceh tersebut menjadi satu-satunya mediasi antara Saiful dengan pelapor. Sementara kepolisian dan kejaksaan tidak menggelar pertemuan serupa. Ketika diperiksa sebagai saksi di kepolisian, Saiful justru disarankan meminta maaf kepada pelapor agar kasusnya bisa dihentikan. “Itu sama saja dengan permintaan awal pelapor, saya harus minta maaf. Masalahnya banyak korban UU ITE yang kami perjuangkan adalah kebenaran. Kritik adalah sebuah kebenaran, kalau kita minta maaf seolah-olah kita yang bersalah,” katanya.
Saiful enggan meminta maaf. Ia tidak ingin permintaan maaf tersebut dijadikan alat bukti untuk melanjutkan kasus secara pidana. Terlebih, menurutnya, pelapor maupun kepolisian tidak menjamin akan menghentikan kasus setelah permintaan maaf tersebut disampaikan.
Kondisi itu yang dianggap Koordinator Paguyuban Korban UU ITE, Muhammad Arsyad akan berulang meski Kepala Kepolisian Indonesia Jendral Listyo Sigit Prabowo menerbitkan telegram yang berisi instruksi penanganan perkara UU ITE. Surat Edaran SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif ini memuat 11 poin penanganan kasus UU ITE. Antara lain terkait dengan mediasi terhadap kasus ujaran kebencian termasuk pencemaran nama baik, fitnah maupun penghinaan. “Memedomani Pasal 27 (3) Undang-undang ITE, Pasal 207 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP,” demikian tertulis dalam TR bernomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 bertanggal 22 Februari 2021.
Di samping itu, kasus tindak pidana yang berpotensi memecah belah bangsa, seperti SARA, kebencian terhadap golongan, agama atau ras dan etnis bisa diselesaikan melalui mediasi maupun dengan cara restorative justice. “Memedomani Pasal 28 (2) UU ITE, Pasal 156 KUHP, Pasal 156a KUHP, Pasal 4 UU Nomor 40 Tahun 2008, serta tindak pidana penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran memedomani Pasal 14 ayat 1 UU No 1 Tahun 1946.”
“Artinya proses mediasi tidak menguntungkan korban, malah yang diuntungkan adalah pelapor dengan tuntutannya itu difasilitasi,” ujar Arsyad kepada Jaring.id.
Dalam hal ini Arsyad mencotohkan kasus yang pernah menimpa Stela Monica. Dia dituduh mencemarkan nama sebuah klinik kecantikan di Surabaya mengunggah kritik lewat di media sosial. Padahal saat itu, menurut Arsyad, Stela hanya mengeluhkan dan mengunggah tangkapan layar percakapan tentang kondisi wajahnya yang mengalami iritasi setelah menjalani perawatan selama berbulan-bulan. Akibat tidak menemui kata sepakat dalam proses mediasi, Stela ditetapkan sebagai tersangka karena tidak bisa memenuhi tuntutan pelapor yang memintanya untuk memasang iklan produk selama tiga hari di media nasional beserta uang hingga Rp 2 miliar. “Sehingga hak dasar korban lebih terampas,” ujarnya.
Arsyad menyatakan bahwa hal ini terjadi karena dalam proses mediasi sangat jarang dihadirkan pihak penengah yang netral. Kata dia, pihak penengah seharusnya tidak berasal dari kepolisian maupun kejaksaan. “Dari 100 kasus yang ada, kemungkinan hanya 1-10 kasus yang proses mediasinya netral dan tidak menghilangkan hak dasar terlapor,” tambah Arsyad.
***
Pengalaman pahit yang menimpa Stela Monica dan Saiful Mahdi hanyalah sebagian kecil dari cerita korban penerapan UU ITE. Sepekan sebelum Presiden Jokowi mengutarakan niatnya untuk merevisi UU ITE, atau tepatnya pada 8 Februari 2021, Isma Khaira Binti Hasyim Ali dihukum tiga bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, Aceh. Ia ditahan di Lapas Lhoksukon bersama bayi usia enam bulan atas laporan Baktiar selaku Kepala Desa Pineung lantaran menyebarkan video perseteruan terkait sengketa tanah antara Isma dengan kepala desa ke grup WhatsApp keluarga dan Facebook.
Lembaga perlindungan hak digital, SAFEnet (Southeast Asian Freedom of Expression Network) mencatat 292 kasus terkait UU ITE sepanjang 2018. Jumlah yang didapat dari putusan online Mahkamah Agung ini dua kali lipat dibanding 2017 yang hanya 140 kasus. Jumlah kasus di 2018 bahkan melebihi total kasus sejak 2011 sampai 2017, yakni 216 kasus.
Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi (SAFEnet), Ika Ningtyas melihat bahwa SE Kapolri belum dapat menjadi obat mujarab yang berpihak pada korban. Terlebih poin D dalam SE tersebut mengintruksikan kepada penyidik untuk dapat membedakan hoaks, kritik dan pencemaran nama baik. “Namun tidak semua penyidik memiliki kapasitas yang sama. Pemahanan terhadap kritik, hoaks dan pencemaran nama baik itu. Ini akan berbahaya ketika penyidik diberi kekuasaan untuk menginterpretasi sendiri,” ujar Ika melalui sambungan telepon pada Kamis, 25 Februari 2021.
Hal lain yang mengancam kebebasan ekspresi warga dari instruksi Kapolri tersebut ialah terkait dengan patroli siber lewat pengiriman peringatan (virtual alert). “Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber,” demikian instruksi Kapolri yang tercantum dalam poin C.
Ika menilai patroli yang akan dilakukan Dittipidsiber tersebut tak ubahnya sebagai praktik baru pengawasan untuk menakut-nakuti warganet. Dalam SE tersebut polisi hanya memberi waktu tidak lebih dari 24 jam untuk warganet menurunkan unggahan atau konten yang berpotensi melanggar tindak pidana siber. Sayangnya, menurut Ika, operasi siber tersebut tidak dibarengi dengan pembukaan ruang pembelaan warganet terhadap klaim hoaks maupun ujaran kebencian yang disematkan oleh polisi.
“Percakapan dunia maya kita itu semakin diawasi oleh polisi. Ini menjadi ketakutan baru bagi warganet. Polisi sudah hadir langsung di ranah privat kita. Akhirnya hak kebebasan berekspresi warga itu semakin tergerus,” ungkapnya.
Itu sebab, Ika menegaskan bahwa yang perlu dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini ialah mencabut pasal karet UU ITE alih-alih melakukan interpretasi terhadap pasal-pasal tersebut.
Adapun pasal-pasal bermasalah UU ITE, menurut Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Djafar antara lain Pasal 27 terkait asusila dan defamasi, 28 (2) memuat tentang ujaran kebencian, 29 ancaman kekerasan, 40 mengenai muatan yang dilarang dan pemutusan akses, serta Pasal 45 yang mengandung ancaman pidana tindakan defamasi atau fitnah. “Kalau sekarang kepolisian menerima setiap aduan terus disuruh kamu minta maaf. Kalau meminta maaf artinya dianggap memenuhi kualifikasi pencemaran nama baik, misalnya. Harusnya tidak begitu,” ujar Wahyudi kepada Jaring.id.
Menurut Wahyudi, dalam penerapan Pasal 28 ayat 2 penyidik kepolisian harusnya bisa memenuhi sejumlah unsur untuk menersangkakan seseorang. Antara lain adanya ajakan melakukan permusuhan, kekerasan, diskriminasi terhadap golongan tertentu berdasarkan suku, agama dan ras. Lalu memeriksa konteks ucapannya yang disampaikan terlapor, gramatikal hingga memeriksa niat terlapor. “SE ini belum menjawab persoalan yang dihadapi terutama implemetansi UU ITE,” kata dia.
Hal senada dijelaskan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati. Menurutnya, UU ITE merupakan masalah utama demokrasi yang tidak bisa dituntaskan oleh SE Kapolri. Oleh sebab itu, ia mewanti-wanti agar pemerintah tidak lagi melakukan interpretasi tetapi merevisi UU ITE. “PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sendiri sebenarnya mengarahkan penghinaan begini secara perdata. Kalau pun pidana, hukumannya bukan penjara, tetapi denda, minta maaf secara publik dan lain-lain,” ujar Asfi lewat telepon pada Kamis, 25 Februari 2021.
Sementara itu, Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo menyatakan bahwa pihaknya sampai saat ini masih mengumpulkan masukan sejumlah orang yang pernah bersinggungan dengan UU ITE. Kata dia, pelbagai narasumber baik yang berasal dari kalangan terlapor maupun pelapor banyak yang menyoroti penggunaan Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE. Dari diskusi tersebut pemerintah mendapat masukan bahwa UU ITE perlu mendapat kejelasan, baik norma maupun implementasi di lapangan.
“Masukan dan pandangan yang diberikan oleh narasumber nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi tim. Baik untuk sub tim 1 yang akan menghasilkan panduan, maupun bagi sub tim 2 yang akan mengkaji kemungkinan revisi,” ujar Sugeng pada Selasa, 2 Februari 2021.
***
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebelumnya membentuk dua tim kajian UU ITE yang akan bekerja hingga 22 Mei 2021. Tim pertama ialah pengarah yang akan berada di Kemenkopolhukam. Sementara tim pelaksana dari Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Hukum dan HAM. Kominfo akan masuk menjadi sub tim 1 yang disebut Tim Perumus Kriteria Penerapan UU ITE. Tim ini bertugas merumuskan kriteria implementasi terhadap pasal-pasal tertentu yang dianggap karet.
Pembentukan tim dilandasi oleh perintah Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar aparatur hukum lebih selektif menggunakan UU ITE. “Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas,” kata Presiden pada Senin, 15 Februari 2021 sebagaimana dikutip dari laman Sekretariat Negara.
Apabila keberadaan UU tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Presiden bahkan menegaskan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE. “Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ucapnya saat itu.
Namun tiga minggu berselang publik hanya mendapat indah kabar daripada rupa. Pemerintah dan DPR, resmi tidak memasukkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Selasa, 9 Februari 2021. Sementara satu-satunya partai politik yang mendukung revisi RUU ITE ialah Fraksi Demokrat.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly yang mewakili presiden dalam rapat tersebut menerangkan bahwa pemerintah tidak mengajukan revisi UU ITE dalam daftar prioritas. Pasalnya saat ini pemerintah masih menggelar public hearing yang dilakukan tim kajian UU ITE. Sehingga, kata dia, revisi UU ITE masih bisa saja menyusul untuk masuk dalam daftar.
“Ini lagi dibahas dan dilakukan public hearing. Ini kan ada kaitannya dengan RUU KUHP yang sudah kita bahas secara mendalam. Kebijakan kita adalah prolegnas dievaluasi per semester, maka lihat perkembangan selanjutnya (rencana memasukkan RUU ITE dalam Prolegnas 2021),” kata Yasonna dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.
Koordinator Paguyuban Korban UU ITE (Paku ITE), Muhammad Arsyad menyesalkan keputusan pemerintah yang tidak memasukkan UU ITE dalam daftar prioritas. Padahal, menurutnya, ada satu ruang kosong yang dapat digunakan untuk merevisi UU ITE setelah Rancangan Undang-Undang Pemilu dicabut dari prolegnas prioritas. “Hari ini sudah jelas bahwa apa yang dilakukan pemerintah jauh dari ucapan presiden. Ini berbanding terbalik,” kata Arsyad saat dihubungi Jaring.id, Selasa, 9 Februari 2021.
Meski begitu, para korban yang tergabung dalam Paku ITE tidak akan berhenti mendorong pencabutan UU ITE. Sebab selama UU ini berlaku, maka akan makin banyak orang-orang yang akan menjadi korban. “Setelah SE terbit polisi masih mengusut, baik terhadap orang yang sebelumnya terjerat maupun yang baru. Artinya apa? rencana revisi, maupun pembentukkan police virtual merupakan tindakkan diskriminatif dan pejabat atau orang yang antikritik akan tetap berjalan selama ada UU ITE. Tetapi ini lah hasilnya. Kekecewaan itu pasti ada tetapi itu bukan akhir,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi Hukum DPR, Arsul Sani menyampaikan bahwa rencana revisi UU ITE saat ini berada di tangan pemerintah. “Presiden sudah menyampaikan secara terbuka. Dalam hal ini kementerian terkait harus merespon,” ujar anggota dewan dari Fraksi PPP seperti dikutip dari kanal Youtube DPR RI, Rabu, 8 Maret 201.
Anggota Komisi Hukum lain, Sarifuddin Suding menyoroti pasal-pasal karet dalam UU ITE. Menurutnya, UU ITE perlu memuat definisi yang jelas agar para penyidik kepolisian mempunyai batasan yang jelas ketika memeroses laporan warga. “UU ini tidak ada batasan definisi yang jelas. Masalah kesusilaaan, penghinaan saya kira harus diperjelas dalam definsi sehingga aparat penegak hukum tidak lagi like dislike dalam prosesnya,” ungkapnya.