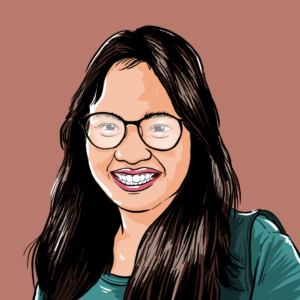Sebuah lukisan abstrak raksasa laksana terbentang di sepanjang lekukan Kali Code di bawah Jembatan Godolayu, Jl. Jenderal Sudirman, Yogyakarta. Sebuah kampung yang seluruh rumah dan atapnya dicat merah, biru, putih, kuning dan hijau dengan pola acak, pemandangan yang eksotik itu.
Menghadap ke kali, rumah-rumah itu dibangun berlapis-lapis. Tidak ada yang saling menutupi sebab kediaman yang di depan selalu lebih rendah. Cahaya matahari bisa menyusup ke setiap bangunan lewat jendela dan itu bisa mengeringkan kain-kain yang dijemur di teras.
Rumah paling dekat dengan sungai dibangun sejajar di atas tanggul setinggi 3 meter. Di depannya tersedia jalan kecil yang di ujungnya ada lapangan untuk olahraga.
Gapura yang lebarnya kira-kira 1,5 meter bertuliskan ‘Kampung Code RT01/RW01’ menjadi penanda sekaligus pintu masuk ke perkampungan ini. Kalau akan masuk ke dalam kampung ini kita menuruni tangga dan jalan semen berundak-undak yang berkelok mengikuti kontur tanah. Setiap rumah hanya bisa dijangkau lewat jalan kecil yang lebarnya muat 1 sampai 2 orang.
Pagi itu suasana tenang terasa di kawasan yang dihuni kurang lebih 60 kepala keluarga ini. Sayup-sayup terdengar suara aliran sungai di antara rintik hujan yang sejak subuh mengguyur Yogya. Seorang ibu menyapa dengan senyum sembari mencuci peralatan masaknya di sumur depan rumah.
Di utara berdiri sebuah rumah dua lantai yang terbuat dari anyaman bambu. Pemiliknya Aryanto, warga yang sudah 37 tahun menetap di kampung ini. Artinya, ia sudah bernukim di sana sebelum ada pengakuan secara administratif untuk kampung yang menjadi bagian dari Kecamatan Kotabaru.
Dulu kampung ini, menurut Aryanto, dikenal sebagai pemukiman kumuh yang dihuni pendatang yang mengadu nasib ke Yogya. Sebagian besar mereka bekerja sebagai pemulung dan buruh kasar. Mereka hanya mampu membangun rumah dari karton dan anyaman bambu yang kemudian dilapisi plastik penahan air.
Bantaran curam sehingga warga berlomba-lomba membuat rumah di area landai yang sangat dekat badan sungai. Naas, di penghujung 1983 banjir besar menyeret rumah yang terlalu dekat sungai. Buntutnya, pemerintah kota Yogyakarta kemudian meminta penghuni meninggalkan bantaran Code dan menetapkan kawasan tersebut sebagai tempat tidak layak huni.
Ada dua pilihan yang diberikan pemerintah ke warga waktu itu: pulang ke kampung halaman atau ikut program transmigrasi.
“Itu pilihan yang berat bagi kami karena kami tidak mampu tapi merasa nyaman di sini,” kata Aryanto.
Bersama warga, Romo Mangunwijaya, seorang rohaniwan Katolik, arsitek, dan sastrawan memperjuangkan Kampung Code agar tidak digusur. Dia menawarkan penataan kampung dan membangun hunian warga agar sesuai dengan kondisi sosial dan budaya. Penulis novel Burung-burung Manyar itu bahkan membuat rumah di tenpat yang paling dekat dengan sungai dan ia tinggal di sana. Dengan cara seperti itu ia ingin menjamin bahwa kediaman warga tak akan terkena banjir lagi jika saja mereka taat pada aturan yang telah disepakati.
Penataan dilakukan dengan menghilangkan rumah yang terlalu dekat dengan bantaran atau sekitar 3 meter dari bibir sungai. Kemudian rumah-rumah dibangun di atas bantaran dengan menghadap sungai. Konsep ini dikenal warga sebagai M3K: Mundur, Munggah [naik], dan Madep [menghadap] Kali.
Beberapa tempat yang di sana tidak boleh didirikan rumah, misalnya, bagian bawah dekat sungai. Maksudnya, supaya tidak terseret ketika banjir terjadi. Pula, kawasan itu bisa juga menjadi tempat bermain anak. Beberapa rumah tidak boleh terlalu tinggi supaya cahaya matahari bisa masuk.
Rumah-rumah bersahaja dan unik itu kemudian dicat indah sehingga menghilangkan kesan kumuh. Materialnya terutama kayu dan bambu. Tujuannya agar tanah yang konturnya curam tidak diberi tekanan berat sehingga longsor bisa dicegah. Romo Mangun punya tim khusus untuk mendisain rumah; tetapi warga tetap terlibat dalam perancangannya.
Fasilitas umum seperti kamar mandi, tempat mencuci, dan kakus dibangun agar warga tidak menggunakan air sungai lagi. Sumber airnya adalah sumur bor yang dibuat Romo Mangun. Letaknya agak jauh dari sungai sehingga cukup terbebas dari bakteri pencemar. Tak hanya bangunan fisik yang dibenahi; warga juga mendapat pembinaan terkait lingkungan dan hubungan sosial. “Sampai sekarang kampung ini dilestarikan dan menjadi salah satu pola penanganan kampung kumuh di kota lain,” ucap Aryanto.
Tahun 1990 kampung Code mendapat penghargaan Aga Khan Award for Architecture. Wajah kampung Code sudah jauh berbeda dari yang semula. Kehidupan warga pun ikut berubah. Sekolah menjadi tak asing lagi bagi mereka. Aryanto boleh berbangga sebagai angkatan pertama dari kampung itu yang bisa sekolah hingga ke perguruan tinggi.
“Generasi berikutnya sudah lebih baik. Keberadaan kami sudah banyak diakui. Warga kita banyak yang terlibat dalam organisasi dan LSM. Kalau saja jadi digusur dulu bisa jadi kita hidup di jalanan; belum tentu kita bisa bertahan di daerah asal.”
Letusan Gunung Merapi tahun 2010 membuat sungai penuh dengan material pasir sehingga air meluap ke rumah warga yang tinggal di bantaran sungai. Tapi tak satu pun kediaman tersebut terkena banjir di Kampung Code. Ini, menurut Aryanto yang juga aktif sebagai pemerhati Kali Code, membuktikan bahwa untuk mencegah banjir tidak melulu dengan menanam pohon di sepanjang bantaran sungai. Bagaimana mengatur interaksi yang baik antara warga kampung dengan sungai, juga merupakan jalan keluar yang tepat. “Kampung tak bisa meminta hak yang menjadi milik sungai karena suatu saat sungai pasti akan meminta kembali haknya yang diambil.”
Status kampung kumuh ditetapkan Pemda Daerah istimewa Yogyakarta lewat surat keputusan (SK). Setiap kampung berstatus kumuh kemudian mendapat anggaran agar secara perlahan statusnya bisa berubah ke arah yang lebih baik. Adapun Kampung Code, ia tidak beroleh SK tersebut. Artinya statusnya bukan kumuh lagi. Tentu saja ini membanggakan warganya kendati pada sisi lain mereka tak bisa beroleh anggaran dari pemerintah. “Kampung Code bukan kampung yang harus mengemis pada pemerintah lagi.”
Budaya Kampung
Di selatan Kampung Code terdapat Ledok Tukangan. Untuk masuk ke kampung ini kita harus melewati jalan beton yang curam. Kampung dan sungai hanya dibatasi jalan setapak dan tembok beton setinggi 1 meter. Kalau air sungai sedang naik, air akan masuk ke pemukiman warga lewat saluran pembuangan.
Di tepi sungai ini, sejak tahun 1999 berdiri Sanggar Anak Kampung Indonesia. Anang Nashicudin, Salah satu pendirinya, menjelaskan sanggar dibentuk agar warga setempat menjaga kampung. Pula agar anak muda di sana menyadari dan menghargai sejarah kampungnya.
“Harus ada gerakan anak muda untuk menghadapi ancaman terutama darurat agraria. Gerakan sosial dan budaya itu perlu agar kita tidak tergusur dari kampung kita,” ucap Anang.
Salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan anak muda di sanggar ini adalah perpustakaan yang menyimpan data-data tentang kampung. Cakupannya adalah data warga, peta tahunan, peta bencana, serta foto yang berhubungan dengan sejarah kampung. Beberapa agenda kegiatan tentang pendidikan publik, kesenian, dan workshop juga tersedia.
Kegiatan yang pernah dilaksanakan warga untuk menumbuhkan rasa kepemilikan kampung antara lain adalah ziarah ari-ari. Menurut budaya Jawa, setiap orang akan didampingi ari-arinya sejak ia lahir hingga selama menjalani kehidupan. Apa yang terjadi pada ari-ari akan terjadi pada orangnya juga.
“Kalau dalam filosofi Jawa, apa yang terjadi pada saya ada pengaruhnya pada kembaran saya, ari-ari. Ketika suatu saat ari-ari yang ditanam di depan rumah diambil dengan buldoser dan hilang, maka masa depan saya juga akan tidak jelas. Sederhananya, kami ingin membuat warga cinta tempat lahirnya ini.”