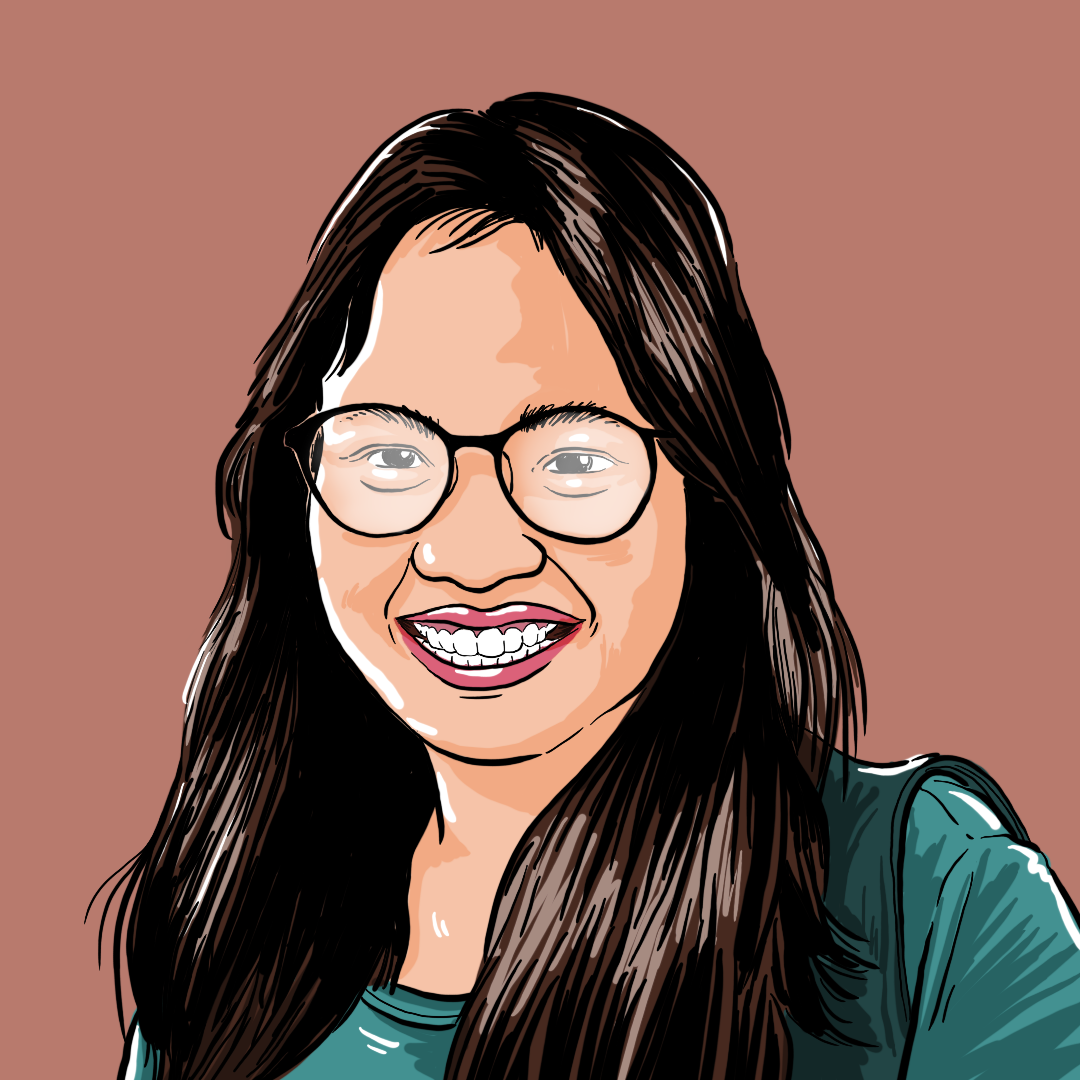Penduduk Jakarta terus bertambah secara eksplosif. Di tahun 1900, saat namanya masih Batavia, populasinya baru 150.000 jiwa. Penguasa Hindia-Belanda membangun sarana dan prasarana kota sesuai dengan kebutuhan warga sebanyak ini. Jalan raya berikut jembatannya, sistem sanitasi, dan kanal, terutama. Sampai hari ini infrastruktur ini umumnya masih berfungsi dengan baik dan tetap menjadi andalan kendati populasinya sudah berlipat-lipat.
Saat Indonesia merdeka tahun 1945 warga Jakarta sudah 623.343 atau bertambah lebih dari 4 kali lipat. Selain karena pertumbuhan alami, urbanisasi penyebabnya. Di zaman Jepang perekonomian begitu sulit—terutama akibat penyeragaman tanaman wajib serta peromushaan rakyat—sehingga banyak orang daerah pergi ke Ibukota untuk mengadu peruntungan. Di Jakarta sebagian mereka menjadi gembel yang berdiam di bawah jembatan dan di emperan toko.
Di tahun 1949, saat RI sudah berdaulat penuh, angka tadi sudah menjadi 1,34 juta. Jakarta yang telah kembali menjadi ibukota, menggantikan Yogyakarta, didatangi kaum migran dan pengungsi. Untuk seterusnya pengungsi terus mengalir akibat pergolakan yang terjadi di sejumlah daerah, terutama Jawa Barat dimana Darul Islam/Tentara Islam Indonesia—DI/TII—melancarkan aksi separatisme.
Tatkala Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden (5 Juli 1959) untuk mengambil penuh kekuasaan negara dari tangan pemerintahan kabinet parlementer, populasi Jakarta telah menjadi 2,8 juta jiwa. Angka ini menjadi 3,6 juta di saat sang proklamator sudah hampir terjungkal di tahun 1966. Selain karena pertumbuhan alami urbanisasilah penyebab pertambahan penduduk 800.000 selama Soekarno menjadi penguasa tunggal di negeri ini.
Untuk menyambut dua pesta olah raga akbar di tahun 1962, Asian Games dan Games of The New Emerging Forces (Ganefo, merupakan tandingan Olympiade), pemerintah membangun sejumlah infrastruktur raksasa sekaligus di ibukota. Termasuk kompleks olahraga Senayan, Hotel Indonesia, dan Jembatan Semanggi.
Ruas jalan Thamrin-Sudirman-Grogol juga diperlebar sehingga menjadi seperti yang kita lihat sekarang. Tenaga kerja yang banyak diperlukan untuk proyek gigantik ini. Kaum migran pun berdatangan untuk menjadi kuli bangunan serta tenaga kerja pendukung. Pun untuk menjadi pengasong makanan, kopi, dan rokok.
Soekarno akhirnya tumbang menyusul Peristiwa 30 September 1965. Soeharto menjadi penggantinya sejak 12 Maret 1967. Mantan Panglima Kostrad ini berkuasa hingga 21 Mei 1998. Selama 32 tahun menjadi kepala negara dia menyaksikan pertumbuhan populasi Indonesia yang terus membesar. Pencanangan program keluarga berencana yang ia lakukan di penghujung 1970-an tak bisa mengerem laju pertumbuhan penduduk yang sudah terlanjur tinggi. Di tahun 1998 populasi Indonesia sudah 203 juga. Penduduk Jakarta 7,8 juta jiwa.
Sejak masa Orde Baru Jakarta mengukuhkan diri sebagai kota terpadat di negeri ini dengan meninggalkan jauh kota lain termasuk Surabaya yang di zaman Hindia-Belanda, sebelum pelabuhan Tanjung Priok digali agar tak dangkal lagi, merupakan yang terbesar di Nusantara. Sebabnya adalah kebijakan ekonomi-politik yang diberlakukan pemerintah Soeharto.
Begitu berkuasa, Jenderal Soeharto mendekonstruksi kebijakan Soekarno terutama yang terkait dengan politik luar negeri dan strategi pembangunan. Ia merangkul kubu Barat yang lama menjadi seteru Soekarno dan menjadikan mereka pembimbing dan mitra utama.
Sesuai anjuran kaum teknokrat didikan AS—sebutannya kemudian: Mafia Barkley—Orde Baru mencanangkan strategi pembangunan yang berorientasi ke modernitas. Intinya, negara agraris Indonesia harus lekas ditransformasikan menjadi negara industri. Maka, pabrik-pabrik modern harus dihadirkan. Investor asinglah yang paling mungkin melakukan itu.
Soekarno acap berujar lantang “go to hell with your aid” ke negara-negara Barat yang mencoba merapat. Soeharto sebaliknya: ia membuka pintu lebar-lebar. Masih di awal berkuasa, tahun 1967, ia merangsang investor asing dengan memberlakukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. AS, Inggris, Jepang, dan yang lain segera masuk. Dua yang pertama ini merambah dunia pertambangan (lokasinya di luar P. Jawa), sedangkan Jepang manufaktur, khususnya kendaraan bermotor.
Orde Baru kemudian mendeklarasikan apa yang disebutnya sebagai trilogi pembangunan. Trilogi itu—sesuai prioritas—adalah: pertumbuhan ekonomi, stabilitas keamanan, dan pemerataan hasil pembangunan. Maksudnya, pertumbuhan ekonomi harus digenjot terlebih dahulu. Agar roda perekonomian lancar berputar stabilitas keamanan mesti senantiasa terjaga.
Ibarat pohon, pembangunan itu kelak akan berbuah. Ke seluruh rakyat Indonesia buah itu nanti dibagikan secara merata. Nyatanya, selama 32 tahun berkuasa pertumbuhan dan stabilitas keamananlah yang selalu dijaga Orde Baru, sementara pemerataan cenderung menjadi utopi saja.
Kehadiran para investor asing sejak masa awal Orde Baru membuat Jakarta langsung menggeliat. Di Ibukota inilah mereka mendirikan kantor pusat untuk kawasan Indonesia kendati proses produksinya di luar Pulau Jawa. Negara-negara Barat juga membuka kedutaan besarnya di tanah Betawi.
Pemerintahan Orde Baru sangat Jakarta sentris. Pajak termasuk dari korporasi asing dan perusahaan dalam negeri (BUMN-BUMD dan swasta) semuanya ditarik ke pusat. Daerah kemudian menerima alokasi sesuai dengan peruntukan yang disetujui Bappenas dan Departemen Keuangan.
Bukan hanya uang negara yang diatur Jakarta tapi juga orang yang patut menjadi pejabat di daerah pun. Pengistimewaan ini tentu saja sangat menguntungkan Ibukota. Wajar saja kalau kemajuannya di segala bidang lekas melampaui provinsi lain.
Di awal tahun 1970-an mendadak harga minyak global melonjak. Sebagai negara pengekspor minyak utama yang bergabung dengan OPEC Indonesia mendapat rezeki nomplok yang luar biasa besar. Jakarta jauh lebih berjaya lagi. Pembangunan yang sangat gencar di paruh ke-2 kegubernuran Ali Sadikin (ia memimpin Jakarta pada 1966-1977) tak terlepas dari bonanza minyak.
Di mana ada gula di situ ada semut, kata pepatah. Jakarta pun demikian. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di masa rezeki minyak telah menderaskan arus urbanisasi di Ibukota. Masalah perkotaan pun meningkat sebab pemerataan hasil pembangunan seperti yang diamanatkan trilogi itu tidak terjadi. Jakarta, pada sisi lain, juga menjadi pusat kemiskinan, penyakit, kejahatan (termasuk tindak kriminal dan korupsi), dan prostitusi di negeri ini.
Kaum elit Jakarta-lah yang paling menikmati buah pembangunan dan pinjaman luar negeri yang terus membesar. Mereka adalah para birokrat dan militer berposisi menentukan serta pengusaha yang berkoneksi ke penguasa. Sebagai gambaran, di Jakarta, misalnya, peningkatan pendapatan negara hanya 1,5% saja dinikmati 10% penduduk berstatus sosial-ekonomi terbawah; sedangkan yang dicecap 10% berpenghasilan tertinggi 43,4%.
Para pejabat ini, seperti diungkapkan sosiolog Hans-Dieter Evans (Sosiologi Perkotaan, LP3ES, 1995) melakukan korupsi secara masif. Mereka mencuci uang negara dengan menanamkannya di sektor yang lukratif. Mereka memburu tanah dan membangun properti. Awalnya mereka membeli lahan di daerah pinggiran Jakarta dan di daerah. Belakangan mereka semakin berani berinvestasi di Jakarta dengan membeli tanah serta membangun properti (hotel, rumah pribadi mewah yang kemudian biasanya disewakan ke kaum ekspatriat, villa, dan tempat rehat lain.
Pembelian tanah persawahan oleh para pejabat birokrasi dan militer itu telah memunculkan masalah tersendiri. Petani pemilik tanah dan buruhnya kemudian tergusur dari lahan pencariannya sekian lama. Ke kota mereka berpaling, terutama ke Jakarta yang gemerlapan.
Sebelum tahun 1970 ekspor utama Indonesia adalah hasil dari lapangan yang padat karya: pertanian dan perkebunan. Pada 1974-1976, di puncak boom minyak, ekspor negara kita 85% berasal dari lapangan yang ekstraktif yakni minyak bumi, gas, dan tambang mineral. Padat modal industri ini, bukan padat karya. Akibatnya lapangan kerja tradisional rakyat yang digeluti orang-orang desa banyak yang hilang. Urbanisasilah dampaknya. Jakarta yang telah menjadi metropolitan sungguhan tetap menjadi muaranya.
Kaum migran ini adalah kalangan yang kurang berpendidikan. Kalaupun berkeahlian, ketrampilan mereka tak jauh dari pengolahan tanah dan kelautan. Di Jakarta mereka menghadapi realitas pahit: Ibukota jauh lebih kejam daripada ibu tiri. Dunia industri tidak membutuhkan orang-orang yang bukan produk sekolahan. Untuk menjadi opas, kerani, dan orang suruhan di kantor (office boy) pun perlu besluit atau izajah setidaknya dari sekolah menengah.
Maka, kalau mujur, laki-laki bersekolah rendah paling menjadi kuli bangunan, tukang becak, atau pengasong. Bila peruntungannya jauh, kemungkinan besar mereka akan menjadi pemulung, pengemis, atau pengamen jalanan. Orang Jakarta menyebutnya ‘gembel’. Yang perempuan bisa menjadi babu (pembantu rumah tangga) atau pelacur.
Di Jakarta apa pun bisa menjadi duit. Jadi asal tidak malas kaum urban akan tetap bisa beroleh minimal sesuap nasi. Yang jauh lebih susah adalah mendapatkan pemondokan karena terbatas dan mahal untuk ukuran mereka. Kalau tidak punya uang dan keluarga atau kenalan untuk ditompangi alternatifnya adalah menjadi penghuni liar.
Tempatnya bisa di mana pun, termasuk di kaki lima toko, kolong jembatan, bantaran kali, sisi lintasan kereta api, taman, dan tanah kosong yang terlantar. Di sana, kalau beruntung, mereka bisa mendirikan gubuk darurat berbahankan kardus, plastik bekas, dan kain rombeng.
Gubernur Ali Sadin sempat membatasi arus migran ke Jakarta. Razia KTP ia galakkan. Ia juga menertibkan para penghuni liar. Kaum tuna wisma itu dijaring dan dibina sebelum dikirim ke provinsi lain sebagai transmigran. Ternyata langkah ini kemudian tersendat. Sebabnya? Orang kita selalu punya akal untuk memanipulasi apa pun. Program wajib ber-KTP Jakarta tak efektif sebab orang bisa memiliki kartu tersebut dengan ‘nembak’. Biaya transmigrasi mahal. Sementara rombongan yang pergi selalu digantikan oleh pendatang baru.
Di masa itu Pemda DKI pernah juga menyiapkan permukiman untuk kaum tuna wisma yang digaruk. Ternyata orang-orang yang tak asing dengan kediaman yang berlantaikan tanah dan beratapkan langit itu tidak betah di sana. Satu per satu nereka minggat dengan alasan tempat penampungan itu jauh dari lokasi cari makan mereka. Pemda akhirnya menghentikan program ini.
Orde Baru kemudian tumbang juga yakni tahun 1998. Sejak itu hingga hari ini kepala negara silih berganti yakni BJ Habibie, Abdurrachman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Sejak tahun 1999 berlaku otonomi daerah di negeri kita. Rupanya kebijakan desentraliasi ini tak kunjung membuat posisi Jakarta bergeser sebagai pusat dari semua hal, terlebih ekonomi. Wajar kalau arus migran tetap menujunya hingga detik ini.
Menurut sensus penduduk tahun 2010 penduduk Jakarta 9,58 juta, Surabaya 2,94 juta, Medan 2,49 juta, dan Bandung 2,39 juta jiwa. Populasi Jabotabek sendiri di masa itu 28 juta. Perlu kita ingat bahwa warga Bogor, Tangerang, dan Bekasi banyak yang bekerja di Jakarta. Jadi, pada pagi hingga petang, manusia yang berada di ibukota saban hari jauh melampaui 9,58 juta. Sungguh Jakarta sudah menjadi mega city terbesar di Asia Tenggara!
Sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014 Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Duet ini membuat sejumlah terobosan besar di Ibukota. Di antaranya: membenahi waduk Pluit dan pasar Tanah Abang, serta mengurangi banjir dan kemacetan. Mereka juga menata kampung, pasar, dan kaki lima yang menjadi tempat pedagang, serta membuat rumah susun.
Mulai 19 November 2014 Basuki Tjahja Purnama menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi Presiden. Dia berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat. Pembenahan Jakarta yang populasinya sudah sekitar 10,2 juta jiwa berlanjut. Pasangan ini menjalankan sejumlah proyek yang tujuannya antara lain: membersihkan sungai, mengurangi kemacetan, membuat transpor umum menjadi lebih bersahabat, dan membangun rusunawa.
Dalam pembenahan kota inilah banyak kaum miskin yang tergusur dari kediamannya. Ke rumah susun sederhana sebagian mereka dialihkan. Tetapi itu ternyata belum menyelesaikan masalah.
Rumah Susun
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pernah mengatakan Pemda DKI terlambat puluhan tahun dalam membangun rumah susun. Sudah telat pun, ujar dia, masih bermasalah yakni bangunan yang didirikan pemerintah untuk kalangan tak mampu tersebut ternyata menjadi komoditi pula. Infrastruktur yang diperdagangkan itu adalah rumah susun sederhana milik (rusunami), bukan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Dalam perkembangan selanjutnya dia memerintahkan penghentian pembangunan rusunami. Pada sisi lain ia mendorong betul proyek rusunawa. Di berbagai kesempatan ia mempromosikan fasilitas ini sebagai sesuatu yang pas menjadi hunian kaum tak berpunya sebab murah. Sewanya hanya Rp. 5.000 per hari atau Rp. 150.000 per bulan. Penghuni tinggal terima beres. Kalau engsel pintunya rusak atau cat temboknya pudar, misalnya, pengelola akan membereskannya.
Kalau di rumah sendiri uang Rp. 150.000—sewa sebulan—tidak ada artinya untuk biaya perawatan bangunan semacam itu.
Pendapatan orang miskin Jakarta sebagian besar mereka pakai untuk membayar sewa rumah dan transport. Untuk menekan angka kemiskinan, Pemprov DKI pun menyediakan rumah susun dan angkutan yang serba gratis. Bantuan sosial (bansos) yang dipakai untuk itu. Di tahun 2015 bansos untuk rumah dan angkutan gratis ini Rp. 3 triliun dan di tahun 2016 menjadi Rp. 3,5 triliun.
Bagi penghuni rusunawa kini antar-jemput anak sekolah dan internet gratis. Anak-anak yang masih pelajar dikasih Kartu Jakarta Pintar (KJP) pula. Untuk penghuni dibuatkan tempat usaha dan dikasih modal Rp. 5 juta-Rp. 10 juta kalau bayarannya lancar. Lantas untuk setiap 5.000 penghuni tersedia masing-masing 1 dokter, bidan, dan perawat. Layanan ini, ucap dia, sudah seperti di Grand Indonesia.
Layanan bus pengumpan (feeder) sudah ada ke sejumlah rusunawa (termasuk Daan Mogot, Tambora, Kapuk Muara, Flamboyan (Jakarta Barat), Marunda, Budha Tzu Chi (Jakarta Utara), Cipinang Besar Selatan, Pulogebang, Pinus Elok, dan Rawa Bebek (Jakarta Timur). Angkutan ini beroperasi dari pukul 05.00 hingga pukul 22.00. Penghuni rusun tak perlu membayar, cukup hanya memperlihatkan KTP—sesuai alamatnya di rusun—kepada petugas di bus.
Selain itu Pemprov DKI juga menyiapkan cleaning service, keamanan, dan kebersihan di rusunawa. Di sana juga ada pendidikan anak usia dini (PAUD), klinik, posyandu, ruang menyusui, tempat bermain bagi anak, jogging track, dan taman.
Pemprov DKI memang tidak main-main dalam penyiapan rusunawa. Di tahun 2016 mereka ngebut menyelesaikan infrastruktur ini di 8 titik yakni di KS Tubun, Lokasi Binaan Rawa Buaya (Jakarta Barat); Rawa Bebek, Cakung Barat, Jatinegara Kaum, Jalan Bekasi Km 2, dan Pinus Elok (Jakarta Timur); serta Marunda (Jakarta Utara). Targetnya bangunan di sana yang mencakup 2.394 unit klar tahun 2016.
Fasilitas ini dimaksudkan untuk menampung mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat proyek pemerintah; yang tergusur dan yang terkena relokasi, terutama. Jumlah unit ini tentu saja tidak cukup. Sebab itu direncanakan hingga tahun 2017 bangunan serupa sudah tersedia 50.000 unit di 39 titik di provinsi ini.
Kendati sedang kejar tayang, Ahok ternyata tidak sudi berkompromi terhadap apa yang dianggapnya ketakbecusan dalam proyek tersebut. Di luar perkiraan banyak kalangan, ia memerintahkan penghentian 5 proyek rusunawa yakni yang di Cakung Barat, Jalan Bekasi KM 2, Rawa Bebek, Semper, dan Marunda. Sebabnya? Proyek itu, menurut dia, sangat bermasalah. Ia merujuk hasil temuan Tim Inspektorat Pemprov DKI Jakarta.
Tim Inspektorat tersebut menilai bangunan di 5 titik ini tidak sesuai bestek. “Masa baju atau kaos nempel di coran dan kayu masuk di tiang,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Arifin, kepada Jaring. Pagar pembatas juga ada yang bergoyang, yakni di rusun Cakung Barat.
Untuk mengaudit rusun-rusun tersebut, kata Gubernur Basuki kepada para wartawan kala itu, Pemprov DKI akan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kalau hasil audit nanti mengatakan bangunan itu laik, barulah proyeknya dilanjutkan. Saat itu ia juga menyebut bahwa dirinya secara informal telah melaporkan kasus ini ke Polri dan KPK.
Kalau hasil temuan Tim Inspektorat itu dibenarkan oleh auditor, kasus ini sungguh sebuah skandal yang mengherankan. Sebabnya, para pengembang yang menangani proyek bukanlah pemain baru di dunia perusunan. Mereka adalah PT Padimun Golden (rusunawa Cakung Barat dan Jl. Bekasi Km.2, dengan nilai kontrak Rp. 99,5 miliar), PT. Marlanco (rusun Lokasi Binaan Semper, Rp. 76,5 miliar), PT Permata Dwi Lestari (rusun Rawa Bebek, Rp. 87,55 miliar).
PT Padimun Golden merupakan perusahaan yang paling sering memenangi proyek pembangunan rusun di DKI pada periode 2012—2016. Mereka mendapat 6 paket pembangunan rusun dengan total nilai kontrak Rp. 236,07 miliar.
Pemilik PT Padimun Golden adalah kakak si empunya PT Marlanco. PT Permata Dwilestari dan PT Ganiko Adiperkasa, sahamnya dimiliki orang yang sama. Adapun PT Ganiko Adiperkasa tahun lalu mereka memenangkan paket pembangunan rumah Susun Rawa Bebek, dengan nilai kontrak Rp. 35,63 miliar.
Dengan rekam jejak seperti itu tentu mengherankan kalau sampai mereka memanipulasi bahan cor-coran dengan memasukkan kaos, kayu, dan yang lain. Biasanya, kalau developernya nakal, campuran semennyalah yang diencerkan, bukan materi yang tak patut yang dimasukkan. Apa gerangan yang terjadi?
Jaring mencoba memverifikasi dengan cara menghimpun informasi dari pihak terkait. Ternyata para pengembang tersebut cenderung menghindar tatkala kami temui. Di kantor mereka tak ada otoritas yang bisa diwawancarai. Seorang petugas pengawas di PT Ganiko Adiperkasa saja yang mau bicara dan itu pun ala kadarnya.
Ia hanya menyatakan bahwa pekerjaan mereka selalu sesuai standar operasi operasional prosedur (SOP) dan senantiasa disetujui konsultan pengawas. Setelah beberapa lama tersendat, kelima proyek itu akhirnya mendapat titik terang. Konstelasi politik yang berubah di DKI menjadi penentunya.
Basuki Tjahaja Purnama yang menyetop proyek ini sudah mundur sebagai kepala daerah karena ia terjun menjadi kontestan dalam Pilkada DKI, 15 Februari 2017. Pengganti sementaranya sebagai gubernur adalah Sumarsono. Pada 5 Desember 2016 Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan ke media massa bahwa pembangunan kelima rusun bermasalah akan dilanjutkan di awal 2017.
Sesuai hasil audit inspektorat, menurut dia, kelima proyek itu laik dilanjutkan. Sisa waktu tahun ini tak cukup sehingga pembangunan dilanjutkan awal 2017. Proses adminsitrasinya akan lekas dibereskan pada Januari-Februari.
Pemda DKI, tutur dia, akan melelang sisa proyek ini. Adapun pengembang yang sudah masuk daftar hitam, mereka tidak boleh mengikuti lelang.
Di ruang Rapat Paripurba gedung DPRD DKI Jakarta, pada Senin (19/12), Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, kembali berbicara soal rusun. Ia mengatakan APBD DKI tahun 2017 lebih banyak untuk infrastruktur. Di lingkungan infrastruktur, rusun-lah penerima dana paling besar yakni Rp. 5 triliun, atau naik Rp. 1,9 triliun dari tahun 2016. Dana ini dipakai untuk membangun 11.105 unit. Sejauh ini sudah 14.900 unit rusunawa yang dibangun di DKI. Yang sedang dan akan dibangun 16.000 unit.
Jelaslah bahwa Pemda DKI akan tetap mengejar target menghadirkan rusunawa di 39 titik pada periode 2016-2017. Bahwa proyek ini disoal pelbagai kalangan, termasuk mereka yang direlokasi ke sana, tampaknya tidak akan membuat langkah otoritas surut. Entahlah kalau nanti Ahok bisa menduduki poisisi gubernur DKI lagi.
Pemerintah provinsi DKI telah menyiapkan rusunawa yang fasilitasnya serba lumayan. Begitupun, penghuninya masih banyak yang berkeluh kesah di sana. Persoalan utama mereka yang komplein ini terkait dengan uang. Di tempat sekarang mereka mesti membayar uang sewa. Kendati tak besar itu memberatkan sebab kini untuk mencari sesuap nasi saja pun mereka kelimpungan. Saat ini total tunggakan sewa rusunawa di DKI sudah Rp. 22 miliar [Kompas, 29 Desember 2016].
Tergusur dari habitat lamanya telah membuat mereka merasa serba kagok dan teralienasi. Untuk bisa beradaptasi tentulah mereka membutuhkan waktu. Apa yang dilakukan Gubernur Basuki Tjahja Purnama ini—menempatkan kaum miskin kota di rumah susun—sesungguhnya sudah pernah dilakukan Gubernur Ali Sadikin. Seperti sudah disebut di bagian terdepan, Ali Sadikin kemudian menghentikan programnya karena kaum papa itu satu per satu kemudian hengkang dari rumah susun sebab merasa jauh dari tempatnya mencari nafkah.
Akankah hal serupa terjadi pada rusunawa? Bisa jadi, jika uang sewa tetap dibebankan ke penghuni serta lapangan penghidupan yang menjanjikan serta dekat dari tempat tinggalnya tak disiapkan otoritas DKI. Pemda DKI perlu memikirkan hal ini.
Sesungguhnya rusunawa hanyalah satu dari sekian alternatif yang bisa dipilih Pemprov DKI dalam menangani tempat tinggal kaum miskin kota di wilayahnya. Alternatifnya bisa saja perbaikan kampung dan revitalisasi kampung. Yang pertama ini sesungguhnya sudah tak asing bagi warga tanah Betawi. Sedang yang terakhir pernah berlangsung di Kali Code, Yogyakarta.
Perbaikan Kampung
Di zaman Hindia-Belanda kampung-kampung kaum pribumi tersebar di seluruh Batavia. Di sana berdiam banyak orang Tionghoa, Arab, dan Eurasia (indo) miskin. Kumuh dan selalu dibayangi persoalan air bersih dan sanitasi, penyakit menular pun acap berjangkit di sana; ujungnya adalah kematian.
Sebagai catatan, di tahun 1926 angka kematian di Hindia-Belanda tinggi, yakni 40 (per 1.000 orang) untuk pribumi dan 39 untuk Tionghoa. Kampung-kampung pribumi itu sering pula terbakar, sementara berdekatan dengan permukiman dan tempat kerja orang Eropa. Wajarlah kalau yang terakhir ini acap cemas.
Di Dewan Kota dan Dewan Rakyat (Volkskraad) kerawanan kampung pribumi itu menjadi agenda pembahasan. Muncul gagasan untuk memperbaiki kawasan kediaman kaun jelata tersebut. Tujuan utamanya adalah agar tak menjadi ancaman lagi bagi permukiman Eropa.
Pihak Kotapraja Batavia akhirnya bertindak. Mereka menjalankan program perbaikan kampung (kampoengverbetering). Intinya adalah pembangunan jalan dan lintasan setapak beraspal yang dilengkapi dengan selokan. Pada 1921-1936 perbaikan 308 hektar kampung dilakukan.
Kampung yang rapi dan bersih ada imbas negatifnya bagi penduduk setempat yang miskin. Biaya sewa dan harga tanah membubung begitu jalan-ajalan bagus membelah perkampungan. Tak sanggup lagi membayar sewa rumah atau tanah ke para pemilik—orang Tionghoa, Arab, dan segelintir pribumi—pemukim berekonomi lemah terpaksa pindah ke tempat lain yang lebih jauh jauh dari tempat kerjanya.
Bila tak mampu memenuhi standar Kotapraja, si empunya rumah harus menerima kenyataan pahit: miliknya rata dengan tanah oleh aparat pemerintah. Sesungguhnya orang Eropa yang paling diuntungkan oleh kampoengverbetering [Susan Blackburn, Jakarta Sejarah 400 Tahun—Komunitas Bambu, 2011].
Selepas tahun 1936 perbaikan kampung oleh pemerintah tak pernah ada lagi di ibukota yang sudah bernama Jakarta sejak pendudukan Jepang tahun 1942. Barulah setelah Ali Sadikin memimpin program ini diadakan lagi.
Letnan Jenderal KKO Ali Sadikin dilantik menjadi Gubernur DKI pada 28 April 1966. Saat itu penduduk di povinsi ini sudah sekitar 3,6 juta; padahal di tahun 1945 masih sekitar 600.000. Kalau saja warga ini sejahtera tak masalah. Realitasnya, tak kurang dari 60% mereka miskin dan berdiam di wilayah kumuh dengan kepadatan 400-600 orang per hektar. Anak-anak mereka yang sudah cukup umur 60% tak bersekolah.
Sebagai kepala daerah Bang Ali tak suka berpangku tangan. Ia rajin menjambangi warganya termasuk yang di kampung-kampung ‘rombeng’. Ia menyaksikan sendiri di sana betapa melaratnya mereka. Kalangan yang paling tak beruntung berdiam di gubuk-gubuk darurat berbahankan kardus. Sangat rapuh tentu ‘bangunan’ itu terlebih kalau hujan mendera. Air bersih langka. Tempat mandi—mencuci—kakus (MCK) tanpa air.
Kalaupun bukan gubuk kediaman mereka yang saling berimpit berdindingkan tambalan triplek dan seng. Bagian depannya langsung bermuka-muka dengan jamban. Membenahi kota yang laksana tak bertata, itulah agenda utama Bang Ali sebagai kepala daerah. Memperbaiki kampung ia masukkan ke daftar 6 proyek vital DKI tahun1968-1969. Program ini di urutan ke-3, setelah perbaikan jalan (ke-1) dan pembangunan gedung-gedung (ke-2).
Anggaran yang cekak merupakan kendala utama bagi para kepala daerah sebelumnya sehingga mereka seperti tak kuasa menangani Jakarta. Untuk mendapatkan dana, mantan Menteri Perhubungan Laut di kabinet Soekarno itu melakukan sejumlah manuver kreatif.
Pajak, misalnya, ia genjot terutama di dunia usaha. Sebagai kompensasinya aneka insentif juga ia berikan kepada wajib pajak. Kelak judi juga ia legalkan sehingga menjadi sumber pendapatan daerah yang lumayan (29% dari anggaran DKI di masa puncaknya, 1968).
Di tahun 1969, setelah mengurusi sarana dan prasarana kota, Bang Ali mulai menangani permukiman warga miskin. Perbaikan kampung—seperti yang pernah dilakukan penguasa Hindia-Belanda tahun 1920-an dan 1930-an, sebutannya kampoengverbetering—yang ia lakukan, bukan pengadaan rumah untuk mereka. Biaya yang jadi pertimbangannya.
Perbaikan kampung lebih murah. Rata-rata biayanya Rp. 5.000 per kepala; sementara kalau perbaikan perumahan sekitar Rp. 200.000. Sesuai ketersediaan dana, program ini direncanakan akan berlangsung dalam 3 Pelita (3×5 tahun). Prioritas kampung yang akan dibenahi adalah yang lingkungannya terburuk, terpadat, tertua, dan paling berpotensi untuk dirawat dan dikembangkan warga pasca perbaikan.
Dalam praktiknya, cakupan proyek ini luas. Bukan hanya memperbaiki kediaman warga tapi juga membenahi kalau bukan menyiapkan: jembatan, trafo listrik, saluran penghubung selokan, pipa air, hidran, kincir air, sumur bor, bak sampah, gerobak sampah, rambu lalulintas, tempat mandi-cuci-kakus (MCK), puskesmas, dan sekolah dasar.
Gubernur Ali Sadikan mengeluarkan surat keputusan pada September 1973 untuk menamai perbaikan kampung ini ‘Proyek Muhammad Husni Thamrin’. Selama Pelita I (1970-1975) kampung yang diperbaiki 87, letaknya di pusat kota dengan kepadatan rata-rata 500 orang per hektar. Sebagian besar dibangun sebelum tahun 1956, di kawasan 2.400 hektar tersebut berdiam sekitar 1,2 juta penduduk.
Bank Dunia sangat terkesan sehingga membantu Proyek MH Thamrin. Untuk membiayai separuh tahapan ke-2 mereka memberikan kredit 15 tahun dengan bunga 8,5% per tahun. Masa tenggang untuk tak membayar cicilan pokok dan bunga (grace period) 5 tahun. Berkat bantuan ini program klar tak sampai 3 Pelita. Di penghujung Pelita ke-2 pekerjaan sudah beres. Hingga tahun 1975/1976 kampung yang telah diperbaiki 166 di kawasan 4.694 hektar yang berpenduduk 1.965.000 jiwa. Total biayanya hampir Rp. 22,5 milyar atau Rp. 11.000 per kepala [Gita Jaya, Pemda DKI, 1977 dan Ramadhan KH, Bang Ali—Demi Jakarta 1966-1977—Pustaka Sinar Harapan, 1993].
Hasil perbaikan kampung nyata. Kesehatan warga membaik. Anak yang bersekolah membanyak. Selain itu perekonomian setempat juga mengeliat sebab rumah banyak yang berfungsi ganda: tempat kos atau warung. PBB pun mempromosikan proyek ini sebagai model pembenahan kawasan kumuh untuk seluruh dunia.
Kampung kumuh di tengah kota tak harus dienyahkan atas nama estetika, higienitas, dan yang lain. Dipertahankan asal diperbaiki juga bisa seperti yang dilakukan Tatapraja Batavia atau Gubernur Ali Sadikin. Pun dapat direvitalisasi. Apa yang dilakukan Romo Mangunwidjaja di Kali Code, Yogyakarta, merupakan salah satu contoh terbaiknya.
Di tahun 1980 Romo Mangun—rohaniawan Katolik yang juga arsitek, sastrawan, dan pegiat kemanusiaan—berhenti menjadi pengajar di Jurusan Arsitektur UGM. Setelah 12 tahun menjadi dosen ia mengundurkan diri dengan alasan: tidak ada perkara gawat di dunia arsitektur; sementara di lapangan lain banyak termasuk di ranah kaum miskin kota.
Selain berhenti menjadi dosen dia juga pindah kediaman. Dari paroki Yogya ia berpaling ke kawasan hitam bernama Kali Code. Bantaran sungai yang membelah kota ini berada di bawah jembatan Gondolayu. Dari Tugu, ikon yang persis berada di depan kanan stasiun kereta api, sebenarnya tempat ini dekat saja. Begitupun warga yang berseliweran di kitaran Jl. Malioboro dan Jl. Sultan Agung, jarang menjejakkan kaki di sana.
Bagi mereka permukiman kumuh tersebut menyeramkan. Penghuninya memang kaum miskin kota dan kelompok kriminal: pemulung, pengemis, pengamen, pengasong, pencopet, garong, dan preman (gali). Seperti lazimnya tempat tinggal kaum sejenis di belahan bumi mana pun, serba darurat keadaannya. Materialnya triplek bekas, kardus, dan plastik untuk menghadang air dari langit.
Berkoordinasi dengan warga setempat, di tahun 1983 Romo Mangun mulai mendirikan bangunan di sana. Sebuah rumah tinggal berukuran besar yang bersekat banyak dan sebuah balai pertemuan yang ia hadirkan. Bahannya apa yang tersedia di sana: bambu dan kayu. Beratap seng, dindingnya adalah gedeg [bambu yang dianyam]. Agar bangunan lebih kokoh, ia juga mengggunakan lempung [tanah liat], batu bata, dan bata beton.
Seiring waktu, bangunan bersahaja berbentuk huruf A bertambah di sana. Berbanjar mengikuti kontur tanah, susunannya. Romo Mangun melibatkan para mahasiswa seni dalam proyek revitalisasi ini. Bersama warga, orang-orang kampus tersebut melumuri dinding bangunan dengan puspa warga. Agar lebih indah, lukisan dinding-tembok (mural) mereka tambahkan. Permukiman Kali Code pun menjadi apik dan asri. Edukasi juga berlangsung saban hari. Sejumlah komunitas yang dirangkul novelis penulis trilogi Roro Mendut, Genduk Duku, dan Lusi Lindri itu bergiat di sana sebagai pengajar. Fasilitas untuk itu disiapkan.
Rumah singgah, kurang-lebih begitulah kedudukan kediaman warna-warni di Kali Code. Penghuni menyepakati bahwa bilik-bilik ini dipakai oleh mereka yang sangat membutuhkannya saja. Kalau sudah berkeluarga mereka akan angkat kaki dari sana. Kalau sudah punya rezeki, tanpa perlu menunggu sampai menikah pun, mereka akan meninggalkannya. Jadi, pemiliknya bukan perseorangan melainkan komunitas.
Seperti disulap, Kawasan Kali Code yang tadinya kumuh dan menyeramkan berubah menjadi bersih-asri dan bersahabat sehingga warga Yogya balik membanggakannya. Ternyata, begitupun, di tahun 1985 Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memutuskan untuk mengenyahkan permukiman tersebut. Alasannya, bantaran sungai akan dijadikan kawasan hijau.
Tentu saja warga setempat dan Romo Mangun tak setuju. Arsitek lulusan Sekolah Teknik Tinggi Rhein, Westfalen, Aachen, Jerman (1966) berjuang keras menggagalkan pembongkaran. Klimaksnya adalah waktu ia mengumumkan akan mogok makan. Dukungan dari kalangan luas pun mengalir ke dia. Pemda DIY akhirnya urung memporak-porandakan bangunan unik di Kali Code.
Sampai hari ini hasil revitalisasi Romo Mangun masih utuh di sana, tak kalah menariknya dari rusunawa yang sudah meramaikan Yogya. Usia memang semakin menggerogotinya. Romo Mangun sendiri telah berpulang pada Februari 1999. Di tahun 1992 pastur penulis kitab Pengantar Fisika Bangunan (1980) dan Wastu Citra (1988) itu beroleh penghargaan prestisius di bidang arsitektur, Aga Khan, berkat kreasinya di Kali Code.
Seperti yang di Kali Code, di bantaran Kali Brantas, Malang, pun kini terdapat kawasan kumuh yang telah berubah menjadi kampung warna-warni. Jodipan, namanya, permukiman kaum miskin kota itu sekarang menjadi daerah tujuan wisata yang sedang naik daun di kota apel.
Penyulapan wajah Jodipan digagas 8 mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang sedang menjalankan praktik lapangan. Untuk mewujudkan idenya, mereka lantas menggandeng pembuat cat, Indana Paint. Cat yang disumbangkan perusahaan ini kemudian digunakan untuk mempuspawarnai seluruh bangunan bersahaja di bantaran kali, pada Juni 2016.
Tidak seperti Romo Mangun di Kali Code yang menata ulang seluruh kawasan berikut sistem sanitasinya, mahasiswa UMM dan warga mengecat Jodipan menjadi serba warna-warni saja. Begitupun, kehadiran kawasan warna-warni laksana yang di Rio de Janeiro, Brazil, telah menarik perhatian banyak kalangan termasuk pelancong. Warga kemudian memberlakukan tarif masuk Rp. 2.000 untuk setiap tamu yang datang ke sana. Uang itu kemudian mereka gunakan untuk membenahi sistem sanitasi secara perlahan.
Jelaslah bahwa untuk menghadapi rawa masalah terkait permukiman kaum miskin kota, Jakarta bisa mengambil pelbagai langkah. Membangun rumah susun sederhana sewa bukanlah satu-satunya pilhan yang tersedia.