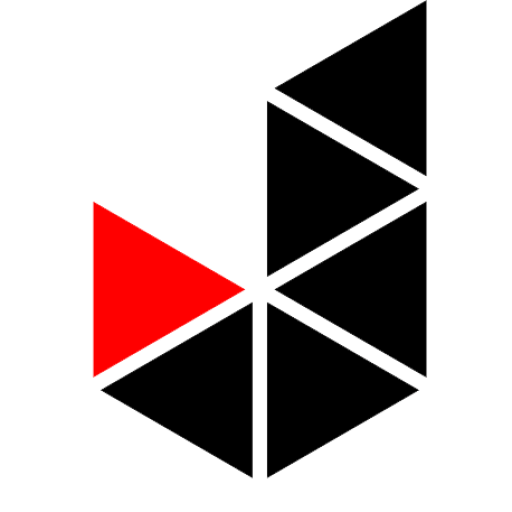Seperti itulah gambaran para pedagang bambu di tahun 1980-an yang ada dalam ingatan Mukhlis bin Sabili. Dari belakang rumahnya di Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang persis bertepikan Sungai Ciliwung, ia acap menyaksikan para penjual itu wara-wiri dengan rakitnya. Sesampainya di tujuan, rakit itu dibongkar dan bambunya dijual ke pengepul.
Salah satu pedagang bambu itu adalah Ali, kakek dari istri Mukhlis. Ali menjadi penghuni bantaran Sungai Ciliwung di Bukit Duri sejak berpuluh tahun lalu.
“Dari pada pulang ke Citayam lebih baik mereka buat rumah di sini,” kata Mukhlis kepada Jaring yang menjumpainya di Bukit Duri. Ali kemudian beranak-pinak. Keturunanya itulah yang kini menjadi bagian dari warga Bukit Duri di bantaran Sungai Ciliwung.
Sungai Ciliwung yang membentang 120 kilometer dari Gunung Gede hingga Pelabuhan Sunda Kelapa, telah berabad-abad menjadi urat nadi transportasi perdagangan. Tepiannya menjadi permukiman bagi banyak orang.
“Sejak zaman kerajaan, Jakarta sudah menjadi daya tarik manusia untuk tinggal dan bermukim karena terletak di tepi atau muara Sungai Ciliwung,” tulis wartawan senior Alwi Shihab dalam buku Betawi: Queen of the East.
Komunitas Ciliwung Merdeka, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk warga Kelurahan Bukit Duri dan Kampung Pulo, meyakini leluhur mereka sudah menempati bantaran sungai itu sejak 1930-an. Meski sudah berada di sana sebelum Republik Indonesia berdiri, Pemerintah DKI Jakarta ternyata menganggap mereka ‘penghuni ilegal’.
Pasalnya mereka tak mempunyai sertifikat tanah; yang mereka miliki hanya bukti kepemilikan seperti girik, akta jual-beli tanah dan rumah, hingga bukti pembayaran pajak masa Belanda [verponding].
Alldo Felix Januardy, pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mengatakan, warga seperti Mukhlis yang menguasai tanah selama 20 tahun dengan ‘itikad baik’ dan lahan tersebut tidak dalam sengketa sebetulnya dimungkinkan mendapat sertifikat seperti diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
“Tapi ketika warga mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat, kendala birokrasinya banyak sekali. Misalnya, pungutan liar atau korupsi,” ucap dia di kantor LBH Jakarta.
Keluarga Mukhlis yang mencoba mengajukan permohonan sertifikasi tanah pada 1990-an mengalami hambatan seperti itu. Mereka dimintai uang jutaan rupiah oleh orang kelurahan. Sejak itu mereka kapok mengurus sertifikat tanahnya.
Direktur Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi tahun lalu mendampingi warga Kampung Pulo mendaftarkan tanah mereka ke Badan Pertanahan Negara (BPN). Rumah penduduk digusur juga akhirnya yakni pada 20 Agustus 2015.
“Susah sekali kalau kita mau mengurus sertifikasi. Padahal pemerintahan Jokowi sedang menggalakkan sertifikasi gratis. Kenyataan di lapangan, itu tidak berlaku untuk warga miskin.”
Hanya segelintir warga bantaran Sungai Ciliwung, menurut Sandyawan, yang bisa mendapat sertifikat. Seorang warga, misalnya, berhasil mendapatkan sertifikat setelah 8 tahun mengurusnya dan menghabiskan Rp. 30 juta.
Pengalaman buruk juga pernah dialami warga Kampung Tongkol yang mendiami bantaran muara Sungai Ciliwung, Pademangan, Jakarta Utara. Mereka pernah ditipu petugas kelurahan yang mengiming-imingi pembuatan sertifikat tanah secara kolektif dengan membayar sejumlah uang. Pengalaman buruk itu membuat mereka patah arang kendati sangat menginginkan sertifikat untuk tanah yang ditempatinya.
Tanpa sertifikat kepemilikan tanah dan rumah, warga miskin kota semakin rentan digusur. Warga Bukit Duri dan Kampung Pulo yang digusur karena dianggap menyalahi tata ruang kota, umpamanya, tidak mendapat ganti rugi apa pun untuk tanah dan rumah yang telah mereka tinggali puluhan tahun. Pemerintah DKI Jakarta hanya menawarkan relokasi ke rumah susun untuk mereka yang tergusur. Bagi sejumlah kalangan ini bukan solusi yang menyelesaikan persoalan warga miskin kota.
Aturan Lemah
Sejak resmi menyandang predikat sebagai ibu kota negara, tahun 1964, Jakarta telah memiliki 4 produk rencana tata ruang yang menjadi rambu-rambu pembangunan kota yaitu Rencana Induk Djakarta 1965-1985, Rencana Umum Tata Ruang 1985-2005, Rencana Tata Ruang Wilayah 2000-2010, dan yang paling anyar adalah Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030.
Salah satu poin penting dalam setiap produk rencana tata ruang itu terkait dengan ruang terbuka hijau. Pada 1965, ruang terbuka hijau di Jakarta masih sekitar 37,2% atau lebih tinggi dari standar Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) yaitu 30% dari total seluruh wilayah kota.
Jumlah ruang terbuka hijau turun drastis menjadi 25,85% pada 1985 dan terus menghilang tinggal 9% pada 2000. Ruang terbuka hijau sempat naik tipis menjadi 9,8% pada 2010 dan tahun lalu 9,9%. Angka yang disyaratkan Undang-undang Penataan Ruang adalah 30%.
Pelanggaran tata ruang yang dibiarkan terjadi dari tahun ke tahun menjadi penyebab utama hilangnya ruang terbuka hijau di Jakarta.
“Penegakan aturan tata ruang sangat lemah. Tidak ada sanksi terhadap pelanggaran yang diberikan pemerintah Jakarta. Perusahaan pengembang pun mengubah daerah hijau menjadi perumahan, kondominium, mal, hotel, gedung komersil, dan perkantoran,” tutur Koordinator Program Kajian Perkotaan dan Perencanaan dari Universitas Savannah State, Amerika Serikat, Deden Rukmana, dalam penelitiannya yang dirilis tahun lalu.
Dalam laporan itu disebut setidaknya ada 3.925 hektar area hijau di 5 daerah di Jakarta telah disalahgunakan sepanjang 1985 hingga 2005. Dengan kata lain, dalam kurun 20 tahun saja, Jakarta Pusat saja kehilangan area hijau 80% akibat alih fungsi. Pelanggaran tata ruang paling parah terjadi di Sunter. Di sana 1.548 hektar yang semestinya merupakan daerah tangkapan air berubah fungsi menjadi areal perumahan elit Sunter Agung dan pabrik-pabrik otomotif sejak 1990-an.
Alih-alih melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran itu, Pemerintah DKI Jakarta justru menerima konversi lima daerah itu dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2000-2010. Deden menilai buruknya penegakan aturan tata ruang akibat tidak adanya peraturan zonasi dan pengawasan.
Untuk mengembalikan ruang terbuka hijau dan memenuhi kewajiban 30% seperti dalam UU Penataan Ruang, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mulai tahun lalu menggencarkan penertiban bangunan yang berdiri di atas lahan hijau. “Semua Ruang Terbuka Hijau di Jakarta kita tertibkan terus. Nggak ada toleransi. Siapa yang menduduki RTH, kami habisi,” kata dia kepada media massa awal tahun ini.
Upaya penegakan hukum yang dilakukan Gubernur Ahok dirasa pincang sebelah lantaran hanya tertuju pada permukiman warga miskin kota; adapun proyek yang dikerjakan para pengembang besar tidal disentuhnya. “Sayang sekali, yang jadi korban selalu rakyat miskin khususnya miskin kota, nelayan, dan buruh. Sementara kelas menengah atas justru difasilitasi secara berlebihan,” kata Direktur Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi.
Perbaikan Kampung
Penegakan hukum tata ruang yang cenderung hanya menyasar permukiman warga miskin kota tidaklah menyelesaikan permasalahan. Lembaga kajian perkotaan Rujak Center for Urban Studies (RCUS) menilai pemerintah perlu membuat sebuah proses yang bertahap untuk menciptakan tata ruang yang ideal; salah satunya dengan melibatkan warga miskin kota.
“Kota yang berdialog lebih baik dari kota yang menegakkan hukum,” ucap Peneliti RCUS Andesha Hermintomo.
Upaya itu mendapat momentum ketika Pemerintah DKI Jakarta mengumumkan untuk meninjau kembali Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, Mei lalu. Musababnya adalah dua proyek nasional di Jakarta yaitu Light Rail Train (LRT) dan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung belum diakomodir dalam aturan tata ruang Jakarta.
Urban Poor Consortium (UPC), lembaga non-pemerintah yang mewadahi 30 komunitas warga perkampungan di Jakarta, mencoba memanfaatkan momen revisi aturan itu supaya kampung yang ada di Jakarta bisa diakui dalam tata ruang Jakarta. Pasalnya, menurut UPC, sejumlah perkampungan warga yang sudah berpuluh tahun ada secara tiba-tiba dan tanpa sosialisasi dijadikan area terbuka hijau, komersial, dan peruntukan lainnya dalam Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Koordinator Advokasi UPC Gugun Gunawan mengatakan timnya bersama warga dari 30 kampung dan dibantu beberapa arsitek dari Universitas Indonesia tengah menyusun masterplan tata letak dan tata guna di kampung serta rencana perbaikan kampung seperti yang dilakukan di Kampung Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara.
Untuk sementara, ada 10 sepuluh kampung yang akan diusulkan lewat jalur Pemerintah DKI Jakarta maupun DPRD DKI Jakarta. Gugun berharap kampung-kampung itu bisa diakui dalam RDTR dengan kode zona kuning (hunian) dan sub zonasi R1 (rumah kampung).
Kalau masterplan itu lolos nanti warga bantaran Sungai Ciliwung dan perkampungan lainnya barangkali tidak perlu khawatir lagi. Yang mereka risaukan selama ini? Pejabat pemerintah yang sebelumnya tak pernah menemui, bersama polisi, tentara, dan Satpol PP, tiba-tiba menyambangi rumah kecil mereka. Tujuannya bukan untuk bertamu tapi menggusur dengan alat-alat berat. Karena mereka yang kuat, merekalah yang dapat!