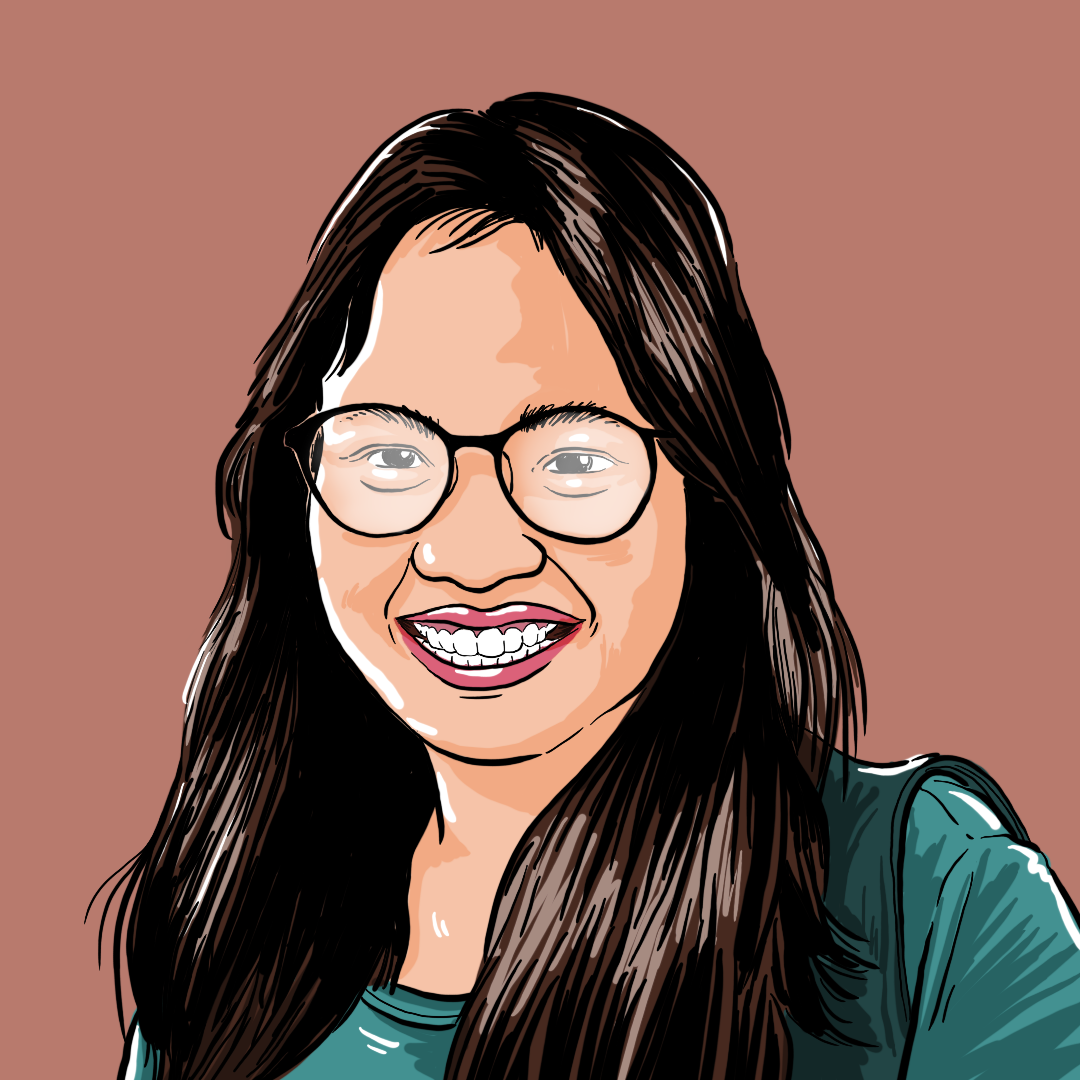Sudah lebih tiga hari, luka bakar yang menghanguskan sebagian kulit tubuh Ruy (bukan nama sebenarnya) tak diobati. Alih-alih mendapat pertolongan medis, bocah enam tahun itu malah disembunyikan keluarganya di Distrik Ermera yang berjarak 30 kilometer dari Dili, Ibukota Timor Leste. Korban kekerasan domestik ini baru dilarikan ke Fatin Hakmatek, sebuah rumah aman di Dili National Hospital setelah salah seorang tetangganya membuat laporan ke kantor polisi setempat. Selain merintih kesakitan dan trauma, dokter mendiagnosa ia menderita malnutrisi dan pertumbuhan terlambat.
“Dia kelihatan seperti anak tiga tahun. Ada bekas luka di lengan dan kakinya,” demikian penggalan kisah yang tertera dalam laporan A day in Fatin Hakmatek, Multi Tasking and Still Breathing pada Agustus 2010.
Lembaga internasional yang mengadvokasi korban kekerasan dalam rumah tangga, Fatin Hakmatek menyebut bahwa kekerasan domestik yang dialami Ruy bukan sekedar kekerasan fisik, tetapi relasi kuasa patriarki terhadap anggota keluarga. Ruy bukan satu-satunya anak yang menjadi korban kekerasan di Timor Leste. Dari pelbagai kekerasan domestik yang ditangani Fatin Hakmatek, anak dan perempuan paling banyak menjadi korban.
Laporan berjudul ‘Unseen, Unsafe’ yang dirilis Safe the Children, World Vision, Plan International dan Child Fund pada 2017 mencatat 612,539 kasus kekerasan anak di Timor Leste. Angka ini setara 87,4 persen dari 700,845 anak di negara itu. Sementara, UN Women mencatat sebanyak 59 persen perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual pada 2015.
Oleh sebab itu, kelompok pemberdayaan perempuan yang terdiri dari 38 organisasi perempuan di Timor Leste menelusuri akar masalah kekerasan sejak negara ini lepas dari Indonesia. Upaya pertama dilakukan pada 2001 ketika kongres perempuan pertama yang digelar di Dili menyepakati pembentukan Kementerian Perempuan. Setelah itu, mereka menginginkan porsi yang lebih besar dari keterwakilan perempuan di parlemen hingga 30 persen, serta pengesahaan Undang-Undang Anti Kekerasan Domestik.
Kerja menahun tersebut akhirnya membuahkan hasil pada 2010. Parlemen Nasional Timor Leste mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang Kekerasan Domestik. Selain memberi kepastian hukum kepada korban kekerasan, peraturan ini juga memberi batas waktu agar penanganan perkara tidak berlarut-larut. Kepolisian hanya punya waktu tidak lebih lima hari untuk membuat berkas perkara.
“Kekerasan rumah tangga jadi bukan delik aduan, tetapi masuk kejahatan umum,” jelas Ketua Komisi A yang membidangi legislasi, Carmelita Moniz di Parlemen Nasional, Dili, Timor Leste kepada Jaring.id dan Radio Rakambia pada Selasa 24 September 2019.
Judicial System Monitoring Programe (JSMP), organisasi sipil yang memantau peradilan di Timor Leste mencatat peningkatan kasus kekerasan berbasis gender yang masuk persidangan hingga mencapai 65 persen. Sementara kasus kriminal lain hanya 35 persen pada 2017.
Tingginya pelaporan kasus kekerasan, menurut Carmelita, telah berhasil mengubah posisi korban di hadapan hukum. Masyarakat Timor Leste tidak lagi menganggap kasus kekerasan sebagai urusan privat. Kasus yang merugikan anak dan perempuan mulai muncul ke permukaan dan tak lagi dianggap sebagai aib yang perlu ditutup-tutupi.
“Di sini ada pemahaman umum kalau suara ‘sendok’ dan ‘garpu’ yang saling memukul tidak boleh kedengaran sampai ke tetangga,” ungkapnya.
Selain menerbitkan UU Kekerasan Domestik yang berhasil mengubah kultur masyarakat Timor, para perempuan di parlemen Timor Leste juga berhasil menggolkan UU Pemilihan Parlemen pada 2012. UU ini memberikan peluang lebih lebar bagi perempuan yang hendak duduk di kursi dewan. Sebab partai wajib mengusung satu perempuan di antara tiga kandidat. Dengan cara itu, jumlah perempuan yang duduk di parlemen meningkat hingga 39 persen dari sebelumnya yang hanya 27 persen.
Meski begitu, representasi politik perempuan di Parlemen Nasional Timor Leste yang terbilang tinggi tidak serta-merta mengubah tingkat ekonomi, pendidikan dan kesehatan perempuan di negara itu membaik. Merujuk data Global Gender Gap Index, indeks yang mengukur ketimpangan gender suatu negara, Timor Leste masih bercokol di posisi 124 dari 149 negara dengan rasio 0.638. Angka ini tidak jauh dari Indonesia yang berada di urutan ke-85 dengan rasio 0.691. Hal ini menunjukan bahwa jurang ketimpangan di Timor Leste dianggap masih lebar.
Di Asia Tenggara, Filipina paling berhasil mempersempit jurang kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, khususnya di bidang pemberdayaan politik dan pendidikan. Negeri jiran ini menempati urutan ke-8 dunia dengan skor 0.799.
Ketua Caucus Feto Politika Timor Leste, organisasi sipil yang mendorong kesetaraan gender dalam politik, Teresinha Maria Noronha Cardoso mengatakan kapasitas perempuan di parlemen masih lemah, utamanya dalam pembahasan anggaran. Padahal masih banyak kebijakan pro-perempuan yang harus diperjuangkan, antara lain RUU Perlindungan Anak, RUU Kesetaraan Gender dan RUU Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selama ini, menurut Teresinha, partai masih mengandalkan program penguatan kapasitas yang diberikan organisasi masyarakat sipil.
“Padahal kami sudah mengikutsertakan sebagian dari mereka (anggota parlemen perempuan) dalam program pertukaran parlemen ke beberapa negara. Tetapi belum menunjukkan hasil,” keluh Teresinha kepada Jaring.id di kawasan Obrigado Barack, Dili pada Senin, 24 September 2019.
Bukan Sekadar Angka
Permasalahan kapasitas terkait anggaran, menurut Teresinha, bukan hambatan tunggal yang membatasi ruang gerak perempuan di parlemen Timor Leste. Mereka kerap bekerja di bawah tekanan kepentingan politik partai jangka pendek. Hal ini menyebabkan para perempuan menjauh dari agenda politik berbasis gender.
“Situasi politik kita juga tidak jelas. Kalau mau fokus ke isu perempuan masih susah. Sebab masalah nasional masih sulit,” kata Teresinha.
Pernyataan Maria merujuk pada situasi politik yang sedang terjadi di Timor Leste. Awal 2017, Presiden Timor Leste, Francisco Guterres atau disapa Lu Olo membubarkan parlemen dengan hak veto. Penggunaan kekuasan sepihak ini mengakibatkan program nasional Timor Leste mandek. Pemilihan parlemen ulang pada 2018 lalu pun tidak jadi panasea bagi kebuntuan politik di negeri matahari terbit. Sebab sekarang giliran anggota parlemen yang menyerang balik pemerintah dengan memboikot sejumlah program nasional.
Kondisi politik perempuan Timor Leste dengan Indonesia, menurut Sekretaris Kaukus Perempuan Parlemen, Hetifah Sjaifuddin, tak jauh berbeda dengan Timor Leste. Namun, perempuan di Timor Leste cukup berdaya memperjuangkan kesetaraan gender, hal yang belum sepenuhnya dimiliki anggota DPR perempuan di Indonesia.
“Dari Komisi I sampai XI. Jangan berpikir masalah perempuan hanya di Komisi VIII. Padahal harusnya semua komisi mencermati apakah ada regulasi yang diskriminatif terhadap perempuan atau hanya menguntungkan satu gender tertentu,” kata politisi Golkar itu pada 2 September 2019 kepada Jaring.id di Jakarta Pusat.
Itu sebab, Hetifah berharap partai mau menyokong perempuan untuk mengisi struktur di parlemen. Tidak hanya sebagai anggota biasa, namun pada posisi yang dapat memengaruhi kebijakan, seperti Ketua Komisi, Ketua Badan Anggaran, hingga Ketua Badan Legislasi. Hetifah satu-satunya perempuan yang menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Periode 2014-2019. Sementara di DPR Periode 2019-2024, Politikus PDI Perjuangan Puan Maharani menjadi perempuan pertama yang didapuk sebagai Ketua DPR.
“Saya kira kita harus kerja lebih keras karena dari jumlah perempuan baru dua puluh persen di parlemen. Perlu lebih banyak perempuan supaya lebih nyaring,” katanya.
Direktur Cakra Wikara Indonesia (CWI), lembaga perkumpulan peneliti sosial dan politik berbasis gender, Anna Margret sependapat. Selain budaya partiarki yang membuat kaum perempuan memiliki posisi asal yang berbeda, menurutnya, dinamika politik di internal partai juga menjadi faktor penghambat pemberdayaan perempuan. Sebab itu, Anna setuju bila porsi besar perempuan di parlemen perlu didorong hingga mencapai angka ideal. Caranya bisa melalui afirmasi politik.
Hal ini penting agar perempuan tidak kalah suara ketika berhadapan dengan isu strategis. Ia tidak ingin produk legislasi yang digodok DPR bias gender, sehingga dapat merugikan perempuan.
“Pengalaman perempuan penting dalam hal penyusunan anggaran hingga perancangan program yang ramah perempuan,” kata Anna ditemui di kantor CWI, Depok, pada Selasa, 4 September 2019.
Namun, ia mengingatkan jumlah perempuan di parlemen bukan satu-satunya ukuran yang dapat mendorong lahirnya kebijakan properempuan. Bagaimanapun, menurutnya, kapasitas terkait identitas politik berbasis gender terbilang penting bagi perempuan di DPR.
“Dalam studi feminis tidak pernah ada yang mengatakan banyaknya perempuan akan lebih baik. Unsur penentu itu adalah identitas politik yang dibawa perempuan,” katanya.
Artikel ini merupakan hasil kolaborasi antara Jaring.id dengan radio Rakambia, Timor Leste