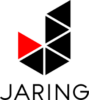Jam sudah menunjukkan pukul setengah 11 malam saat sejumlah warga berkumpul di salah satu rumah di Gen Saok atau kini disebut Dusun Sabar Bubu, Desa Kuala Hilir, Simpang Hulu, Ketapang, Kalimantan Barat. Di antara mereka adalah Tarsius Fendi Susupi yang merupakan Kepala Adat Desa Kualan Hilir. Ia terlihat duduk bersila bersama para pemangku adat lainnya di ruang tengah berkelir merah jambu. Semakin malam makin banyak warga yang datang. Sebagian dari mereka merokok, sehingga ruangan seluas 5 X 3 pun mulek dengan kabut asap rokok.
Saat laki-laki merapat, para ibu sibuk di dapur. Mereka meracik kopi dengan gula yang banyak dan siap dihidangkan selagi panas. Sebuah teko penuh kopi dan cangkir melanin dihidangkannya di pinggir ruangan.
Malam itu warga Dusun Sabar Bubu membuat rencana untuk kembali mengunjungi PT Mayawana Persada—perusahaan yang dianggap sebagai biang keladi dari kerusakan lingkungan dan penghidupan mereka sebagai masyarakat yang tinggal di batas hutan. Ini karena lahan konsesi seluas 136.710 hektare yang diberikan ke Mayawana tidak hanya mencakup permukiman warga, melainkan juga habitat orangutan, lahan pertanian, dan hutan adat. Sekitar 88.100 dan 83.060 hektare lahan merupakan ekosistem gambut berdasarkan analis pemetaan.
Dusun yang ditinggali Fendi dan warga lain yang hadir dalam rapat malam itu adalah salah satu wilayah yang terdampak karena masuk dalam konsesi perusahaan lewat izin usaha pemanfaatan hutan (PBPH) tanaman industri berdasarkan SK.732/Menhut-II/2010. Izin tersebut mencakup Kabupaten Ketapang hingga Kabupaten Kayong Utara.
Lembaga konservasi Yayasan Palung menyebutkan bahwa hutan alam di kawasan PT Mayawana Persada termasuk dalam bentang alam atau lanskap Mendawak yang kaya akan biodiversitas yang terdiri dari hutan alam dan hutan gambut. Cakupan lanskap Mendawak meliputi empat kabupaten yakni, Kayong Utara, Ketapang, Sanggau, dan Kubu Raya dengan perkiraan luas mencapai 500.000 hektare.
“Besok kita berangkatnya pagi-pagi sekali ke kantor perusahaan Mayawana Persada. Jangan lupa pamit sama istri. Wanti-wanti supaya tidak perang dunia lagi,” tegas Fendi disambut kata setuju warga lain, Senin, 25 Maret 2024.
Perang dunia yang dimaksud Fendi merujuk pada peristiwa 29 Juni 2023 lalu. Saat itu para warga beraksi dengan memboikot 12 unit alat berat beserta satu mobil truk pengangkut pasir di Sabar Bubu—sebuah bukit yang menjadi tempat sakral karena kerap digunakan sebagai lokasi menggelar ritual adat bagi para leluhur warga Gen Saok. Aksi tersebut diikuti ratusan warga, mulai dari perempuan, anak, dan laki-laki. Para warga berang karena perusahaan Mayawana Persada merambah sampai tempat suci mereka hingga gundul tak bersisa.
Dalam aksi perlawanan tahun lalu itu para petinggi adat mengenakan pakaian khas Dayak Simpakng—suku asli warga setempat, guna menggelar Mandoh. Kali itu yang dipilih berwarna merah, sebagai tanda perlawanan. Mulai dari ikat kepala, baju, hingga celana semuanya berwarna merah darah. Aksesoris gigi, tanduk binatang hingga buah-buahan hutan dikenakan sebagai kalung, gelang, dan pengikat kepala.
Beras kuning ditaburkan, mantra-mantra tak berhenti dilantunkan oleh para piawang atau penjaga hutan adat, sehingga suasana sesak mencekam. Satu persatu para pengendara alat berat dan security perusahaan berseragam polisi dengan lambang Brimob pasrah menyerahkan kendali kendaraan, bahkan beberapa lainnya lari terbirit-birit tanpa perlawanan. Sementara alat berat yang dijejerkan serupa tentara sedang apel itu bertahan hingga 11 hari sampai 9 Juli 2023.
Pada hari ke-12, surat panggilan pemeriksaan dari kepolisian sampai ke kepala adat. Isinya pemanggilan terhadap beberapa nama warga yang diduga merusak bibit akasia milik Mayawana Persada, termasuk kepala adat. Mereka dikenakan pidana, dan sempat mendekam di tahanan Polsek Ketapang. Antara lain Kepala Desa Sekucing Kualan—sebuah desa yang letaknya berbatasan langsung dengan Desa kualan Hilir dipenjara 1,5 tahun akibat membakar lahan garapannya sendiri. Pemenjaraan dilakukan tanpa ia diberitahu bahwa lahan yang selama ini digarap bagian dari konsesi PT Mayawana Persada.
“Saya juga datang ke Polsek waktu itu, tapi tak ikut ditahan,” kata Fendi Susupi kepada Jaring.id pada 19 Maret 2024 malam.
Sedangkan pada 2022, anak Patih Adat Desa Kualan Hilir, Daniel Ariyanto juga ditahan di Polres Ketapang. Daniel dituduh mencabut dan merusak tanaman akasia yang baru saja ditanam.
Dari cerita setahun lalu itu obrolan berlanjut hingga tengah malam sekitar pukul 2 kurang. Satu persatu warga beranjak meninggalkan ruangan. Para ibu yang awalnya membantu di dapur memilih pulang sejak tadi. Aini, istri kepala dusun, Andreas Ratius tanpa disuruh memberesi ruangan dan membawa cangkir bekas kopi untuk dicuci. Sekalipun berat mengurus rumah, Ai mengaku tak keberatan menjalani itu semua karena sejak perusahaan datang ke desanya, suaminya mulai sibuk melawan dan memperjuangkan hak atas tanah mereka.
“Semenjak ada Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Mayawana Persada datang, bapaknya sering dikunjungi oleh intel polisi atau ikut bersama warga lainnya datang ke perusahaan melawan. Pernah sekali hampir seminggu tak pulang,” jelasnya.
Sembari mencuci cangkir bekas kopi di bak cuci, Aini mengaku khawatir tiap kali suaminya melakukan aksi protes. Sebab yang dilawan bukan hanya pihak perusahaan, tetapi juga aparat kepolisian. “Dulu sebelum mereka datang, kami semua merasa tenang,” keluhnya.
Sabar Bubu adalah dusun yang terletak di Desa Kualan Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Jaraknya sekitar 371 km dari Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Selain Sabar Bubu, terdapat empat dusun lainnya di desa tersebut, yakni Lelayang Batu, Setontong, dan Meraban.
Mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai petani dan menjadi bagian dari komunitas adat Dayak Kualan. Mereka menggantungkan hidup dari hasil ladang dan berbagai tanaman di kebun, semisal padi, karet, cabai, bawang, dan berbagai jenis buah-buahan.
Dusun tempat tinggal Fendi dan Aini sendiri berada sekitar 4-5 jam perjalanan dari Balai Berkuak, Kecamatan Simpang Hulu. Saat tim kolaborasi yang terdiri dari Betahita.id, Ekuatorial.com, Mongabay.id, CNN TV, Pontianak Post mengunjungi dusun hampir tak terlihat jalan yang mulus. Selain mengandalkan hasil hutan dan pertanian, warga desa pun beternak.
Aini sendiri memiliki 16 ekor dori atau babi hitam peliharaan gemuk dan sehat di dalam kandang yang terletak di belakang rumah. Keluarga Aini pun memodifikasi rumahnya agar bisa menampung sarang burung walet. “Ada seribuan ekor di sana,” jelasnya sambil menatap dan memanyunkan mulutnya ke arah langit-langit atap rumah.
Ia bersama suaminya bekerja keras untuk mendapatkan semua itu. Hampir saban hari Aini ikut ke dalam hutan untuk menanam hingga memanen hasil pertanian. Hutan yang awalnya tanpa kepemilikan, digarap, dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sana mereka menanam jengkol, karet dan berbagai macam buah-buahan. “Di sini, siapa pun yang mau mengelola hutan boleh memanfaatkannya terus-terusan. Asal tetap menyisakan hutan supaya leluhur tak marah,” katanya.
Namun sejak Mayawana Persada merangsek ke desanya, hidup Fendi dan Aia tak tenang. Tanah seluas 40 hektare yang telah digarap selama 14 tahun, lenyap tanpa sisa. “Usaha saya hanya sekitar 5 hektare yang belum produktif. Tapi, yang lain, seperti jengkol sudah panen, cempedak sudah panen. Bahkan, karet saya yang sudah bisa disadap kurang lebih 15 hektare,” ujarnya.
Tanpa tanah, Fendi kini menyadap karet milik warga lain. Sesekali ia pun menjadi buruh kuli. Namun itu semua tak cukup untuk membiayai kehidupan. Itu sebab keluarga Fendi tak punya pilihan lain selain melawan sembari berharap-harap tak ditahan. “Walaupun berat, kadang saya berpikir biar lah tanah itu diserahkan saja, asal suami saya tak dipenjara,” Aini meneteskan air matanya dan menyeka dengan tangan bekas cucian piring yang masih basah.
****
Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Selasa, 26 Maret 2024, Aini sudah sibuk berada di dapur. Suara denting gelas yang beradu dengan sendok terdengar hingga ke ruang tamu. Istri dari Kepala Dusun Sabar Bubu ini buru-buru menyiapkan kopi dan sarapan karena harus segera memandikan sebelum mengenakan seragam sekolah dasar ke badan Ook, anaknya.

![]() Sementara di luar rumah beberapa beberapa mulai memadati halaman rumah terlibat pembicaraan serius. Mereka berpakaian serba hitam, lengkap dengan mandau, ornamen-ornamen gigi, dan tanduk binatang dikenakan sebagai kalung, serta ikat kepala berwarna merah.
Sementara di luar rumah beberapa beberapa mulai memadati halaman rumah terlibat pembicaraan serius. Mereka berpakaian serba hitam, lengkap dengan mandau, ornamen-ornamen gigi, dan tanduk binatang dikenakan sebagai kalung, serta ikat kepala berwarna merah.
Ook yang sudah siap berangkat sekolah pagi itu tiba-tiba mogok mengurungkan niatnya untuk pergi ke sekolah. Anak kelas 3 sekolah dasar itu meronta-ronta ingin ikut ayahnya pergi ke perusahaan Mayawana Persada. Mendengar Ook ngamuk, Aini tak punya cara lain selain membujuk, namun anaknya itu tetap merengek tak mau sekolah. “Harus ikut. Harus ikut. Pokoknya ikut,” bicaranya dengan tersedu-sedu.
“Dia tak mau ditinggalkan ayahnya lagi. Dulu pernah. Apalagi sejak banyaknya intel polisi yang datang ke rumah ingin membawa Bapaknya Ook pergi,” ungkap Ai sembari menenangkan anaknya. Ayahnya tampak tak tega, namun rombongan tetap harus pergi.
Berselang sejam, Ook berangkat ke sekolah diantar ojek yang sudah sedari tadi menunggu.
Setelah satu per satu keluarganya pergi giliran Aini yang ke luar rumah menuju ladang. Hari itu ia hendak memanen padi pada siang yang terik sekitar 34 derajat celcius. Guna mengurangi paparan sinar matahari, Ai mengenakan caping dan pakaian berlengan panjang. Tak lupa ia olesi wajahnya dengan bedak beras. Sedangkan di tangannya terdapat sebilah pisau kecil berbentuk persegi panjang dengan ukuran tak lebih dari 10 centimeter yang diberi tangkai kayu atau bambu kecil.
Saat itu Aini tak sendiri. Sedikitnya ada 40 warga lain mengenakan pakaian serupa yang berkumpul di sebuah pondok tani beratap terpal hijau. Jumlah antara laki-laki dan perempuan hampir sama, namun didominasi para orang tua.
Mereka datang untuk bergotong royong memanen padi atau bahasa setempatnya disebut pangari. Sebuah budaya serupa arisan, di mana setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk dibantu oleh anggota kelompoknya. Tidak hanya memanen, bahkan untuk menanam dan membuka lahan.
Padi ditanam di media tanah atau yang disebut padi ladang. Tidak hanya padi, tumbuhan lainnya juga ikut ditanam. Tomat, cabai, mentimun, jeruk nipis, hingga pohon monokultur seperti karet dan sawit. Sembari menunggu panen padi setahun sekali, hasil tanaman lainnya bisa dipanen terlebih dahulu. “Kalau padi tidak boleh dijual, tapi yang lain jual, kan untung,” jelas pemilik ladang bernama Caya yang kini sudah berusia 68 tahun di tengah udara siang yang benar-benar panas.
Satu per satu, warga yang terpencar di ladang menyelinap masuk ke pondok. Beberapa ibu-ibu juga sudah sibuk menanak nasi dan menyiapkan makan siang. “Sejak hutan di rambah, Tuhan murka. Angin pun tak mau datang,” celetuk salah seorang warga bersungut-sungut. Caya mengangguk sambil membagi-bagikan piring plastik warna-warni.
Semua orang makan, cepak mulut orang-orang mengunyah bersatu dengan lagu dangdut dari speaker. Sambil makan Caya tampak tak senang. Raut mukanya datar sebelum tiba-tiba air matanya jatuh. Ini karena hasil panennya har itu tidak memuaskan. Padahal sebelum perusahaan penggundul hutan datang, gabah yang dihasilkan tiap panen biasanya bisa mencapai 4-10 ton, tergantung luasan areal yang ditanami padi. Namun kini Caya tak lagi leluasa menggunakan teknik garap gilir balik setelah adanya kasus penyerobotan tanah. Tanah yang saat ini sedang dipanen pun diketahui sudah dua kali ditanami padi. “Seharusnya ditanami lagi 5-6 tahun biar alam istirahat dulu. Capek kalau dipaksa juga,” jelasnya meringis.
Caya adalah salah satu korban penyerobotan lahan yang dilakukan Mayawana Persada melalui izin pemanfaatan hutan (PBPH) tanaman industri berdasarkan SK. 732/Menhut-II/2010. Lahan garap Caya yang diambil paksa seluas 5 hektare. “Ladang yang ditanami getah dicuri. Digusur malam-malam. Bukan dijual, tapi dicuri,” jelasnya sambil menyeka pelupuk matanya yang sudah berat.
Makin hari ia makin risau dengan seluruh ladang garapannya, termasuk yang sedang dipanen. Ia menilai ladangnya tak lagi bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. “Anak saya ada yang jadi buruh di perusahaan sawit, tapi gaji sejuta-dua juta itu tetap tak cukup,” jelasnya mengapa masih berladang.
Kekhawatiran yang sama dirasakan Fransisca (41) dan Yulita (53). Mereka mengaku kehilangan lahan sekitar 3,8 hektaree secara tiba-tiba. “Mereka (perusahaan) memang benar-benar kejam. Kehilangan lahan tak diganti. Tak tahu sekarang bagaimana kelanjutannya,” kata Yulita.
Yulita bersama perempuan-perempuan lain di Dusun Sabar Bubu memang menyerahkan segala urusan dengan perusahaan, termasuk semua perlawanan kepada laki-laki, baik suami maupun anak laki-laki. “Perjuangan itu lama dan waktunya panjang. Kami para perempuan membantu mendukung dari rumah saja,” celetuk Yulita sambil mengenang banyaknya kejadian yang terjadi di desanya.
Perlawanan warga terhadap penyerobotan lahan garap sudah dilakukan sejak 2020. Caranya pun beragam. Mulai dari pemberian sanksi hukum adat, aksi damai di depan kantor perusahaan, mengawal pengukuran tanah, hingga penahanan 13 unit alat berat agar perusahaan jera pada 2023. Namun hingga kini perusahaan bergeming.
Sebuah kawasan hutan adat seluas 31,4 hektare yang dikelola secara komunal oleh masyarakat Sabar Bubu turut terdampak. Dalam waktu singkat, hutan adat yang berada di RT Ketabar dan Blok J tersebut berganti dengan tumbuhan akasia. Menurut Fendi, penggundulan hutan dilakukan secara cepat dan masif oleh perusahaan.
Pembabatan hutan seluas satu blok atau setara 25-30 hektare diperkirakan hanya berlangsung selama dua minggu. Berdasarkan analisis spasial yang dilakukan oleh The TreeMap untuk Atlas Nusantara, sejak 2021-2023, PT Mayawana Persada membabat hutan hampir separuh dari luasan Singapura, yaitu 33.070 hektaree. Perusahaan membabat 11.8-5 hektaree hutan tropis, dan 16.118 hektaree konsesi kayu pulp di Ketapang dan kayong Utara. Sedangkan pada 2010-2020, perusakan hutan terjadi sebanyak 24 ribu hektaree.
Beralih dari Tanah Garapan
Rasa percaya masyarakat adat Dayak terhadap alam sudah berlangsung ratusan tahun. Mereka hidup dari apa yang mereka peroleh dari hutan dan tanam. “Mau makan, tanam padi. Mau ikan, lari ke sungai. Mau daging merah, tinggal berburu di hutan. Sayur, tinggal cabut saja dari tanah. Itu lah arti sejahtera bagi kami,” ujar Fendik Susupi, Kepala Adat Desa Kualan Hilir.
Namun sejak hutan dibabati oleh perusahaan, kata Fendi, masyarakatnya tak lagi bisa tenang. Sebagian dari mereka terpaksa untuk bekerja sebagai buruh lantaran tak ada lagi tanah garapan. Melati—bukan nama sebenarnya, sudah dua tahun bekerja sebagai buruh harian lepas sebagai pembibit pohon atau nursery di Mayawana Persada. “Saya waktu itu hanya membawa kartu keluarga dan KTP,” ujarnya tanpa mau disebutkan nama.
Sebagai buruh lepas harian Melati melakukan banyak pekerjaan, tapi tugas pokoknya ialah memasukkan kokopit (cocopeat) atau sabut kelapa ke media tanam bibit pohon akasia. Pekerjaan itu dilakukan Melati sedari pukul 7 pagi. Kalau cepat ia bisa menuntaskan pekerja setelah makan siang, tapi kebanyakan tugasnya itu tuntas pada jam 3 sore. “Sehari-harinya,
Dari pekerjaan hampir seharian itu ia dapat mengantongi sebesar Rp122 ribu per hari. “Dulu, Saya dapat mengantongi Rp 3 juta setiap bulannya, jika bekerja selama 25 hari setiap bulannya,” ungkapnya. Sebagian dari pendapatannya itu ia kirim ke anaknya yang tengah melanjutkan pendidikan tinggi di Yogyakarta.
Meski begitu, saat ini Melati mengaku sedang was-was dengan kondisi pekerjaannya. Di samping rumor yang beredar di kalangan pekerja mengenai pengurangan karyawan sampai 30%, jumlah hari kerjanya pun akan dipangkas. Kata dia, pekerja dibagi menjadi dua kelompok dengan waktu kerja berbeda. “Kelompok A bekerja selama seminggu, kemudian digantikan kelompok B pada minggu berikutnya,” jelas Melati.
Sistem kerja itu berdampak pada jumlah pendapatan Melati. Hari kerja yang sebelumnya sebanyak 25 hari, kini hanya 18 hari kerja, sehingga ia kini hanya beroleh pendapatan sekitar Rp2,1 juta perbulannya. “Setiap kali menerima gaji, saya mengirimi anak saya Rp2 juta setiap bulannya. Kalau gaji saya sekarang 18 hari kerja, maka semuanya akan dikirim buat anak,” katanya.
Penurunan pendapatan ini membuat Melati bingung. Selain mengirimi anak uang saku, ia juga perlu untuk membayar kasbon dan kebutuhan sehari-hari. Kembali menggarap lahan pun bukan pilihan bagi Melati lantaran sekarang sudah tak tersisa lahan garapan lagi. “Sudahlah, terima saja nyatanya,” ucapnya miris.
Melati bukan satu-satunya warga Kualan Hilir yang bekerja di PT Mayawana Persada. Sedikitnya terdapat 70 KK atau lebih dari 200 orang warga Desa Kualan Hilir yang bekerja di sana. “Saya sangat senang ketika hari gajian. Dapat uang, dapat bayar kasbon. Bahagia lah,” katanya.
Sebelum bekerja di Mayawana Persada, Melati menerima ganti rugi lewat skema yang diberi nama “tali asih.” Dengan skema itu tiap orang mendapat penggantian sebesar Rp1,5 juta per hektare dan janji biaya kayu sebesar Rp2.500 per kubiknya.
Sebagian warga lain yang menolak bersikeras bahwa ganti rugi tersebut tak cukup. Sebab dalam Peraturan Bupati (Perbup) Ketapang nomor 86 tahun 2016, harga dasar ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) didasarkan pada jenis, klasifikasi (tanaman muda dan tanaman produktif), serta satuan tanaman per hektarenya. Jika per batangnya dihargai Rp75 ribu, maka nominal yang seharusnya diterima sebesar Rp30 juta per hektare.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat, Hendrikus Adam menilai penguasaan wilayah kelola masyarakat oleh perusahaan sangat berdampak pada siklus hidup warga, terutama terkait kebutuhan pangan. “Ketika wilayah kebun dan ladang pertanian digusur, maka harapan mereka untuk terus bertahan dan mengakses pangan menjadi terbatas,” ujarnya.
Dampak lanjutannya, kata dia, ekonomi warga makin melemah. Ditambah dengan tekanan psikologis dan tradisi masyarakat adat yang akan mulai terpinggirkan. Ia pun mengaku tak heran apabila lambat laun masyarakat terdampak akan meninggalkan ladang. Sementara konflik terus berlanjut.
Pada 29 September 2022 lalu konflik antar warga terjadi. Suami dari Kiam adalah korbannya. Kepada Jaring.id ia menceritakan peristiwa nahas yang terjadi hampir dua tahun lalu. Saat itu, ia bercerita, suaminya, Matius Midin (54) pulang dari ladang lebih cepat dari biasanya dengan air muka tak biasa. Ia menundukkan wajah, matanya nanar, tertegun di depan pintu. “Semuanya habis, semuanya diambil. Dibakar,” ujar Midin kepada Kiam.

Tangis keduanya pun pecah. Kiam buru-buru ke dapur dan kembali dengan segelas air putih di tangannya. Midin menceritakan bagaimana 400-an pria warga Kampar Sebomban mengusirnya tanpa basa-basi dari ladang sembari melihat pondokannya lamat-lamat roboh hangus terbakar. “Kita dituduh berladang di luar batas administrasi kecamatan,” jelasnya.
Tidak hanya pondok Kiam yang dibakar, delapan pondok lainnya pun hangus hari itu. Padahal di dalam pondok terdapat padi ladang sekitar 6 hingga 7 ton. “Untung saja, suami saya tidak ikut melawan. Jika iya, pasti ikut dibakar suami saya,” kata perempuan anak tiga tersebut.
Sejak 2022, Desa Kualan Hilir dan Kampar Sebomban dipisahkan oleh dua kecamatan yang berbeda akibat pemekaran. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Bupati Ketapang. Sebelumnya, kedua desa termasuk ke dalam kecamatan Simpang Hulu. Sejak saat itu, Kampar Sebomban termasuk ke dalam area administrasi Kecamatan Simpang Dua yang juga termasuk ke dalam areal konsesi PT Mayawana Persada.
Meskipun begitu, Kiam menolak bahwa suaminya berkebun di tempat yang bukan miliknya. Hal itu disebut mengada-ngada dan hanya untuk kepentingan PT. Mayawana Persada saja. Pasalnya sejak dulu, warga kedua desa itu tidak pernah terlibat dalam konflik apapun. Sekarang, mereka tiba-tiba berubah dan langsung menyerang begitu saja. “Sudah sejak dulu-dulunya suami saya berkebun di sana. Sudah lebih dari 20 tahun,” jelasnya.
Selain pondok, ladang suaminya ikut digusur. Seluas 15 bidang lahannya hilang dalam sekejap mata. Selain padi, karet, sawit, nangka, cabai, dan jenis sayur-sayuran lainnya pun lenyap dalam semalam. “Kemarin suami saya masih menoreh mengambil getah, besoknya sudah tidak ada,” katanya.
“Apakah mungkin itu perbuatan masyarakat biasa? hebat betul kalau memang 400 orang itu yang bekerja,” Kata Kiam mengejek.
Setidaknya terdapat 59 warga yang lahannya dirampas perusahaan. Kiam dan suaminya hanya menyisakan satu petak ladang dekat rumah. Ketika hendak membantu suaminya, ia tak bisa berbuat apa-apa. Kesehatannya terus-terusan menurun sejak kejadian akhir September lalu. Padahal sebelumnya Kiam mampu berladang, memanen sayur, hingga menjualnya ke pasar. “Anak saya yang pertama jadi satu-satunya yang berkuliah di sini. Sudah tamat,” katanya.
Namun kesempatan seperti itu, menurut Kiam, tidak dapat dirasakan oleh adiknya yang sedang bersekolah di kelas 3 SMK. Ia dan suaminya sama-sama ragu untuk melanjutkan sekolah anaknya itu ke jenjang perguruan tinggi. “Terpaksa tidak kuliah. Buat makan saja susah,” sebut Kiam sambil mematut-matut foto anak pertamanya memakai toga.
Atas kejadian itu pemerintah mewanti-wanti agar tidak lagi terjadi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengimbau agar perusahaan menjalankan mekanisme kemitraan di area konsesi guna meredam konflik. Risno Murti Candra, Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK mengatakan, konsep kemitraan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri LHK nomor 285 tahun 2024. “Konteksnya, sama-sama mengelola kawasan. Bisa masyarakat adat, masyarakat setempat. Pemegang PB PH sebagai off taker-nya,” kata Risno ketika ditemui di Kantor KLHK, Jakarta.
Kemitraan itu, tambahnya, mengatur sejumlah ketentuan misalnya, subjek yang terlibat dalam kerja sama itu adalah masyarakat yang memang tinggal di sekitar konsesi. “Entitasnya kami tidak lihat adat atau tidaknya, tapi masyarakat yang betul-betul ada di situ,” kata Risno.
Komoditi yang dikembangkan dalam kerja sama itu pun harus sesuai dengan jenis tanaman kehutanan. “Tidak bisa sawit ada di situ,” ujarnya.
Hingga laporan ini terbit tim kolaborasi telah berupaya meminta kesediaan PT Mayawana Persada untuk melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang dikirim ke Ardian Santoso selaku humas perusahaan pada 27 April 2024 lalu tak berbalas. Sejak surat dikirim, secara berturut-turut mulai 30 April, 1 Mei, dan 3 Mei tim menanyakan perihal waktu wawancara atau jawaban tertulis, namun tak ada tanggapan. Begitu pula saat kami bertemu dengan Ardian pada 4 Mei 2024.
Laporan ini merupakan hasil liputan kolaborasi yang dilakukan oleh Jaring.id bersama Ekuatorial.com, Betahita.id, Mongabay.id, CNN TV, dan Pontianak Post atas dukungan Depati Project dan The Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ).