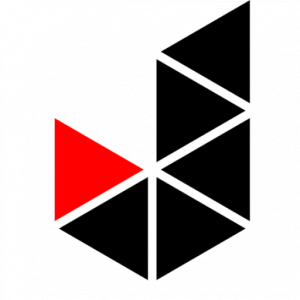Sebelum membuka seri obrolan NgeHAMtam episode “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada!” Haris Azhar sudah menyangka bakal terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (U ITE). Sebab situasi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia sedang memburuk. Sedangkan keberadaan kelompok pemegang kekuasaan menguat. Karena itu, Haris tidak heran apabila celah hukum yang ada di UU ITE bakal dimanfaatkan para pejabat.
“Penguasa formal—pejabat, dan material, misalnya kelompok-kelompok bisnis atau orang-orang kaya di lapangan. Itu juga menggunakan mekanisme yang mereka sebut penegakan hukum. Iya, sah. Tapi fairness-nya buruk, nggak adil,” tutur Haris kepada Jaring.id, 4 Juni 2022.
Terlebih ia mengaku sudah beberapa kali diperingatkan untuk tidak memuat konten sensitif di Youtube. “Saya nggak usah sebutkan lah siapa itu. Pokoknya beberapa kali diprotes,” ungkapnya.
Namun demikian, Haris tetap teguh pada pendirian untuk mendiskusikan laporan tersebut lewat Youtube. Ia meyakini bahwa laporan riset gabungan koalisi sipil penting diketahui publik. Apalagi hanya sedikit media yang mengangkat laporan tersebut ke permukaan. Padahal, menurut Haris, metodologi kajian sudah benar. Temuan riset pun sejalan dengan yang ia kerjakan saat bergabung dengan tim kemanusiaan Papua untuk kasus Intan Jaya.
Karena semua itulah, Haris sadar betul, mengungkap hasil riset juga berarti membuka kemunggkinan risiko mendapatkan ‘serangan balik.’ Termasuk, dilaporkan secara hukum. Dan prediksi Haris benar adanya.
Pada bulan yang sama, beberapa hari setelah video tersebut tayang di kanal YouTube-nya pada 20 Agustus 2021, Haris menerima somasi. Bulan berikutnya pada 22 September 2021, ia pun diadukan ke polisi. Adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang membikin laporan. Pensiunan TNI ini menganggap Haris melanggar pasal penghinaan dan pencemaran nama UU ITE.
“Jadi jangan mengatakan hak asasi yang ngomong saja, hak asasi yang diomongin juga kan ada. Saya juga tidak ingin anak cucu saya merasa bahwa, saya sebagai orang tuanya, kakeknya, membuat kecurangan di Papua. Saya tidak pernah lakukan,” ucap Luhut usai diperiksa sebagai pelapor di Polda Metro Jaya pada Senin, 27 September 2021.
Sekitar enam bulan setelahnya, tepatnya pada 23 Maret 2022 Haris diperiksa sebagai tersangka. Itu adalah pemeriksaan perdana. Belakangan, Haris baru tahu, rupanya penetapan tersangka sudah dilakukan sebulan sebelumnya. “Begitu naik penyidikan, kami nggak pernah dikasih tahu. Ternyata, waktu saya dipanggil polisi, penetapannya sudah ada satu bulan. Jadi bulan Maret itu kan diperiksa, ternyata penetapan tersangkanya bulan Februari,” ungkap Direktur Eksekutif Lokataru tersebut.
***
Dalam video tak sampai 30 menit ini, Haris membedah temuan bertajuk “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya,” bersama perwakilan koalisi masyarakat sipil. Salah satunya ialah Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti. Dalam video disebut bahwa operasi militer di Papua merupakan upaya ilegal.
Temuan lain ialah indikasi adanya relasi antara penempatan dan penerjunan militer di Papua—kajian mengambil kasus di Kabupaten Intan Jaya—tersebut dengan bisnis tambang. Setidaknya empat perusahaan teridentifikasi berpotensi diuntungkan. Salah satunya, diduga terhubung dengan Menko Marves Luhut Pandjaitan.
Begitulah awalnya keberatan Luhut yang lantas berbuntut somasi. Ia menghendaki kedua aktivis HAM itu meminta maaf. Sampai kemudian, berujung pada pelaporan Haris dan Fatia ke Polda Metro Jaya.
Kini, hampir lima bulan Haris memanggul status tersangka kasus dugaan pencemaran nama, usai menyampaikan kritik berbekal riset. Keganjilan demi keganjilan dirasakannya sepanjang proses hukum.
Selain soal status perkara dan penersangkaan yang disebutnya dilakukan ‘diam-diam,’ Haris curiga penyidik polisi tak mengantongi bukti kuat. “Ketika saya diperiksa, saya itu belajar, mereka itu nggak punya bukti. Pelapor dan polisi itu hanya punya bahan dari saya—yaitu judul dan download-an video ditranskrip. Cuma itu saja,” kata praktisi hukum yang juga kerap mendampingi dan mengadvokasi korban UU ITE.
“Jadi mereka nggak punya bahan; mencemarkan nama baik, melakukan penghinaan. Mestinya dibuktikan, di bagian mananya (menghina dan mencemarkan nama). Misalnya gara-gara pencemaran nama, kantornya Luhut runtuh, misalnya. Mestinya dalil itu yang dipakai,” imbuh Haris.
Proses mediasi—yang berulang kali dipromosikan Kapolri Listyo Sigit untuk penanganan perkara dugaan pelanggaran UU ITE—pun nyatanya tak berjalan mulus di lapangan. Terlebih saat dihadapkan pada pelapor yang merupakan pejabat Negara. Haris merasa pengambilan keputusan polisi timpang alias berat sebelah ke pihak pelapor. Hal itu tercermin dari cara polisi mengambil keputusan dan memperlakukan pihak yang berkasus. “Gara-gara saya sama Fatia nggak datang (undangan mediasi). Apa yang terjadi? Kasusnya naik ke penyidikan,” ungkap Haris mencontohkan diskriminasi yang ia alami.
Namun, kata Haris, hal itu tak berlaku untuk Luhut. Pasalnya pada pemanggilan sebelumnya di mana Haris dan Fatia menghadiri undangan, justru Luhut lah yang tidak menghadiri mediasi. “Apa indicator? ukurannya apa? apa excuse? Enggak datang mediasi kok naik ke penyidikan? Kenapa waktu pelapor itu melapor, begitu ada mediasi, dia enggak datang, mestinya laporannya dibatalkan,” lanjut dia.
“Kok kami yang dibilang tidak punya itikad baik untuk mediasi,” tukas Haris mempertanyakan.
Ketidakjelasan penerapan pasal dalam UU ITE, ditambah dengan relasi kuasa pelapor, pada akhirnya dinilai memunculkan ketimpangan dalam proses penegakan hukum. Itu mengapa Haris menyebut pemidanaan terhadap dirinya lebih mirip panggung humor belaka. “Saya menganggap, yang gini-gini ini kan salah satu bubble di tengah panggung of joke, aja kan. Ini panggung becanda aja,” nada bicaranya terkesan santai saat mengungkapkan itu.
Berulangnya Kritik Berujung Pidana
Rusdianto Samawa, diwawancara dalam kesempatan dan waktu berbeda secara tak sengaja mengutarakan hal yang hampir senada. Menurutnya, pelaporan UU ITE oleh pejabat seperti hanya jadi bagian dari ‘panggung guyon penguasa.’ Bahkan ia curiga proses hukumnya juga sekadar untuk menyenangkan penguasa.
Rusdianto, adalah aktivis nelayan yang juga dijerat dengan pasal karet UU ITE. Bedanya dengan Haris, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia ini tak lagi berstatus tersangka, melainkan terpidana. Putusan hakim di pengadilan pertama, banding, hingga kasasi di Mahkamah Agung menyatakan Rusdianto terbukti bersalah.
Mirip dengan kasus Haris. Pemidanaan terhadap Rusdianto berawal dari kritik ke pejabat publik yang diutarakannya melalui akun media sosial Facebook dan Youtube.
Ini kali, pelapornya Susi Pudjiastuti. Pada 6 Juli 2017 silam, Susi—saat itu menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP)—mengadukan Rusdianto ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama. Tak sampai dua bulan, Rusdianto ditetapkan sebagai tersangka.
Dari amar putusan hakim, sedikitnya ada Sembilan penggalan unggahan yang dipermasalahkan Susi. Dua di antaranya:
“Heran, merasa heran, sudah gagal, ditambah dengan kebijakan Permen yang ugal-ugalan. Sekarang ditambah juga dengan perilaku tidak baik yakni bau korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.”
“KKP RI juga mendistribusikan kapal kepada masyarakat melalui koperasi yang dibentuknya sendiri dan ditunjuk langsung pengurusnya, tanpa ada proses pemenuhan syarat-syarat sesuai Undang-Undang Koperasi.”
Atas unggahan itu, hakim di pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta pada 2018. Merasa tak puas, Rusdianto mengajukan banding. Tapi kemudian, putusan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta pun menguatkan vonis di pengadilan tingkat pertama.
Masih tak menyerah, Rusdianto mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. “Saya pasrah (waktu itu), tapi demi Allah, saya tidak pernah berniat mencemarkan nama baik. Dan Ibu Susi juga tidak tercemarkan juga nama baiknya, karena dia pejabat,” tutur Rusdianto kepada Jaring.id, 5 Juni 2022.
Namun putusan kasasi tak banyak mengubah situasi. Rusdianto tetap dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal penghinaan dan pencemaran nama. Meski, vonisnya lebih rendah yakni enam bulan penjara dan 1 tahun masa percobaan. “Tapi sampai ada putusan ini, saya tidak merasa bersalah dan tidak pernah merasa mencemarkan nama baik dia,” pengakuan yang diucapkan berulang-ulang, termasuk saat ia menjalani proses hukum.
Rusdianto masih tak habis pikir, mengapa pendapat soal kebijakan pejabat publik malah dianggap sebagai penghinaan dan pencemaran nama. Bukankah itu bentuk penilaiannya sebagai warga?
Selain kritik berbuah pidana, kejanggalan lain yang dirasakan Rusdianto adalah proses penersangkaan yang dianggapnya kelewat kilat. Tak sampai dua bulan. Yang juga mengganjal, ia mempertanyakan soal kuasa hukum Susi. Bila memang pelaporan Susi saat itu dilakukan secara pribadi—atau bukan sebagai pejabat publik—mengapa kuasa hukumnya adalah tim biro hukum KKP. “Kalau pribadi, mestinya surat kuasanya tidak boleh dari dalam struktur KKP, mestinya ke pengacara independen,” Rusdianto mempersoalkan.
Dikonfirmasi mengenai pelaporan pada 2017 lalu, Susi Pudjiastuti tak merespon panggilan maupun pesan Jaring.id. Sementara Lilly Aprilya Pregiwati yang saat itu menjabat Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat KKP beralasan kurang mengetahui detail kasus dan ihwal bantuan hukum dari tim biro hukum KKP. “Dalam hal ini yang dapat menjelaskan tentang hal ini adalah bu Susi. Semoga bu Susi menjawab chat Anda,“ tutur Lilly yang kini menjabat Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Badan Riset dan SDM KKP kepada Jaring.id, 30 Juni 2022.
Mengapa Pejabat Leluasa Menjerat Menggunakan UU ITE?
Nyaris lima tahun berselang, situasi ini tak berubah. Kasus Rusdianto pada 2017, pada 2021 juga menimpa Haris Azhar.
Pelaporan serupa dialami Riski Afif Ishak pada 2020. Ia jadi tersangka lantaran dianggap mencemarkan nama usai menyampaikan hasil kajian Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) terkait dugaan korupsi di tempat pelelangan ikan Wameo, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Pelapornya, adalah Walikota Baubau saat itu, A.S. Tamrin (almarhum).
Baca juga: Di Koran Wajahku Terpampang Sebagai DPO
Data pemantauan dan pendampingan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) sepanjang 2021 menemukan, sedikitnya 30 kasus pemidanaan dengan total 38 korban kriminalisasi UU ITE. Dari jumlah itu, pejabat publik—mulai setingkat RT hingga menteri—tercatat sebagai pelapor terbanyak, yakni 10 kasus atau 35,7 persen.
Koordinator Paguyuban Korban UU ITE, Muhammad Arsyad menyatakan pejabat sudah jadi langganan menempati daftar puncak pelapor UU ITE. “Dari tahun ke tahun itu selalu menempati posisi terdepan,” kata Arsyad kepada Jaring.id, 30 Juni 2022.

Dosen Hukum Tata Negara dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Herlambang P. Wiratraman membeberkan setidaknya empat alasan mengapa pejabat leluasa dan gemar memakai pasal karet dalam UU ITE.
Pertama, pemilik kekuasaan begitu mudah menggunakan otoritas, jaringan kekuasaan maupun, kepentingan dominannya sehingga merasa lebih dibandingkan yang lain.
Kedua, penjelasan sosiologis hukum juga menyajikan argumen bahwa hukum mengenali struktur sosial. “Hukum akan lebih membentengi mereka yang kuat, sehingga warga biasa kerap dikorbankan dengan posisinya selalu yang lemah,” terang Herlambang kepada Jaring.id, 2 Juni 2022.
Ketiga, UU ITE pun rentan disalahgunakan lantaran sedari awal konstruksi pasal-pasalnya banyak yang bermasalah. “Terutama cyber defamation, penafsiran hoaks. Sekalipun ada SKB, tidak banyak berguna, karena di lapangan mindset penegakan hukumnya tak mau belajar upaya maju perlindungan hak-hak digital,” tuturnya.
Terakhir, lanjut Direktur Pusat Studi Hukum dan HAM LP3ES ini, penegakan hukum—baik polisi, jaksa bahkan hakim—kerap bekerja secara tak profesional. Menurut Herlambang, sebagian dari mereka bahkan tak banyak mengikuti perkembangan kemajuan perlindungan HAM dan hak-hak digital. “Tak mengherankan, banyak putusan hakim ikut-ikutan ngawur dan tak mengikuti doktrin hukum yang berkembang,” tukas dia lagi.
Padahal, pelaporan oleh pejabat publik mestinya tak perlu terjadi. Pasalnya, menurut Arsyad, kritik atau masukan dari warga merupakan bagian dari jabatan publik. “Masyarakat seperti kami, yang tidak punya kekuatan, hanya mempunyai modal riset, hanya mempunyai modal untuk mengelola data, akhirnya sedikit-sedikit dijadikan tersangka,” kata Arsyad yang juga pernah dikriminalisasi dengan pasal karet UU ITE.
“Mengapa orang yang hanya mengungkapkan fakta adanya kesalahan mengurus pada pejabatnya, tiba-tiba harus dijadikan tersangka?” ucapnya retoris.
Yang juga perlu diwaspadai dari tren pelaporan UU ITE oleh pejabat publik, lanjut Arsyad, adalah mulai munculnya kecenderungan pejabat pelapor maupun penegak hukum yang menggabungkan pasal UU ITE dengan pasal lain, sehingga ancaman pidananya bisa lebih dari lima tahun. Dengan begitu, ada dalih untuk menahan korban kriminalisasi.
Sejak UU ITE disahkan pada 2008, lebih dari 380 orang dijerat dengan pasal karet. Latar belakang korban pun beragam. Mulai dari aktivis, warga, pendamping atau korban, jurnalis hingga akademisi. Semuanya bisa kena.
Sebagian besar korban itu dikenakan pasal penghinaan dan pencemaran nama. Banyaknya penggunaan pasal ini sebetulnya menjadi indikasi adanya relasi kuasa yang timpang antara pelapor dan terlapor dalam perkara UU ITE. “Hampir semua kasus yang terkait UU ITE, pasti relasi kuasa pelapornya jauh lebih kuat ketimbang perkara-perkara lain. Karena pelaku (pelapor UU ITE) biasanya pejabat, pemodal, yang kerap dibantu oleh oknum penegak hukum,” ungkap Arsyad yang juga pernah menjadi korban pasal karet UU ITE.
Riset Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang menelusuri putusan kasus sepanjang 2016 hingga Februari 2020 menemukan gambaran serupa. Pasal pencemaran nama atau Pasal 27 ayat (3) jadi yang paling banyak dipakai. Dari 768 perkara di seluruh Indonesia terkait penerapan Pasal 27-29 UU ITE, sebanyak 286 atau 37,2 persen di antaranya adalah pasal pencemaran nama.
Kajian mendapati bahwa praktik penerapan UU ITE justru memfasilitasi ketimpangan relasi kuasa, alhasil ada banyak korban yang merupakan kelompok rentan atau lemah.
Temuan soal ketimpangan relasi kuasa, rendahnya standar pembuktian, hingga penafsiran unsur-unsur tindak pidana yang tidak jelas ini merupakan bagian dari belantara masalah dalam penerapan UU ITE.
Ilusi SKB
Itu sebab, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE. Surat keputusan yang diteken Menkominfo Johnny G. Plate, Jaksa Agung Burhanuddin dan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu dimaksudkan menjadi panduan agar tak ada lagi jerat pasal karet dalam UU ITE.
Baca juga: Semua Bisa Kena
Pada beberapa kesempatan, Kapolri Listyo Sigit pun berulang kali mengingatkan jajarannya untuk mengutamakan restorative justice atau langkah damai melalui mediasi dalam penanganan dugaan pelanggaran UU ITE. Sebelum SKB terbit, Kepolisian bahkan telah memiliki Surat Edaran (SE) tentang penerapan UU ITE yang dikeluarkan Februari 2021.
Namun begitu, upaya pemidanaan dengan jerat pasal karet UU ITE tetap terjadi. Misalnya yang dialami dua aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Perkara dengan pelapor Luhut Pandjaitan ini tetap naik ke penyidikan.
Anggota tim kuasa hukum Haris Azhar, Nur Kholis mensinyalir proses penegakan hukum kliennya sarat masalah. Pertama, ada indikasi diskriminasi perlakuan terkait hak-hak tersangka ketika berhadapan dengan pelapor yang adalah pejabat. “Jadi kami meminta ada review, mendesak kepolisian melakukan pengawasan, menguji kembali (laporan), tapi itu tidak dilakukan. Jadi tiba-tiba, cepat sekali prosesnya,” bebernya kepada Jaring.id, 1 Juni 2022.
Kedua, SKB pedoman implementasi pasal tertentu UU ITE rupanya tak memuat mekanisme yang jelas untuk mengklasifikasikan apakah sebuah materi ini tergolong penilaian, pendapat, hasil evaluasi, sebuah kenyataan, ataukah pencemaran nama. Akibatnya, apa yang disampaikan kliennya masuk sebagai delik pencemaran nama. “Dalam proses penyidikan kami tidak tahu apakah polisi mendengar keterangan Kominfo, apakah polisi mendengar keterangan ahli atau tidak. Itu yang justru dipertanyakan,” papar Nurcholis.
Ketiadaan petunjuk teknis yang rinci dalam SKB itu pada akhirnya tak menyelesaikan masalah pasal karet dalam UU ITE. Nurcholis khawatir, ketidakjelasan SKB malah memberikan peluang tafsir yang berisiko disalahgunakan sampai ke soal potensi kewenangan berlebih pada polisi. “Sehingga cenderung arbitrary (sembarangan) atau bahkan sewenang-wenang. Potensinya besar bagi polisi untuk melakukan penilaian sesuai dengan diskresinya sendiri, jadi diskresinya menjadi eksesif,” ia menjelaskan.
“Jadi ada celah hukum yang memberikan risiko besar bagi polisi untuk diskresi, menentrukan sendiri apa itu fakta, apa itu kritik, apa itu riset atau bukan, atau semua dipukul rata defamasi (pencemaran nama),” lanjutnya.
Dikonfirmasi mengenai penerapan SKB yang dinilai tak berjalan baik serta indikasi diskriminasi penegakan hukum dalam perkara UU ITE dengan pelapor pejabat negara, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Asep Edi Suheri meminta waktu dan menjanjikan penjelasan. “Ok. Nanti setelah kegiatan rapat kerja saya coba jawab. Saya masih tugas raker di luar kota,” kata Asep kepada Jaring.id, 10 Juni 2022.
Tapi hingga berita ini terbit, Asep tak kunjung menjawab telepon maupun membalas pesan Jaring.id. Adapun Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Ahmad Ramadhan beralasan tak memiliki data rinci, sehingga harus terlebih dulu berkoordinasi dengan Direktorat Siber untuk merespons ihwal kasus UU ITE.
Kelemahan dan celah hukum SKB memperkuat alasan untuk segera merevisi pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE. Arsyad yang tergabung dalam Koalisi Serius Revisi UU ITE juga mengingatkan, SKB bukan produk hukum dan tidak berkekuatan hukum. Itu mengapa, menurut dia, satu-satunya jalan untuk memperbaiki sistem dan mengurangi gelombang kriminalisasi adalah dengan merevisi pasal bermasalah dalam UU ITE. “Apalagi ketika pelapornya adalah pejabat ataupun penguasa, SKB itu hanya sebuah kertas hanya sebuah pedoman yang tidak mempunyai landasan hukum yang kuat yang kadang diabaikan penegak hukum,” pungkas Arsyad. (Ika Manan)