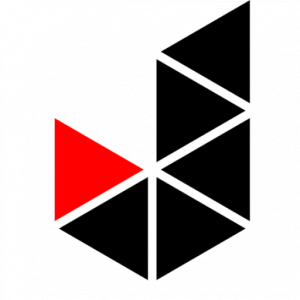Hartoyo menutupi separuh wajahnya dengan tangan. Suaranya bergetar ketika menonton film berjudul “Bulu Mata” yang diputar pada Kamis, 1 September 2022. Film tersebut kini hanya dapat ditonton di kalangan terbatas seizin Suara Kita demi keamanan. “Takut kalau teman-teman di sana diburu,” ungkapnya kepada Jaring.id dan Koran Tempo.
Pendiri Suara Kita—organisasi advokasi kesetaraan dan keadilan bagi kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, dan interseks (LGBTQI) ini pun mengaku tak kuat menonton film tersebut, sehingga ia memilih untuk memecah ingatan pada peristiwa traumatik dengan memainkan gawai. “Saya sudah nonton berkali-kali, tapi masih saja nggak kuat. Dada terasa sesak,” ujar Hartoyo.
Film yang memenangkan Piala Citra kategori dokumenter panjang Festival Film Indonesia pada 2017 lalu ini merekam aktivitas sejumlah transpuan di Aceh menjelang pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Mereka antara lain Citra, Dea, Lisa, dan Puri.
Film berdurasi lebih dari satu jam dibuka dengan aktivitas transpuan di sebuah pasar. Dengan bergandengan tangan mereka menyapa para pedagang. Ada penjual macam-macam masakan, sayur, dan ikan segar. Saat membeli ikan, tak sedikit lelaki yang menyiuli dan menyoraki. Bahkan salah seorang dari mereka tak segan berkata sarkastik di tengah keramaian. “Potong saja pakai parang nggak ada gunanya,” seru pedagang dalam film dokumenter. Tentu yang dikatai tidak membalas. Ia hanya menebar senyum.
Menurut Hartoyo, barisan adegan dalam film hanya bagian kecil dari pelbagai masalah yang dialami transpuan di maupun di luar Aceh. Terlebih ketika hukum syariah diberlakukan. “Masih sama kondisinya sampai saat ini,” ungkapnya. Karenanya tak sedikit dari mereka yang mengambil pilihan sulit untuk keluar dari Aceh. Vanesa salah satunya. Transpuan asal Meuraxa, Kota Banda Aceh ini diusir dari Aceh karena bersalin gender. “Kami bantu melarikan diri dari Aceh, karena dipersekusi tengah malam, kami sempat ungsikan ke Medan karena itu kota yang paling dekat dari Aceh,” kata Hartoyo.
Kisah itu bermula tujuh tahun lalu. Lewat tengah malam pada Juli 2015, pintu kamar kosnya berdentum kencang. Kaget, dia langsung membuka pintu dan mendapati lebih dari sepuluh orang yang langsung menyeretnya ke luar rumah. Tanpa sempat berkata-kata, Vanesa dihujani tinju. Para pelaku terindentifikasi sebagai pemuda dan orang tua setempat. Kata dia, ada juga aparat. “Saya dihajar habis,” ujar Vanesa yang saat itu mengenakan daster bermotif bunga. Air matanya menetes saat menceritakan peristiwa pada malam nahas itu.
Sembari dipukuli, Vanesa diarak menuju pos satpam. Dia digunduli, lalu disiram air comberan. Warga yang berkerumun seperti terhibur dan bergantian mengabadikan tindak kekerasan itu dengan kamera telepon seluler. “Di situ saya nangis. Mana keadilan bagi kami sebagai transpuan?” kata Vanesa. Rizky, nama lahir Vanesa, juga dituntut membayar denda berupa dua kambing. Hewan itu menjadi bagian dari upacara adat pembersihan kampung. Ia dianggap telah mengotori lingkungan. “Banda Aceh itu ngeri lah. Ketat banget syariatnya. Saya kena denda dua kambing dan uang Rp 500 ribu,” kata dia saat ditemui di sela gedung pencakar langit di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu, 10 Agustus lalu.
Sudah digebuki, dikenai denda, diusir pula. Dia dipaksa menandatangani surat pernyataan yang berisi ancaman hukuman cambuk jika kedapatan beraktivitas di Aceh. “Saya hampir depresi. Saya lahir dan besar di Aceh. Masak harus pindah,” kata Vanesa.
Vanesa pun terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya menuju Medan. Di sana, dia bekerja di kedai minuman keras. Demi penghidupan yang lebih baik, dia hijrah ke Jakarta pada 2018.
Impian terbesarnya adalah pulang ke Banda Aceh. Vanesa ingin mengunjungi makam ayah, ibu pertama, dan kakak tirinya. Ketiganya korban tsunami 2004. Kala itu, Rizky, 7 tahun, berada di Medan. Dari televisi, dia melihat gelombang laut memporak-porandakan kota kelahirannya.
Sampai saat ini, Vanesa masih berkomunikasi dengan keluarga lewat panggilan video. Salah satu orang yang sering dihubungi adalah kakak kandungnya yang kini tinggal di Medan. “Saya kangen, tapi saya pendam saja. Saya terakhir bertemu langsung dengan kakak itu pada 2017,” ujar Vanesa sembari mengingat orangtuanya. “Mau pulang sekalian ziarah ke makam ayah dan ibu,” ia menambahkan.
Selain kehilangan keluarga, Vanesa kehilangan hak suara. Kendati memiliki Kartu Tanda Penduduk dan mendapat pemberitahuan untuk memilih di desanya, ia tak dapat mencoblos pada pemilihan umum 2019. Besar kemungkinan hal serupa berulang pada pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024. Ia khawatir kena cambuk saat pulang kampung. “Jadi, saya golput saja. Saya ingin menjaga nama baik keluarga saya juga,” ungkapnya.
***
Hidup jauh di pulau seberang, Vanesa menjadi “juru bicara” bagi ribuan transpuan yang masih bertahan di Aceh. Akhir Juli lalu, seorang pegiat kesetaraan identitas gender memberikan nomor telepon seluler Vanesa dan seorang transpuan lain yang juga meninggalkan Aceh. “Yang mereka alami dulu, sama dengan yang dialami transpuan Aceh sekarang ini,” kata sumber yang enggan disebutkan identitasnya tersebut. Amat disayangkan, seorang transpuan lain yang memilih hengkang ke luar negeri belum merespons ketika laporan ini diturunkan.
Sejak Juli lalu, tim kolaborasi berkomunikasi dengan sejumlah transpuan di beberapa kabupaten dan kota di Aceh. Namun atas pertimbangan keamanan, semuanya kompak meminta agar cerita tentang kondisi mereka saat ini tak ditulis. “Kami akan dikejar-kejar,” kata seorang di antara mereka.
Mendapatkan informasi secara terbuka tentang kondisi transpuan dari kalangan akademisi dan kelompok sipil di Aceh juga tak mudah. Mereka menyebut, “Ini isu sensitif di Aceh.” Bagaimana pun, kata seorang di antara mereka, Qanun Jinayat adalah peraturan yang berlaku di Serambi Mekah.
Kabar buruknya, ancaman terhadap transpuan di Aceh bukan tidak ada. Transpuan di Aceh saat ini memilih untuk lebih disiplin menghindari petaka, seperti tidak keluar malam. Salah-salah mereka terjaring razia yang justru dianggap positif oleh sebagian kelompok masyarakat. “Setiap menjelang pemilihan, razia meningkat. Nanti akan disusupi kepentingan politikus setempat untuk menaikkan citra,” kata seorang sumber tim kolaborasi.
Baca juga: Habis Pemilu, Transpuan Dibuang
Peristiwa yang dialami Vanesa tujuh tahun lalu terjadi tak lama setelah pemerintah Aceh memberlakukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pendek kata, peraturan daerah ini mengatur perbuatan yang dilarang syariat Islam.
Sebenarnya, tak satu pun pasal dalam Qanun tersebut yang menyebut transgender. Hanya saja, kelompok minoritas tersebut rentan menjadi sasaran dengan adanya larangan Liwath. Qanun mengartikannya sebagai perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Ada juga larangan Musahaqah atau perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling-saling menggosok-gosokkan anggota tubuh untuk memperoleh kenikmatan seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.
Hukuman atas dua perbuatan tersebut sama. Pelakunya diancam 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.
Sejak saat itu, razia marak digelar di seantero Aceh. Vanesa hanya salah satu korbannya. Hartoyo, Ketua Suara Kita, beberapa kali ikut mengurus evakuasi. “Teman-teman di sana sebelum Qanun masih bisa kerja, buka salon atau warung kopi, sekarang sudah tidak bisa,” tuturnya, 1 September lalu.
***
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Irawan Abdullah mengklaim tidak ada diskriminasi hukum syariah terhadap transpuan. Mereka diberikan haknya untuk berpartisipasi dalam proses politik.
Menurut Irawan, qanun tidak dibuat untuk membatasi transgender. Aturan syariah tersebut, dia melanjutkan, hanya melarang seseorang melakukan kegiatan yang dilarang agama, seperti perilaku seks yang dianggap menyimpang maupun perzinahan. “Jadi, itu yang diburu qanun. Bukan orangnya, melainkan perilakunya,” ujarnya.
Komisi Independen Pemilihan Aceh menyatakan kelompok marginal seperti transpuan menjadi satu sasaran sosialisasi pemilu. Sebab, mereka kerap terpinggirkan dalam proses demokrasi lima tahunan itu. “Mereka jadi subyek kami untuk memastikan hak konstitusi mereka bisa digunakan,” kata Ketua Divisi Teknis KIP Aceh, Munawarsyah.
Dia memastikan semua orang bisa menggunakan hak pilihnya selama memenuhi syarat yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Satu di antaranya adalah bisa memilih jika telah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki KTP elektronik. Kendalanya, menurut Munawarsyah, sebagian transpuan yang tinggal di Aceh merupakan pendatang yang tidak mengubah domisilinya.
Mereka yang tidak mengubah domisili atau mengajukan permohonan pindah memilih, kata dia, bisa terancam kehilangan hak pilihnya. “Sering kami sampaikan kepada komunitas marginal bahwa kondisi perubahan administrasi kependudukan penting agar hak mereka memilih dan dipilih terjamin oleh konstitusi,” ujar Munawarsyah.
Kondisi sosial juga membuat transpuan tidak nyaman dalam menggunakan hak pilihnya. Misalnya saat jadi pusat perhatian di tempat pemungutan suara. “Kondisi sosial-agama juga tidak bisa dikesampingkan,” kata dia. “Kelompok ini memang belum bisa diterima oleh seluruh masyarakat Aceh,” lanjutnya.
Menurut Munawarsyah, penolakan tersebut bukan karena aturan syariah. Regulasi Qanun Jinayat justru melindungi transpuan dari pelecehan seksual. Regulasi syariah tersebut, kata dia, hanya menempatkan laki-laki sebagai laki-laki dan begitu juga dengan perempuan.
Yang mesti juga dipahami, dia melanjutkan, setiap wilayah mempunyai peraturan yang menjadi kesepakatan masyarakat umum. Peraturan publik tersebut bisa dibuat mengacu pada nilai budaya maupun agama. Di dalam Qanun Jinayat diterapkan prinsip syariah Islam. Satu aturannya, kata dia, memang diwajibkan bagi pria muslim mengenakan pakaian yang menutup aurat—antara pinggang dan lutut.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan diskriminasi sosial maupun politik yang dialami transpuan di Aceh merupakan fenomena gunung es. “Terutama untuk memperoleh hak asasi mereka,” ucapnya kepada Jaring.id dan Tempo, Rabu, 14 September 2022 melalui telepon.
Sebagai warganegara, lanjut Usman, transpuan memiliki hak yang sama secara konstitusional maupun hukum. Ia bebas untuk memilih. Bahkan berhak mencalonkan diri sebagai kontestan pemilihan umum. “Jika fenomena itu tidak dihentikan, maka itu sama dengan memperlihatkan kegagalan pemerintah untuk melindungi perempuan transgender dari perlakuan yang merendahkan martabat mereka sebagai manusia,” jelasnya.
Kolaborasi peliputan ini terselenggara berkat dukungan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan The Asia-Pacific Regional Support for Elections and Political Transitions (RESPECT). Program tersebut juga melibatkan Philippines Center for Investigative Journalism (PCIJ) dan Lafaek News (Timor Leste).
Tim Kolaborasi
Penanggung Jawab: Muhammad Kholikul Alim (Jaring.id); Agoeng Wijaya (Koran Tempo)
Penulis: Abdus Somad, Reka Kajaksana (Jaring.id); Shinta Maharani, Imam Hamdi, Riri Rahayuningsih (Koran Tempo)
Penyunting: Damar Fery Ardiyan (Jaring.id); Agoeng Wijaya, Rusman Paraqbueq (Koran Tempo)
Foto: Shinta Maharani (Koran Tempo), Abdus Somad (Jaring.id)