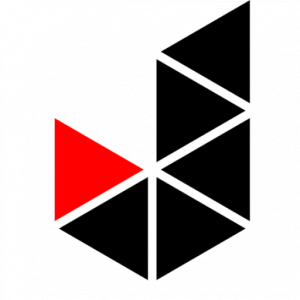“Apakah menentukan pilihan politik berdasarkan kesamaan agama, ras, atau jenis kelamin, itu salah?” Pertanyaan tersebut bakal memancing debat tak berkesudahan di tengah tensi politik di Indonesia yang menghangat beberapa tahun belakangan.
Dari seratusan lebih peserta diskusi bertajuk “Media dalam Politik Identitas” yang dihelat Jaringan Indonesia untuk Jurnalisme Investigasi (JARING) dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Jumat (20/7) lalu, beberapa diantaranya mungkin berusaha mencari jawaban atas pertanyaan tersebut dari cendekiawan sekaliber Ariel Heryanto. Didapuk sebagai pembicara, Herbert Feith Professor untuk Studi Indonesia di Monash University tersebut memberi jawaban retoris atas pertanyaan tersebut.
“Buat saya jelas nggak salah, tapi apakah itu (memilih berdasarkan kesamaan identitas) yang terbaik?,” tukas Ariel.
Ariel tak berniat memberi solusi praktis untuk pemilih atau partai politik di tengah menguatnya politik identitas di Indonesia. Dari paparannya sepanjang diskusi Ia lebih banyak membahas akar dari menguatnya politik identitas dan kebencian yang menyertainya.
Kebencian

Ariel menyebut kebencian hadir sepanjang sejarah Indonesia, meski tak selalu berkobar hebat. “Kita mulai membenci Belanda karena kolonialismenya; diajak mengarahkan kebencian pada neo-kolonialisme, liberalisme, dan segala hal yang tidak revolusioner oleh Soekarno; diharuskan membenci semua yang dianggap tidak Pancasila oleh Soeharto; dan masuk dalam kebencian berdasarkan kategori Islam dan tidak/kurang Islam sesudah 1998,” ungkap Ariel.
Singkatnya, kebencian melibatkan proses inklusi dan ekslusi. Jika bukan kawan, maka bisa disebut lawan. Kebencian dilibatkan dalam pembentukan identitas yang pada gilirannya dimobilisasi dalam panggung politik.
“Sekarang tampaknya ujaran kebencian itu terjadi begitu hebatnya, sampai-sampai, seakan-akan seorang calon presiden yang bagus adalah presiden yang bisa membenci a, b, c.” kata Ariel.
Ia melanjutkan, “Kebencian seakan-akan menjadi salah satu kriteria menjadi tokoh. Itu mengerikan sekali. Dan ini bukan terjadi pada setiap zaman, tidak setiap hari, tidak setiap tahun.”
Dari mana kebencian ini berasal? Ketimpangan atau ketidakadilan serta angan-angan atau obsesi terhadap “kemurnian” atau “keaslian”merupakan akar dari kebencian. Ariel menyebutnya sebagai “racun”. Perkembangan sains dan teknologi membuat penyebaran “racun” tersebut makin menjadi.
Dahulu, proses ungkapan kebencian terkonsentrasi di tangan industri media dan elite politik. Perkembangan teknologi menghancurkan batasan tersebut. Saat ini hampir setiap orang memiliki kerannya masing-masing untuk menyuarakan kebencian.
“Celakanya, teknologi ini seringkali memperbesar kemampuan indera kita, tetapi tidak akan pernah berimbang memperbesar kemampuan emosi dan nalar kita,” imbuhnya.
Masyarakat mampu melihat banyak hal baru dengan kemajuan teknologi. Namun, tidak semua siap mendengar dan melihat hal-hal baru tersebut.
Sia-sia
Di sela diskusi, seorang audiens yang sempat berkecimpung dalam partai politik menyebut bahwa identitas terbukti lebih “laku” dijual dibandingkan program. Pada beberapa kasus, Ariel menilai, hal tersebut ada benarnya.
“Pilgub Jakarta itu memang menarik, saya menduga itu merupakan muara atau timbunan sejumlah masalah yang berbeda-beda. Yang tidak bisa dengan mudah direproduksi, diulang di tempat-tempat yang berbeda konteksnya. Jadi memang agak khusus,” terangnya.
Tensi politik yang meninggi akibat mobilisasi identitas nyatanya tidak terjadi di daerah-daerah lain yang baru usai menghelat Pemilihan Kepala Daerah. Namun, bukan berarti menguatnya kebencian dan politik Identitas yang terjadi belakangan tidak punya benang merah.
“Selama ada ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi maka ada rasa tidak suka. Kalau orang tidak suka dan orang benci, tentu saja maklum kalau ada ujaran kebencian,” ujarnya.
Ariel menegaskan bahwa sejarah manusia adalah sejarah ketidakadilan dan ketimpangan. Menariknya, kebencian tidak lantas berkobar hebat di setiap masa.
Alih-alih mencari alasan di balik kebencian yang menyesaki media massa dan ruang publik di Indonesia belakangan ini, Ia mengajak kita bertanya mengapa kebencian tidak selalu menguat? Sibuk mengurusi ujaran kebencian ibarat mencincang air. Bakal sia-sia jika kesenjangan tak juga jadi perhatian.
“Orang-orang menderita itu lari kemana? Dia butuh perwakilan supaya suaranya didengar,” tegasnya.
Andaikata mereka yang menderita punya saluran yang sah dan terlembaga untuk menyampaikan keluhannya, panggung politik Indonesia bakal punya cerita berbeda. Pesan itu yang mungkin coba disampaikan Ariel dalam diskusi kemarin. (Debora Blandina Sinambela/M.Kholikul Alim)