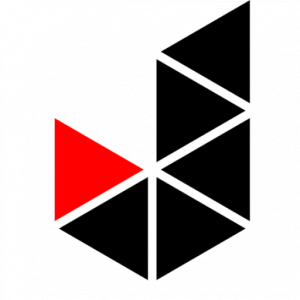Bulan lalu, wartawan Serambi Indonesia Said Kamaruzzaman melakukan investigasi di belantara hutan lindung di Aceh Tamiang. Bersama GeRAK Aceh, Serambi Indonesia memotret keberadaan HGU kebun sawit yang kurang memberikan manfaat untuk warga di Kabupaten Tamiang. Di sisi lain, program restorasi hutan lindung, sebuah kebijakan pengembalian fungsi hutan di Kabupaten Aceh Tamiang yang selama ini ditanami sawit ilegal, justru berjalan sukses. Seluas 1.123 hektare hutan berhasil direstorasi dengan melibatkan warga sekitar. Ada keberhasilan, ada pula tantangan dalam program restorasi ini. Berikut beberapa catatan dari hasil penelusuran tersebut, yang diturunkan dengan pendekatan Jurnalisme Solusi.
Meskipun Kabupaten Aceh Tamiang kini memiliki 100-an HGU perkebunan sawit yang dikelola swasta, tidak ada pemasukan sepeser pun Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pemerintah setempat. Kalaupun ada, melalui Pajak Bumi dan Bangunan yang jumlahnya tidak seberapa setiap tahun.
Kadis DPKAD Aceh Tamiang, Abdullah SE mengatakan, tidak ada kontribusi pemasukan untuk pendapatan asli daerah dari HGU kebun sawit. “Keberadaan puluhan ribu HGU perkebunan di Aceh Tamiang tidak memberikan pemasukan pendapatan asli daerah (PAD),” tandasnya kepada Serambi, pekan lalu.
Namun, kata Abdullah, masih ada pemasukan yang signifikan ketika HGU habis. Untuk pengurusan izin baru bisa miliaran rupiah masuk ke kas daerah. Namun, tentu butuh waktu untuk menanti hingga 25 tahun sampai perpanjangan izin baru tersebut. Selain itu, ada juga pemasukan melalui PBB Perkotaan dan Perdesaan yang dipungut Pemkab Tamiang setiap tahun. “Ditargetkan lebih dari 2 miliar rupiah per tahun dan dipungut oleh Pemkab Tamiang,” tandasnya.
Menurut penelusuran Serambi, beberapa tahun silam Pemkab Tamiang pernah berencana untuk mendapatkan PAD dari sektor perkebunan swasta. Maka dirancanglah qanun yang isinya kutipan retribusi sebesar Rp 5 per kg tandan buah segar yang dihasilkan perusahaan perkebunan. “Namun, setelah diajukan ke Jakarta, pusat kemudian membatalkan qanun tersebut, karena dianggap tidak ‘ramah’ investasi,” tandas mantan Ketua DPRK Tamiang Rusman, dalam sebuah perbincangan dengan Serambi, pekan lalu.
Sedangkan tenaga kerja yang direkrut pun, terbatas jumlahnya. Mayoritas mereka justru berasal dari luar Aceh. Sementara Pemkab Tamiang harus menguras uang miliaran rupiah setiap tahun untuk memperbaiki berbagai infrastruktur jalan, jembatan, yang sebagiannya rusak akibat lalu lintas angkutan truk pengangkut sawit.
“Dana Otsus habis untuk memperbaiki jalan. Hampir semua atau sekira 85 persen pemilik kebun tersebut orang luar Aceh. Kantor pun hampir semuanya berada di Medan, Sumatera Utara,” tandas Direktur LSM Lembahtari Sayed Zainal SH. Kini, kalaupun ada keuntungan langsung yang signifikan dirasakan petani, hanyalah melalui program restorasi yang dicanangkan pemerintah sejak 4 tahun lalu.
Kata Sayed Zainal, meskipun jumlah HGU tercatat tidak kurang dari 50, namun tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah areal yang dikuasai puluhan perusahaan swasta tersebut. Sayed menduga, sebagian perusahaan mencaplok areal di luar HGU. Beberapa perusahaan malah sudah dilaporkannya ke polisi, karena dianggap mencaplok areal di luar HGU. “PT Semadam pernah kita laporkan ke Polda pada tahun 2014, karena mencaplok areal di luar HGU,” tandasnya.
Lalu, bagaimana solusinya? Menurut Sayed Zainal, terkait PAD memang harus dibuat kembali regulasi yang memungkinkan pengutipan retribusi, tentu harus dengan persetujuan pemerintah pusat. Begitu juga dengan tenaga kerja, harus mengutamakan pekerja lokal setempat. Sedangkan terkait dengan areal yang dikuasai perusahaan, Sayid Zainal meminta diukur ulang. Dia memperkirakan, ada sekira 20 persen areal ilegal di luar HGU yang dimanfaatkan perusahaan. Lebih aneh lagi, kata Said Zainal, saat ini puluhan ribu hektare kebun berubah kepemilikan, menjadi milik asing.
“Solusinya diukur ulang, dipatok yang bermasalah. Sehingga kita tahu kebun ini di luar HGU. Ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah selama ini. Untuk mengukur ulang, tentu harus melibatkan tim independen, yang mewakili berbagai unsur,” tandas pria ini.
Namanya Wak Ino. Umurnya sudah di atas kepala enam. Tapi, pria bertubuh kekar ini menjadi teladan banyak pihak di Tenggulun, khususnya terkait kesuksesannya dalam bertani. Maklum saja, hanya dengan menanam terong, timun, genjer, kangkung, sawi, cabe, ubi, dan kacang panjang, penghasilan pria ini bisa mencapai 3-4 juta per bulan.
Seperti halnya 49 petani lain yang tergabung dalam kelompok tani Tukul Lestari, Wak Ino mendapatkan jatah satu hektare lahan restorasi. Kini, sebagian lahannya sudah ditanam tanaman keras. Ada durian, mahoni, nangka, hingga pisang. Namun, disela-sela tanaman tersebut, wak Ino menanam tanaman musiman. “Pohon durian sudah besar-besar, tapi butuh beberapa tahun lagi untuk berbuah. Untuk kebutuhan sehari-hari, saya menanam tanaman musiman,” kata Wak Ino kepada Serambi mengawali pembicaraan, di sebuah pagi awal bulan Juni seraya menyirami tanaman cabe yang sudah tumbuh sejengkal.
Dengan menggunakan sepedamotor, Wak Ino selama ini menjajakan hasil kebunnya itu ke desa-desa. Sebagian ibu rumah tangga memang sudah menjadi langganan tetapnya. Setiap kali berangkat, Wak Ino mengaku membawakan masing-masing 30 kg timun dan genjer, kangkung 50 ikat, daun ubi 40 ikat, cabe 3-4 Kg, dan beberapa kilogram terong. Biasanya, sejak pagi hari barang bawaannya itu habis diborong kaum ibu.
“Saya membawanya pakai sepedamotor setiap dua hari sekali. Ya, alhamdulillah bisa bawa pulang 250.000-300.000,” tandasnya.
Dalam sebulan, rata-rata Wak Ino bisa berpenghasilan sekitar Rp 4 juta. Saat ditanya kiat dirinya jadi petani sukses, Wak Ino cuma tertawa lebar. Kata dia, yang penting cuma kemauan bekerja keras. “Yang lain pada malas-malas. Di kelompok saya, cuma beberapa orang saja yang rajin,” timpalnya lagi.
Saat ini dia merasa kwalahan memenuhi permintaan sayur dan buah yang lumayan tinggi. Hampir tak pernah barang dagangannya itu dibawa pulang. Bahkan jika pun ada stok lebih, Wak Ino membawanya ke pasar terdekat. “Kalau tak habis, kami bawa ke pekan (pasar, red). Ada di Simpang Kiri, Tenggulun, Simpang Tiga Pucuk. Tapi, jarang saya bawa ke sana, karena di kampung saja masih kekurangan,” katanya.
Terkait benih sayur, semua dibeli di pasar. Harganya tidak terlalu mahal. Sedangkan pupuk yang dipakai jenis organik bikinan sendiri. Begitupun, pupuk kimia masih digunakan, meskipun dalam jumlah yang terbatas. “Pupuk organik dicampur dengan kimia. Namun, pupuk kimia dalam porsi yang kecil,” tandasnya.
Namun, seperti juga pekerjaan apa pun, selalu ada tantangan yang dihadapi, yakni serangan hama babi. Sebulan sebelumnya, ubi kayu milik Wak Ino habis dilahab babi hutan. Hama ini memang merepotkan para petani, apalagi sekeliling areal kebunnya masih kosong, sehingga praktis menjadi sasaran utama.
Kini, sejalan dengan kesuksesannya dalam bertani di lahan hasil restorasi, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah III Dinas Kehutanan Aceh dan Forum Konservasi Leuser (FKL) sebagai lembaga yang mendampingi petani, sepakat untuk menambah jatah lahan untuk Wak Ino.
“Kami sudah tambahkan lahan 0,5 hektare untuk Wak Ino, sehingga menjadi 1,5 hektare,” tandas staf FKL, Armiadi, pekan lalu. Keuletan sekaligus keberhasilannya menjadi pertimbangan penambahan jatah lahan. Apalagi, kata Armiadi, sebagian petani tidak produktif meskipun lahan sudah diberikan dan beberapa keterampilan dan teknik budidaya sudah diajarkan pihaknya. Sebab lahan tak dimanfaatkan optimal bermacam-macam, mulai dari kekurangan modal, lahannya jauh dari tempat tinggal, hingga tingkat kesuburan tanah yang kurang.
“Ada juga petani yang bekerja di perusahaan perkebunan, sehingga kurang maksimal menggarap lahan yang diberikan,” papar Armiadi.
Pada tahun 2007, Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) melakukan pemantauan kebun sawit ilegal di Aceh Tamiang. Saat itu, beberapa orang staf BPKEL melakukan pantauan hutan lewat udara bersama kepolisian resort Aceh Tamiang. Hasil pantauan tersebut, ditemukan sejumlah perkebunan sawit yang berada dalam hutan lindung.
Setelah pemantauan hutan itu dilakukan, BPKEL memetakan seluruh kebun sawit ilegal tersebut. Hasil pemetaan BPKEL, setidaknya 3.000 Ha hutan lindung telah berubah fungsi menjadi kebun sawit selama bertahun-tahun. BPKEL kemudian menyampaikan temuan ini kepada Pemkab Tamiang untuk mengambil langkah-langkah strategis.
Setelah melakukan pendekatan yang panjang, BPKEL berhasil meyakinkan Pemkab Tamiang agar diambil satu langkah tegas terhadap alih fungsi hutan lindung yang terjadi di Aceh Tamiang. Semua pihak saat itu setuju untuk melakukan restorasi hutan lindung yang telah berubah fungsi.
Pada tahun 2009, BPKEL melakukan penebangan perdana kebun sawit ilegal di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu. Luas kebun sawit ilegal yang ditebang oleh BPKEL pada masa itu 425 ha. Kebun sawit ilegal tersebut dikuasai oleh salah seorang pengusaha Aceh Tamiang. Dengan dukungan kepolisian, BPKEL terus mengidentifikasi kebun-kebun ilegal lainnya.
Kegiatan restorasi ini terhenti pada tahun 2012. Saat itu, Gubernur Aceh yang baru yakni Zaini Abdullah membubarkan lembaga BPKEL yang dibentuk oleh gubernur sebelumnya. Setelah lembaga pemerintah tersebut bubar, tidak ada lagi sawit ilegal yang ditebang.
Kegiatan restorasi hutan lindung di Aceh Tamiang berhenti salama hampir 2 tahun setelah pembubaran BPKEL. Tidak ada satu lembaga pun yang melanjutkan kerja restorasi hutan lindung di Tamiang saat itu. Namun, FKL berdiri pada akhir tahun 2012 membawa misi melanjutkan perlindungan KEL, yang salah satunya adalah restorasi hutan lindung di Aceh Tamiang.
Di awal tahun berdirinya FKL, negosiasi terbatas terus dilakukan untuk menggalang dukungan dari pemerintah Tamiang dan masyarakat agar kegiatan restorasi hutan lindung dapat berjalan kembali. Usaha untuk meyakinkan banyak pejabat dan masyarakat ini mendapat banyak rintangan dari orang-orang yang ingin melindungi kebun sawit ilegal agar tidak ditebang.
Pada akhir tahun 2014, Bupati Aceh Tamiang Hamdan Sati saat itu setuju untuk kembali melakukan restorasi hutan lindung di Aceh Tamiang. Hamdan menerbitkan surat keputusan untuk merestorasi lahan sawit ilegal seluas 1.071 ha di Kecamatan Tenggulun.
FKL bersama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tamiang (Dishutbun) saat itu melakukan inventarisasi batas kawasan hutan yang telah berubah fungsi. Inventarisasi ini dilakukan untuk menetapkan areal hutan lindung yang akan dipulihkan. Setelah kegiatan ini selesai, FKL dan Dishutbun Aceh Tamiang menetapkan penebangan perdana dilakukan pada September 2014.
Dalam kurun waktu 2 tahun, telah ditebang sebanyak 60.000 batang sawit atau seluas 500 ha. Tercatat, ada 11 orang pemilik kebun ilegal di hutan lindung Tenggulun yang akhirnya setuju sawitnya dibabat habis dan direstorasi. Dalam perjalanan kegiatan restorasi ini, begitu banyak dinamika birokrasi yang terjadi di Indonesia termasuk salah satunya pencabutan wewenang Dishutbun kabupaten ke Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelola Hutan (UPTD KPH) Provinsi Aceh sesuai amanat UU 23/2013.
Oleh Dinas Kehutanan Provinsi Aceh, sebagian lahan sawit ilegal ini dikerjasamakan dengan pemilik perkebunan tersebut. Pemerintah Aceh membuat kebijakan untuk melakukan pengelolaan kelapa sawit yang “telanjur” ditanam dengan skema kemitraan.
Pola kemitraan ini menuai protes dari kalangan LSM di Aceh, yang menilai kebijakan ini cacat hukum karena tidak berdasarkan amanat Undang-undang. LSM berkesimpulan bahwa pola kemitraan pengelolaan sawit ilegal bertentangan dengan UU yang berlaku. Namun, pihak DLHK Aceh punya alasan tersendiri.
Pada tahun 2015, Dinas Kehutanan Aceh memberikan hak pengelolaan hutan lindung kepada tiga kelompok tani. Total luas areal kelola kelompok tani adalah 250 hektare. Pola restorasi hutan lindung yang dikembangkan tiga poktan tersebut adalah agroforestry. Model restorasi ini dirasa sesuai dengan keinginan kelompok masyarakat yang menginginkan adanya pendapatan tambahan dari hasil mengelola hutan lindung.
Komposisi tanaman restorasi di tiga areal ini dibagi menjadi 60% tanaman keras dan 40% tanaman buah. Juga diselingi dengan tanaman semusim sebagai alternatif mendapatkan tambahan pendapatan jangka pendek. Sampai bulan Desember 2017, FKL bersama masyarakat telah membuat 30.000 bibit tanaman, dan sekitar 10.000 bibit tersebut sudah ditanam.
Saat ini restorasi hutan lindung di Tamiang berjalan sangat bagus. Hutan muda sudah mulai tumbuh di beberapa areal restorasi. Tanaman masyarakat juga banyak yang menghasilkan. Semua keberhasilan tersebut tentu didapat dengan cara yang tidak mudah.
Artikel ini telah diterbitkan di Serambi Indonesia dan diedit kembali untuk dimuat di Jaring.id