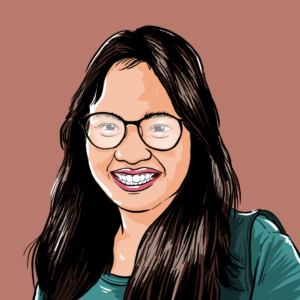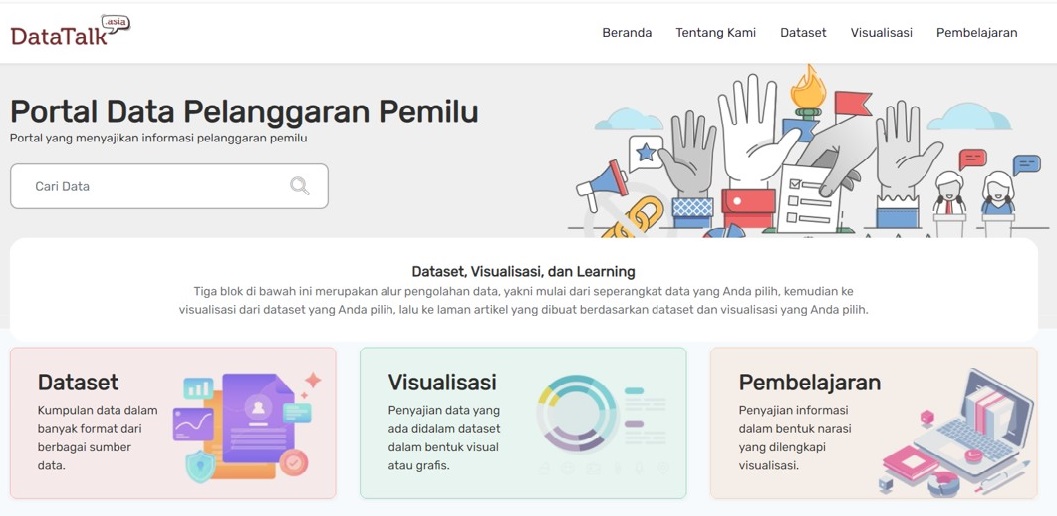
Penyelenggara pemilihan umum (pemilu) di luar Jawa bercokol di puncak daftar pengaduan terkait netralitas pada saat proses pemilihan kepala daerah 2020. Dari 270 daerah yang mengikuti pilkada serentak saat itu, penyelenggara di Sumatera Utara diketahui paling banyak diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedikitnya ada 66 kasus dari 415 aduan yang dilakukan penyelenggara di seluruh daerah. Diikuti Papua dengan 44 pengaduan dan Sulawesi Selatan dengan 25 pengaduan.
Sementara pada pemilu 2019 lalu, penyelenggara di Papua lah yang paling banyak diadukan dengan 75 pengaduan, lalu Sumatera Utara dengan 39 pengaduan dan Sumatera Barat 30 pengaduan.
Hal ini didapatkan Jaring.id setelah mengolah pelbagai data DKPP dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tersedia di datatalk.asia. Situs yang dikembangkan secara kolaboratif oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama Sinar Project Malaysia dan Philippine Center for Investigative Journalism (PCIJ) ini memuat data terbuka pemilu di Asia Tenggara, khususnya data pemilih, hasil dan pelanggaran pemilu di Malaysia, Filipina dan Indonesia.
Data yang tersedia dimuat dalam pelbagai format yang mudah diolah, seperti Comma Separated Values (CSV) dan JavaScript Object Notation (Json). Dengan begitu, pengguna dapat langsung menganalisa maupun mengonversi dataset ke dalam bentuk infografis lewat fitur yang sudah tersedia di datatalk.asia.
Dalam data yang diolah Jaring.id dari situs tersebut juga diketahui bahwa pelanggaran berupa netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pilkada 2020 paling banyak terjadi di Sulawesi. Dari 2300 laporan dugaan pelanggaran, terdapat sekitar 282 aduan yang dilayangkan terhadap pegawai pemerintah. Sedangkan dugaan penyalahgunaan wewenang pejabat daerah dan perangkat desa paling banyak terjadi di Papua dan Maluku.
Kondisi ini berbeda dengan yang terjadi di Pulau Jawa. Bila di luar Jawa dilakukan oleh penyelenggara maupun ASN, maka kasus dugaan pelanggaran pemilu di Jawa paling banyak dilakukan oleh peserta pemilu, antara lain calon anggota legislatif, calon presiden, partai politik dan tim sukses. Dari 12,489 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 di Pulau Jawa, sekitar 92 persen atau setara 11.495 laporan berkaitan dengan kontestan.
Salah satu kasus yang sempat mencuat ialah ketika DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemecatan kepada tiga anggota Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) di Nias Selatan pada 2020 lalu. Mereka ialah Hilimegai Paolianus Gulo, Amandraya Umbuzisokhi Giawa dan Huruna Juferman. Ketiganya terbukti masih berstatus pengurus di DPC Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Nias Selatan ketika menjadi PPK. Sementara lima anggota KPU Nias Selatan yang bertanggung jawab dalam rekrutmen mendapat sanksi peringatan dari DKPP karena dianggap tak netral dalam proses pengerahan penyelenggara adhoc.
“Teradu satu sampai lima telah melakukan kecurangan, tidak netral, tidak adil, dan sewenang-wenang dalam memilih dan menetapkan jajaran PPK,” bunyi kutipan putusan sidang perkara nomor 78-PKE-DKPP/VIII/2020.
Dalam kasus ini, sebetulnya Bawaslu Nias Selatan sudah memperingatkan KPU perihal status ketiga PPK lewat surat rekomendasi. Selain berstatus anggota partai, ketiganya menjadi bagian dalam tim sukses salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Namun saat itu KPU Nias Selatan tak menjalankan rekomendasi Bawaslu tersebut.
Peneliti pemilu dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Pratama menyebut setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan penyelenggara maupun ASN rentan terlibat dalam pelanggaran pemilu. Pertama ialah luasnya daerah pemilihan dan sistem pemilihan proporsional terbuka. Sistem yang mulai berlaku pada 2009 ini menggunakan suara terbanyak untuk menentukan calon legislator yang duduk parlemen.
Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) menunjukkan bahwa penerapan sistem proporsional terbuka melambungkan ongkos politik. Pengeluaran caleg pada Pemilu DPR 2014, misalnya, berkisar Rp 1,18 sampai 4,6 miliar. Sedangkan untuk DPRD Rp 481 juta sampai 1,55 miliar.
Dengan ongkos tersebut, menurut Heroik, para kontestan berusaha meraup suara dengan mencari jalan pintas melalui orang-orang berpengaruh, antara lain penyelenggara pemilu maupun pemerintah daerah. “Dua-duanya bisa berpengaruh sehingga perlu dilihat bagaimana daerah pemilihan dan jumlah calonnya di masing-masing daerah,” kata Heroik ketika dihubungi pada Senin, 12 Juli 2022.
Dalam riset berjudul Malpraktik dan Korupsi Pemilu di Indonesia: Analisis terhadap Proses Perhitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu 2019 yang terbit di Jurnal Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara paling banyak terjadi di tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara. Sedangkan aduan paling banyak terjadi pada tahap rekapitulasi tingkat kecamatan. Dengan begitu, penyelenggara rekapitulasi suara di tingkat kecamatan lebih rawan melakukan malpraktik pemilu.
“Perlu dua syarat malpraktik pemilu di tingkat kecamatan, adanya keinginan saksi partai yang ingin mengubah perolehan suara dan persetujuan PPS atau PPK yang bersekongkol dengan panitia pengawas kecamatan,” kata Heroik.
Oleh sebab itu, Heroik menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menggunakan sistem rekapitulasi elektronik (e-recap) guna meminimalisir terjadinya malpraktik pemilu. Sampai saat ini, pemanfaatkan teknologi digital itu belum dapat dilakukan karena terhalang regulasi. “Tapi jangan sampai pemanfaatan teknologi menutup akses masyarakat mengawasi rekapitulasi suara,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DKPP, Didik Supriyanto menilai tingginya pelanggaran yang dilakukan penyelenggara di sejumlah daerah merupakan imbas dari sistem pemilihan yang melibatkan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam proses ini, partai yang memiliki pengaruh besar dapat menentukan siapa anggota KPU maupun Bawaslu terpilih. Hal ini, menurut Didik, tak sesuai dengan status penyelenggara pemilu sebagai lembaga independen dan mandiri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. “Ini semacam ucapan terima kasih karena sudah memilih saya, maka tim seleksi yang dipilih akan mewakil kelompok-kelompok tertentu, termasuk afiliasi partai politik tertentu,” kata Didik saat dihubungi pada Senin, 12 Juli 2021.
Selain itu, minimnya pengawasan publik terhadap proses pemilu di daerah juga berpengaruh terhadap pelanggaran. Padahal partisipasi warga mengawasi pemilu sangat penting dilakukan. “Adanya pengawas-pengawas yang dibentuk penyelenggara, justru membuat partai dan masyarakat berpikir pengawasan hanya tugas Bawaslu, bukan tugas masyarakat luas. Ini membuat laporan dari pelanggaran dari masyarakat minim,” katanya.
Senada dengan Didik, Direktur Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menyebut bahwa mekanisme pengawasan pemilu saat ini belum efektif. Baik penyelenggara maupun pemerintah tidak punya sumber daya manusia dan anggaran yang memadai guna melakukan pengawasan. Hal ini berimbas pada pelanggaran berulang dari pemilu ke pemilu. “Seharusnya masyarakat diberikan pendidikan pemilih agar ikut mengawasi jalannya pemilu dan bagaimana memilih calon bukan karena uang atau iming-imingnya,” kata Bahtiar.
Dalam hal pelanggaran netralitas ASN dan pejabat daerah, Bahtiar menilai sudah banyak aturan yang dibuat sebagai pedoman etik pejabat dan ASN. Hanya saja, menurutnya, aparatur pemerintah yang terbukti melanggar etik dalam pemilu tak serta merta bisa dihukum. Dalam pelanggaran etik, keputusan Komite Etik hanya sampai pada tahap memberikan rekomendasi sanksi. Sementara eksekusi terhadap rekomendasi tersebut sangat bergantung pada keinginan kepala daerah. “Tak jarang kepala-kepala dinas terancam jabatannya atau diasingkan jika dianggap tak berkontribusi memenangkan kepala atau wakil kepala daerah,” katanya.
Bahtiar berharap, pelbagai pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan penyelenggara, kontestan maupun ASN tidak berulang pada pemilihan umum 2024 mendatang. Dengan mamanfaatkan data pemilihan sebelumnya, penyelenggara harusnya mampu meminimalisir pelanggaran serupa. “Agar tidak terulang (pelanggaran) masih banyak hal yang bisa kita lakukan menjelang 2024 seperti pendidikan pemilih, pendidikan pengawas, pendidikan penyelenggaraan. Kemudian mendidik masyarakat untuk mengawasi pemilu dan memilih secara cerdas. Itu pekerjaan berat yang harus dilakukan semua pihak,” tutupnya. (Debora B. Sinambela)