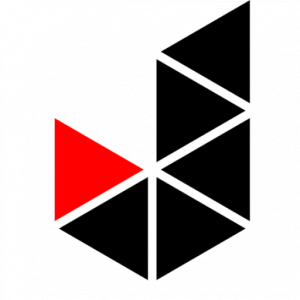JAKARTA, JARING – Sungai di desa Buket Linteung, Langkahan, Aceh Utara, telah lama mati. Padahal, sungai ini dulu begitu hidup, air mengalir dari sumbernya dengan lancar. Para perempuan menggunakan sungai ini untuk berbagai keperluan rumah tangga.
Namun, sejak beberapa tahun terakhir, sungai itu tak lagi mengalir. Air yang ada di sana bisa pergi ke mana-mana, hanya tergenang. “Sungai itu dulu hidup. Pembangunan bendungan membuat sungai ini tidak nyambung dengan asalnya,” kata Siti Maimunah dari Sajogyo Institute di hadapan peserta Fellowship Investigasi untuk Jurnalis: Jurnalisme Investigasi untuk Pengurangan Deforestasi, yang diselengarakan JARING di Jakarta, Senin (1/8).
Bukan cuma itu terputus dengan daerah asal, limbah dari perusahaan-perusahaan tambang di sekitarnya juga masuk ke sungai tersebut, membentuk sedimentasi di sana. Akibatnya ketika hujan lebat, banjir akan bertahan hingga berhari-hari.
Masalahnya, kata Maimunah, hanya perempuan yang menggunakan sungai tersebut. “Laki-laki bisa menggunakan sumber air dalam perjalanan mereka dari rumah ke tempat bekerjanya,” katanya.
Yang terjadi kemudian, perempuan mengalami gatal-gatal pada vagina mereka. “Kondisi ini seperti bukan masalah. Mereka biasa menggunakan balsem atau minyak kayu putih untuk meredakan gatal-gatal tersebut,” tutur Maimunah.
Gambaran di atas adalah dampak dari eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) terhadap kaum perempuan. Perempuan menjadi korban yang paling menderita. Namun, media jarang tertarik untuk mengangkat perspektif kaum perempuan ketika menulis soal eksploitasi SDA.
Ada banyak contoh eksploitasi SDA yang mengabaikan hak-hak perempuan. Maimunah bercerita tentang Desa Perigi di Sumatera Selatan. Desa ini memiliki lahan rawa gambut yang luas. Di lahan ini, tumbuh purun (pandan). Oleh para perempuan Perigi, purun-purun ini dianyam, menjadi hasil kerajinan. Kini, di desa itu akan dicetak sawah seluas 1000 ha. “Bayangkan apa yang terjadi jika pencetakan sawah dilakukan dengan revolusi hijau,” kata Maimunah.
Cerita lain tentang Aleta Baun, perempuan dari Pulau Timor. Ia mengorganisir dua kampung untuk menolak tambang marmer. Mengapa? Karena ia yang pernah menjadi pekerja LSM dan kerap memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi menemukan para perempuan di kampungnya terus-menerus sakit. Ternyata, limbah tambang marmer itulah penyebabnya.
Tidak Jadi Rujukan
Cerita-cerita tentang pengalaman perempuan dan perspektif mereka, sayangnya, jarang ditulis media massa. “Bahkan tidak pernah menjadi rujukan. Sehingga seolah-olah kita membicarakan perempuan, tapi sebenarnya mereka tidak pernah benar-benar diletakkan sebagai narasumber yang penting untuk ditulis,” katanya.
Menjawab pertanyaan seorang peserta tentang bagaimana jika para perempuan ini yang justru terlibat dalam kegiatan tambang ilegal, Maimunah mengatakan media harus lebih kritis melihat aspek ilegal dan legal. “Ilegal biasanya terkait pada persoalan adanya izin,” katanya.
Perempuan dalam konteks tambang ilegal itu sesungguhnya menghadapi kondisi yang berlapis-lapis. “Penting untuk meletakkan saat kita melihat perempuan itu bekerja dalam ruang-ruang ilegal, di mana setiap orang sebenarnya mendapatkan keuntungan,” katanya.
Di saat yang bersamaan, justru perempuanlah yang paling terkena masalah, kata Maimunah. Banyak tambang emas rakyat yang masih menggunakan merkuri. Saat bekerja, mereka terpapar racun merkuri. “Tubuhnya secara reproduksi juga terpapar racun saat membakar merkuri untuk memisahkan bijih-bijih emas. Di udara, racun merkuri lebih mudah masuk ke dalam tubuh, terutama tubuh perempuan yang hamil,” tutur Maimunah.
Ia mengatakan media justru seharusnya membantu untuk melihat bagaimana sebenarnya para perempuan itu dalam sistem ilegal. “Ini pentingnya tulisan kita karena kita menuturkan bagaimana sebenarnya persoalan itu bukan cuma konteks ilegal, tapi juga bagaimana risikonya terhadap kaum perempuan dan keluarganya,” katanya.