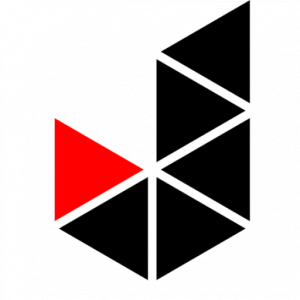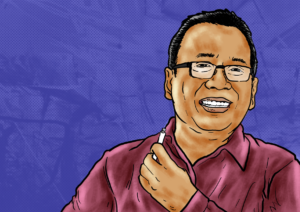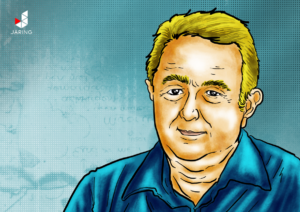Pemilu 2024 disertai berbagai keriuhan. Mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang dinilai melanggar kode etik, para cukong di belakang kandidat, hingga kampanye yang penuh gimmick. Namun, ada satu hal yang tak banyak dibicarakan dan telah kami obrolkan bersama Max Lane, Indonesianis asal Australia dalam Petik Dua sebelumnya: kekosongan ideologi
Dalam edisi kali ini, Jaring.id bersama empat Je-Jaring yakni Alisa Qottrun Nada Munawaroh, Debora Blandina Sinambela, Rio Nanto, dan Vicky Kurniawan mewawancarai Ruth Indiah Rahayu. Dia adalah aktivis dan peneliti Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif (Inkrispena) — lembaga riset yang memfokuskan pada kajian tentang krisis dan perlindungan sosial transformatif bagi rakyat pekerja. Ruth juga menjadi peneliti di IndoPRogress Institute for Social Research and Education.
Berikut petikan wawancara selama 1 jam 40 menit yang kami lakukan pada . Versi lengkapnya, bakal ditayangkan di kanal YouTube Jaring.id.
Melihat dinamika yang terjadi belakangan ini di Indonesia, apakah pemilu 2024 bakal berdampak bagi perempuan dan gerakan perempuan?
Kita terlebih dahulu harus memahami apa itu pemilu dan sejarah pemilu di Indonesia. Pemilu 2024 hanyalah serentetan atau cerminan dari perubahan adanya pemilu sejak reformasi.
Reformasi hadir karena adanya gerakan sosial secara keseluruhan. Semangat reformasi menginginkan agar negara demokrasi kembali ke keadaan yang sebenarnya sehingga masyarakat ikut serta mengelola negara. Namun, semangat itu gagal diciptakan oleh Reformasi 1998.
Proses reformasi juga mereduksi ekonomi-politik menjadi politik saja. Politik direduksi hanya menjadi pemilu yang prosedural, pemilu langsung, seperti saat sekarang ini. Hanya dalam pemilihan legislatif, eksekutif, dan kepala daerah saja.
Jika bicara proses pemilu, yang kemudian terjadi hanya siapa yang dapat menguasai gelanggang kepemiluan saja? Di Indonesia, pemilu erat kaitannya dengan pemilu uang akibat campur tangan rezim neoliberalisme. Sehingga partisipasi politik selalu dimediasi oleh uang. Warga negara, terutama yang mengalami eksklusi sosial, tidak memiliki cukup uang, tidak punya relasi atau koneksi dengan para oligarki politik tidak akan tergabung di dalam kontestasi kepemiluan.
Contoh konkritnya saja dapat dilihat pemenuhan suara 30 persen perempuan. Siapa perempuan yang kemudian berhasil menjadi anggota parlemen di daerah atau pusat?. Kebanyakan orang yang mempunyai koneksi dengan oligarki politik, atau bagian dari keluarga elit-elit politik, atau yang punya duit.
Kebanyakan perempuan pasti tidak memiliki privilese itu. Sehingga akan sulit ikut kontestasi pemilu. Kuota 30 persen perempuan kemudian menjadi masalah. Penyebab awalnya akibat reduksi-reduksi politik tadi.
Sejak pemilu 2004 hingga saat ini, partai politik tidak pernah mendidik perempuan, tidak pula membangun ormas. Sehingga, partai politik hanya mengambil perempuan-perempuan yang berasal dari LSM, NGO perempuan, atau dari serikat-serikat. Kemudian, belum tentu mereka akan dijadikan ujung tombak. Sehingga tidak aneh jika keterwakilan perempuan 30 persen itu masih susah terpenuhi.
Jadi yang akhirnya menguasai kepemiluan ini, atas nama proses demokrasi, adalah keluarga-keluarga elit politik yang punya partai dan tentu punya uang. Di luar itu, jangan harap kita bisa masuk ke ranah kepemiluan ini. Itu yang terjadi.
Hal lain yang semakin akut adalah kampanye yang semakin penuh gimmick dan tanpa gagasan substantif. Ini sebetulnya fenomena apa?
Saya perlu cerita ke belakang. Dulu, pada pemilu 1955, partai-partai membangun relasi sosial dan politik dengan masyarakat. PNI, NU, PKI, Masyumi, dan Partai Sosialis rata-rata memiliki “kaki” di tengah masyarakat. Mereka inilah yang bergerak di bawah, ke kampung-kampung ke desa-desa dan sebagainya.
Ini yang kemudian disebut politik warga, bukan politik langsung. Semua literasi politik diajarkan di dalamnya. Dari sana, partai-partai punya kader-kader yang sudah diberikan literasi tentang politik. Nantinya mereka yang akan dipilih menjadi caleg-caleg dari partai tersebut.
Jika sudah seperti itu, apakah tetap dibutuhkan spanduk atau banner-banner politik bertuliskan pilihlah saya yang menyampah itu? Tentu tidak. Sekarang, kita bahkan tidak pernah mengenal siapa caleg itu, sehingga salah satu cara adalah menunjukkan dirinya di papan-papan iklan itu.
Partai politik tidak lagi memiliki kaki di tengah-tengah masyarakat. Pada 2004, Capres-Cawapres ini saking tidak tahunya harus melakukan program apa, yang terjadi mereka mengumpulkan para ahli. Para pakar ini yang nantinya menjadi tim sukses dan membuat program ekonomi. Padahal program itu tidak mencerminkan masalah yang ada di masyarakat.
Hari ini gilanya, orang nyaleg sebagai job seeker. Mereka tidak punya visi misi, namun ingin mengejar pendapatan saja dari jabatan itu. Hal itu lahir karena adanya kontestasi di dalam pasar kerja yang bernama pemilu. Partai politik ruangnya, kemudian job seeker-nya keluarga, atau siapapun yang memiliki koneksi. Partai politik sekarang hanyalah partai politik warisan massa yang mengambang. Tidak memiliki ideologi sama sekali.
Debora: Apakah upaya membuat pemilu murah akan berefek pada munculnya pemimpin yang kita harapkan? Lalu, apakah ada kemungkinan bahwa sistem pemilu tertutup membuat partai mempunyai ideologi lagi?
Saya mungkin agak beda dengan pandangan kawan-kawan bahwa otak atik prosedural akan berhubungan dengan substansi. Banyak energi kawan-kawan sejak 2004, bahkan sebelum 2004, untuk (mengusahakan) perubahan undang-undang politik. Tidak sempat mempersoalkan substansi seperti kesetaraan ekonomi dan sebagainya.
Gerakan itu harus dievaluasi kembali. Percuma kita memperjuangkan prosedur-prosedur yang memungkinkan keterwakilan perempuan naik menjadi 30 persen atau lebih, tetapi yang mengisi (legislatif) yang punya uang. Problemnya menurut saya adalah partai politik yang bukan betul-betul membangun proses demokrasi. Kita kembali kepada model kepartaian seperti sebelum tahun 65, dengan ormas yang bekerja di bawah. Ini kan tanpa modal besar.
Neoliberalisme ini kecenderungannya mendorong kepemiluan dimediasi oleh uang, bukan oleh relasi dengan massa. Semua gerakan yang ingin membangun relasi dengan massa dipotong. Ketika pemilu ini dimediasi oleh uang, mereka memang nanti akan terjadi proses sirkulasi uang. Yang saya tidak tahu, siapa yang akan menerima keuntungan atau nilai lebih dari proses-proses kepemiluan ini. Uang ini kan berputar, bersirkulasi. Jadi memang ada rezim ekonomi-politik yang membiarkan pemilu ini mahal atau dimediasi oleh uang. Ini yang harus dilawan.
Salah satu contoh, beberapa tahun lalu saya masih ikut (membuat) strategi teman-teman caleg perempuan menang. Jangan caleg nasional langsung, tapi ambil caleg level kabupaten/kota. Siapa yang banyak menang? Bidan. Karena mereka banyak berelasi dengan perempuan. Yang kedua, mereka yang turun terjun mengurusi korban poligami, korban kekerasan seksual, kartu kelahiran, atau tidak punya kartu-kartu macam-macam, termasuk BPJS.
Kembali kepada konsep saya, yang bisa membuat pemilu (berbiaya) murah adalah membangun relasi dengan masyarakat. Membangun relasi nggak sekedar membagi kartu anggota, kartu caleg. Membangun adalah memecahkan masalah yang dirasa oleh masyarakat.
Itu berhasil, untuk level bawah (DPRD tingkat II). Untuk nasional saya belum mampu karena masih dimonopoli para perempuan yang punya kaitan dengan oligarki politik.
Jadi, saya bisa membantah bahwa problem-nya bukan di prosedur pemilu tertutup atau terbuka, tetapi bagaimana membangun kembali relasi dengan massa.
Saya tidak percaya bahwa perbaikan prosedur sebagai satu-satunya cara membuka pintu menuju demokrasi yang substansial.
Rio: Apakah benar bahwa partai-partai kita tidak punya ideologi atau ideologi-ideologi partai tunduk pada kepentingan oligarki? Lalu bagaimana preferensi generasi milenial untuk pemilu 2024?
Saya tidak terlalu suka dengan kategori-kategori gen Z dan lain-lain. Mereka semua adalah kaum muda. Mereka, sesuai dengan perkembangan kemanusiaannya, adalah generasi yang labil. Kita tidak tahu preferensi politiknya akan memilih siapa. Labil dalam arti menjadi swing voters karena tidak tahu memilih itu dasarnya apa.
Kedua, generasi milenial atau gen Z ini berkembang dalam era-era digital. Saya termasuk yang mengatakan bahwa digital itu memang membentuk atau merupakan sebuah realitas, tetapi bukan realitas yang riil. Realitas yang riil tetap ada di dalam relasi sosial. Sementara digital itu realitas yang dimediasi oleh teknologi.
Nah, kawan-kawan milenial atau gen Z atau apapun, mereka dibesarkan, didewasakan dalam era digital ini. Mereka generasi yang dibesarkan untuk menyukai idola. Maka kesadaran tentang sesuatu yang menjadi pilihannya, dasarnya adalah idol.
Namanya saja idol, dibentuk oleh kesukaan, bukan oleh landasan ideologi dan politik. Idol ini sebuah proses marketing untuk mengagregasi kesukaan orang, mengarahkan kesukaan atas sesuatu yang merupakan sebuah trend dan bisa berubah-ubah.
Dalam konteks capres, ada capres-capres yang membaca trend bahwa anak muda menyukai idol. Supaya mereka dipilih, yang dikampanyekan adalah idolitas ini, ketimbang bagaimana mengantar generasi muda supaya punya pekerjaan yang baik, supaya bisa punya rumah. Jaminan masa depan ini tidak pernah diberikan oleh semua capres.
Tim kampanye yang mampu menangkap ini memakai avatar. Itu bagian dari tanda-tanda idolisasi. Memang yang menonjol capres nomor dua dalam menciptakan idolitas. Dulu di Amerika, saya pikir sekarang hampir di seluruh dunia begitu, Trump juga menciptakan dirinya sebagai idol yang mewakili emosi tertentu.
Seorang penulis perempuan bernama Martha Nussbaum menulis buku yang cukup bagus tentang political emotion. Dia berpendapat bahwa pada akhirnya paradoks politik di masa modern atau late capitalism adalah (kecenderungan) pendayagunaan political emotion, daripada ideologi dan politik.
Political emotion ini sebenarnya membangun sentimen. Trump membangun sentimen sebagai orang Amerika yang besar. Begitu juga di India, mereka membentuk political emotion dengan Hindu. Agama lain kemudian menjadi minoritas.
Di Indonesia juga. Semua coba membangun sentimen-sentimen atau political emotion untuk menjangkau massa-massa tertentu. Di Indonesia, konyolnya, politik identitas yang berdasarkan agama itu yang lebih banyak dipakai untuk membangun political emotion tadi.
Kembali ke kaum muda. Mereka ini yang dibangun political emotion-nya adalah (melalui) idolitas tadi.
Alisa: Lalu, bagaimana kiat agar pemilih muda memilih secara bijak pada pemilu 2024 di tengah konten kampanye di sosial media yang penuh bias?
Banyak orang ngomong soal Gen Z, preferensi politik Gen Z, ingin meraih Gen Z, tetapi tidak pernah bertanggung jawab membangun gerakan politik, penyadaran politik buat kaum muda. Lalu apa rujukan mereka (orang muda)? idolitas lagi.
Sebetulnya, orang muda ini akan senang diajak “meneliti”. Mereka punya kemampuan mengoperasikan sarana-sarana digital. Ini pengalaman pribadi saya dengan beberapa anak muda. Yuk, kita search caleg di daerahmu, tapi kita arahkan bagaimana metodenya. Mereka senang dan hasilnya luar biasa. Intinya, mereka butuh wadah untuk membimbing (soal) metode, sehingga ketika mencoblos mereka yakin.
Tapi ini tidak ada. Mungkin ada, tapi (skala) kecil. Kita tidak adil terhadap anak muda. Sekarang ini, tiba-tiba milenial dan gen Z dikomodifikasikan secara politik. Mereka ingin meraih konstituen, tapi tidak bertanggung jawab dalam pendidikan politik.
Kaum muda ini akan mudah kalau mereka diresahkan dengan masa depan. Cara menguliknya kan situ dulu, baru mereka akan mudah dikumpulkan, diberikan pendidikan politik. Kita buat yang namanya ruang publik untuk diskusi. Selama ini ruang publik untuk mendiskusikan politik, khususnya kepemiluan, hanya (ada) menjelang pemilu dan sudah di-setting, diarahkan.
Ruang publik itu harusnya bebas mendiskusikan siapa kandidat yang tepat, yang baik kriterianya. Itu kan harusnya bukan lima tahun sekali menjelang pemilu. Sepanjang waktu ruang publik ini harus dibangun, termasuk dengan teman-teman muda. Mereka diajak berpikir,
mendiskusikan kualifikasi kepemimpinan yang menjawab problem ekonomi-politik.
Vicky: Apakah lemahnya punishment KPU menjadi sebab partai tidak memenuhi keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen? Bagaimana cara agar partai-partai kecil seperti Partai Hijau bisa mengalahkan partai-partai yang sudah mapan dan tidak jelas ideologinya?
Soal keterwakilan perempuan, saya kira sudah ada mekanisme punishment di KPU untuk partai yang tidak memenuhi kuota. Tapi, ketika sorotan, desakan, atau pressure dari gerakan perempuan lemah soal keterwakilan, partai-partai seperti memenuhi prosedur saja.
Saya lihat gairah (memperjuangkan) 30 persen kuota perempuan sekarang juga longgar. PKS yang menarik, karena punya mekanisme seleksi pengkaderan perempuan mulai dari bawah, sementara partai lain tidak konsisten
Sekarang hampir sudah jelas, (caleg) perempuan yang bakal menang adalah kerabat atau koneksi oligarki politik. Di pusat ini ada namanya Kaukus Parlemen Perempuan dan Kaukus Politik Perempuan. Dua-duanya dipimpin anggota legislatif yang merupakan keluarga pemilik partai.
Partai Buruh, Partai Prima, Partai Hijau dibangun oleh gerakan-gerakan sosial, tapi semua selalu tidak memenuhi persyaratan prosedural. Bagaimana supaya mereka bisa memenuhi persyaratan prosedural? Sebenarnya ini sudah dipikirkan sejak 2014. Beberapa kampanye dilakukan, judicial review ke MK, dan lain-lain, tapi memang mentok.
Parliamentary threshold itu menjadi masalah besar. Mungkin harus ada strategi alternatif agar partai-partai kecil ini tetap eksis. Waktu itu strateginya adalah kolaborasi. Tapi ini persoalan juga, kalau kolaborasi menurut model Indonesia kan kolaborasi dengan parpol. Parpol mana yang akan diajak berkolaborasi? Kalau dipilih-pilih sebenarnya enggak ada parpol yang pas. Kolaborasi di Indonesia agak beda dengan di Amerika. Di sana kolaborasinya melibatkan elemen-elemen gerakan sosial yang kuat. Mereka berkolaborasi misalnya, dengan partai demokrat ketika pemilu. Sesudah itu, mereka menempatkan diri sebagai kelompok-kelompok watchdog, mengawasi kandidat-kandidat mereka yang menang. Nah, di Indonesia itu nggak bisa terjadi. Pernah dicoba (dan) nggak bisa.
Ini juga soal hitung-hitungan politik. Partai besar, kekuatan politiknya besar. Sementara partai kecil, ketika mencoba masuk ke kepemiluan, tidak punya dukungan gerakan sosial yang kuat. Gerakan sosial yang ada selalu merasa imparsial. Seharusnya NGO itu ikut mendorong, mendukung partai-partai kecil. Menurut saya, ini cara berpolitik yang tidak benar. Banyak NGO masih meyakini mereka imparsial, tapi beberapa individunya bermain politik. Inilah inkonsistensi di kalangan gerakan yang menurut saya memberikan andil kegagalan-kegagalan partai kecil yang dibangun dari bawah.