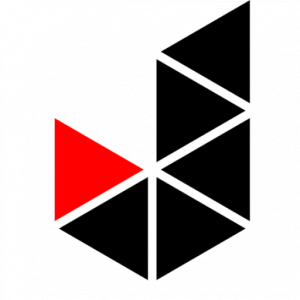Militer masih berkuasa di Thailand hingga hari ini. Mimpi mengembalikan militer ke barak dan mendudukkan supremasi sipil masih jauh panggang dari api. Namun kekerasan dan serangan terhadap jurnalis menurun drastis pascapemilu 2019.
Pravit Rojanaphruk, jurnalis Thailand yang pernah diciduk tentara dua kali pascakudeta militer tahun 2014, menyebut bahwa kini tidak ada lagi penangkapan dan penahanan semena-mena kepada jurnalis seperti yang terjadi pada dirinya di masa lalu hanya karena mengkritik rezim. Hari ini, jurnalis bebas melancarkan kritik kepada rezim yang berkuasa tanpa takut diculik atau dipenjara.
Namun, tetap ada yang tak boleh dikritik di Thailand, yakni kekuasaan monarki atau kerajaan. Atas hal ini, media massa di Thailand, terutama media mainstream, memilih melakukan self-censorship—sebuah praktik yang mengebiri kebebasan pers.
Pravit pernah ditahan pada Mei 2014, pascakudeta militer, gara-gara tulisan kritisnya terhadap junta. Ia kemudian dilepas dan ditahan lagi pada September 2015. Ia dibawa ke pangkalan militer dengan mata tertutup. Dua hari kemudian ia dibebaskan tanpa tuduhan, namun pejabat militer mengancam akan membekukan rekening banknya jika dia terus mengkritik rezim. Sebagai syarat pembebasan, ia dipaksa menandatangani formulir yang menyatakan bahwa ia tidak akan terlibat lagi dalam kegiatan anti-junta.
Beberapa hari setelah pembebasannya, otoritas The Nation, tempat Pravit bekerja selama 23 tahun, memintanya mengundurkan diri untuk menghindari surat kabar tersebut menghadapi tekanan pemerintah. Kini Pravit adalah kolumnis dan penulis senior untuk Khaosod English, dan terus menulis dengan nada kritis, terutama terkait tindakan keras rezim militer terhadap sentimen anti-kerajaan. Di bawah Undang-Undang Lese Majeste, kritik terhadap keluarga kerajaan bisa dijatuhi hukuman 3-15 tahun penjara.
Senin, 24 Oktober 2022, wartawan Jaring.id, Fransisca Ria Susanti, Abdus Somad, dan Reka Kajaksana mewawancarai Pravit melalui zoom untuk membincang situasi politik terakhir di Thailand, kondisi jurnalis, dan kebebasan pers. Berikut petikan wawancara dengan peraih Penghargaan Kebebasan Pers Internasional 2017 dari Committee to Protect Journalist (CPJ).
Bagaimana situasi politik Thailand saat ini, pascakeputusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Prayut Chan-O-Cha menjabat sebagai perdana menteri hingga 2025 jika ia terpilih kembali?
Move Forward Party, partai oposisi terbesar kedua di Thailand mengajak orang-orang untuk menggelar referendum di hari pelaksanaan pemilu. Mereka menuntut konstitusi baru, salah satunya anggota Senat tidak boleh berasal dari mantan junta militer. Namun, kalaupun tuntutan ini berhasil, butuh waktu lama untuk membikin draft konstitusi baru tersebut. Sehingga Prayut tetap bisa memilih anggota senat, dan senat akan memilih dia lagi sebagai perdana menteri. Ini seperti pertandingan tinju. Di satu sisi, saya harus mematuhi aturan, tapi di sisi lain, pihak lain bisa memukul di bawah perut.
Namun Move Forward Party tetap bisa menjadi opsi, terutama di kalangan anak muda. Mereka berani meneriakkan reformasi militer, reformasi di banyak aspek, bahkan reformasi monarki. Mereka sangat menginginkan reformasi terhadap UU Lese Majeste. Sementara Pheu Thai Party, partai oposisi terbesar pertama, tidak cukup jelas mengatakan hal ini.
Sementara Democrat Party beberapa pekan lalu mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan Move Forward Party karena kerap mengkritisi monarki. Partai Bhumjaithai, partai yang populer karena mendorong legalisasi marijuana di Thailand, juga mengatakan bahwa mereka tidak akan bekerjasama dengan Move Forward Party setelah pemilu karena sikap partai terhadap isu monarki.
Jadi, meskipun Move Forward Party saat ini sangat populer, tapi mereka tetap akan sulit membentuk pemerintahan, sekalipun mereka memperoleh kemenangan besar untuk meraih kursi parlemen nanti.
Apa isu yang dibawa oleh partai-partai politik jelang pemilu?
Salah satu isu pemilu ke depan adalah apakah kau menentang atau mendukung legalisasi ganja. Di kalangan koalisi partai pemerintah tidak semuanya setuju dengan langkah Bhumjaithai. Sementara banyak partai oposisi yang juga menentang. Tapi Bhumjaithai cukup populer dan mendapatkan banyak dukungan.
Di semua kafe di Thailand sekarang bebas menjual mariyuana. Banyak orang tua mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya. Tapi yang lain berpikir bahwa ini baik untuk ekonomi, mengundang banyak wisatawan.
Bagaimana dengan kebebasan pers?
Kondisi kebebasan pers setelah pemilu 2019 mulai membaik. Periode di bawah Prayut, yang bukan pemimpin dari junta, lebih bisa menolerir kritik. Tidak lagi terjadi penghilangan maupun penangkapan semena-mena, seperti yang terjadi dua kali pada saya di masa lalu. Dalam hal ini, memang terjadi perbaikan.
Problem yang sekarang masih berlanjut adalah diskusi apapun tentang reformasi monarki masih tabu dan pers melakukan sensor atau reporter atau editornya sendiri yang melakukan sensor diri. Jadi itu masalahnya. Pers kini bebas mengkritik militer apapun, dan bahkan mengecam Prayut, dan tak ada konsekuensi. Tapi monarki tetap tabu. Terutama oleh media mainstream. Saya sangat kecewa dengan media.
Beberapa tahun lalu saya meminta kepada Thai Journalist Association (TJA), asosiasi jurnalis terbesar di Thailand, untuk menuntut atau setidaknya mengakui bahwa UU Lese Majeste dan tindakan self-censorship media atau segala sikap berlebihan dalam menghadapi kritik terhadap monarki adalah merugikan terhadap kebebasan pers di Thailand.
Lalu apa respons mereka?
Mereka bungkam. Mereka berpura-pura seolah tidak ada apa-apa. Sangat memalukan. Saya bahkan menulis artikel yang saya juga taruh di Twitter, menuliskan bahwa saya telah menghubungi mereka. Saya bilang, jika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah, setidaknya kita punya tugas untuk menjelaskan ke publik betapa problematikanya masalah ini. Pun kalau mereka tidak mau melakukannya, misalnya anggota board tidak nyaman mengatakan perihal reformasi monarki, tapi setidaknya mereka bisa mengorganisir forum. Undang para akademisi dan diskusikan tentang UU Lese Majeste. Tapi ini pun tidak mau mereka lakukan. Padahal ini mudah dilakukan. Bikin forum diskusi di kampus tentang hal ini, kemudian bikin beritanya.
Saya pernah membaca buku. Sebuah buku tentang Korea Utara. Menceritakan tentang perjumpaan mantan sekretaris negara Amerika Serikat Madeleine Albright dengan Kim Jong-il, dan Jong-il mengekspresikan kekagumannya pada monarki Thailand. Ia bilang, “Di masa depan, kami harus belajar bagaimana menjalin hubungan dengan dengan rakyat, seperti monarki Thailand.”
Ini kan artinya ada mekanisme kontrol yang halus (di Thailand), yang bahkan tidak disadari, sehingga membuat kagum seorang Kim Jong-il. Bagaimana pun kontrol terbaik adalah ketika kita mampu menginternalisasikan (kepatuhan) sehingga kita tidak lagi melihatnya sebagai problem.
Jadi saya tak bisa membayangkan bagaimana pemimpin asosiasi jurnalis Thailand bertemu dengan asosiasi jurnalis dari negara lain dan bicara soal kebebasan pers, tapi mereka tidak mau melihat dan tidak mau menyebut bahwa self-censorship yang mereka lakukan adalah problem.
Bisa dicontohkan self-censorship yang dilakukan oleh media massa Thailand?
Saya contohkan, 99 persen media massa mainstream di Thailand, tidak ada yang menyampaikan fakta bahwa Raja Thailand lebih sering berada di Jerman daripada di negaranya. Padahal ini dilaporkan dengan detail oleh media Jerman.
Kalau ini tidak memengaruhi hubungan dua negara tak masalah. Itu urusan pribadi. Tapi ini memengaruhi. Dan tidak ada (media) yang membahasnya.
Contoh lain adalah bagaimana media menghadapi tuntutan reformasi monarki yang disampaikan oleh para pemrotes sejak 2020. Sejumlah media melakukan self- censorship. Tidak semua tuntutan pemrotes ditulis dan banner yang berisi kecaman keras terhadap monarki tak muncul di media.
Bagaimana Anda melihat self-censorship yang mungkin dilakukan media atau jurnalis jelang pemilu?
Bangkok adalah kota utama di Thailand. Semua terkonsentrasi di Bangkok, termasuk media massanya. Media-media nasional yang berkantor di Bangkok ini bergantung pada stringer, bukan full time reporter. Mereka punya pekerjaan lain, misal pemilik usaha kecil. Tapi masalahnya adalah mereka rentan untuk disuap dan para kandidat akan mengirimi mereka pesan ketika datang masa pemilu. Stringer bisa bias karena dibayar oleh para kandidat.
Bagaimana dengan media-media independen? Bagaimana posisi Khasoed English?
Khasoed English adalah bagian dari media mainstream. Namun terkait dengan monarki, kami bisa bersikap independen. Ini lebih karena kami adalah media berbahasa Inggris. Jadi apa yang kami tulis tidak langsung berpengaruh seperti media-media berbahasa Thailand karena Prayut jarang baca media bahasa Inggris.
Apakah pernah ada kasus jurnalis yang terjerat UU Lese Majeste pascapemilu 2019?
Sangat sedikit, karena mereka melakukan sensor diri. Bahkan mereka melakukan sensor yang sebenarnya tak perlu disensor, seperti soal fakta Raja Thailand tinggal di Jerman.
Bagaimana dengan media sosial?
Selama dua tahun terakhir, ratusan orang yang terjerat UU ini karena menyampaikan kritik terhadap monarki di media sosial. Minggu lalu, seorang pustakawati usia 20-an dikenai vonis 9 tahun penjara karena mengunggah hal tersebut ke tiga media sosial miliknya. Dia bisa keluar dengan jaminan, dan saat ini sedang mengajukan banding.
Apa konten yang ia posting?
Soal kritik terhadap monarki. Anda tidak bisa bicara hal negatif tentang Raja tanpa membawa Anda masuk ke dalam penjara. Raja sudah seperti Tuhan. Minggu lalu, tiga orang divonis untuk hal serupa dan kemudian mereka melarikan diri keluar Thailand. Sekarang kami punya komunitas pembangkang yang tumbuh di Eropa dan Amerika Utara.
Generasi muda memiliki harapan yang berbeda. Mereka berani menyampaikan pendapat mereka tentang monarki dan kebebasan macam apa yang mereka butuhkan. Dan mereka kemudian mempostingnya di media sosial. Orang-orang tidak lagi percaya pada media mainstream. Orang-orang memilih menerjemahkan berita dari media asing, terutama terkait dengan kritik terhadap monarki, lalu membaginya ke Twitter, Facebook, dan kemudian mereka ditangkap.
Jadi serangan digital kebanyakan terjadi pada aktivis media sosial dan bukan jurnalis?
Ya, karena kebanyakan jurnalis memilih bermain aman. Mereka tidak mau berurusan dengan isu kerajaan. Saya pikir mereka akan diadili oleh sejarah. Saya sudah sampaikan ini ke mereka.
Selain UU Lese Majeste, apakah pemerintah Thailand juga menggunakan UU Komputer untuk menjerat jurnalis atau orang-orang yang mengkritik kerajaan dan memostingnya di media sosial?
Ya UU Lese Majeste dan UU Komputer. Lima tahun hukuman penjara untuk satu unggahan. Jadi kalau Anda mengkritik kerajaan dan kemudian mempostingnya di media sosial, maka Anda akan dianggap melakukan dua tindak kejahatan.
Apakah ada advokasi dari kelompok masyarakat sipil?
Masyarakat Thailand pada dasarnya menjaga kerajaan tak tersentuh oleh kritik. Nyaris seperti agama. Lebih bebas mengkritik Buddha Gautama daripada mengkritik kerajaan. Kami tidak punya konsensus. Itu masalah Thailand. Kami tidak punya kontrak sosial untuk menyetujui relasi macam apa yang dimiliki warga dengan institusi monarki dan apa batasannya. Hal lain, soal seberapa penting supremasi sipil. Itu dua isu penting Thailand.
Bagaimana Anda membandingkan situasi jurnalis di Thailand dengan negara lain di Asia Tenggara?
Dengan rendah hati saya mengatakan bahwa kami berada di tengah di antara negara-negara anggota ASEAN. Tentu saja lebih baik dari Kamboja, Laos, Vietnam, apalagi Myanmar. Mungkin bisa dibandingkan dengan Malaysia dan Indonesia. Sementara Filipina, pers bebas, tapi banyak jurnalis dibunuh. Saya bersimpati dengan masalah yang dihadapi setiap negara. Tapi setidaknya media atau jurnalis mengetahui dan mengakui masalahnya, bukan menafikannya.