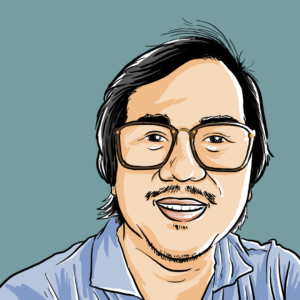Penantian empat tahun yang menguras waktu dan energi Ramsiah Tasruddin, seperti terbayar. Kepolisian Resort Gowa menghentikan penyidikan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada 3 Februari 2022 lalu.
“Saya mendengar langsung dari penyidik, dia menyampaikan ke saya. Rasanya Bahagia,” Ramsiah semringah menceritakan ulang momen itu melalui panggilan video dengan Jaring.id pada Kamis (27/10/2022).
Rasa senang itu tak bisa disembunyikan. Dengan antusias yang sama, ia menuturkan berulang soal keyakinan bahwa dirinya tak bersalah, apa yang dilakukan sudah benar, tidak melanggar undang-undang dan, betapa banyak dukungan yang ia dapat. Dari orang-orang yang, bahkan sama sekali tak pernah ia kenal, tapi justru begitulah harapan kemudian ia rawat.
“Sebenarnya teman LBH yang memberikan kekuatan. Ada dari PAKU ITE juga, banyak sekali. Saya dibuatkan grup sendiri untuk kasus saya. Saya terharu.. orang yang tidak saya kenal sebelumnya justru yang care,” ia mengenang hal-hal apa yang selama ini meneguhkannya.
Ramsiah, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Kota Makassar ini ditetapkan sebagai tersangka pada 1 September 2019 lalu. Ia dijerat Pasal 27 Ayat 3 UU ITE terkait dugaan penghinaan atau pencemaran nama.
Pelaporan dilayangkan Nur Syamsyiah pada Juni 2017 yang kala itu menjabat Wakil Dekan III UIN Alauddin Kota Makassar. Pangkal perkaranya, adalah percakapan di WhatsApp Group terbatas yang anggotanya terdiri atas dosen dan dekan. Mereka—termasuk Ramsiah—mengkritik keputusan Nur Syamsiah selaku Wakil Dekan III yang menutup Radio Syiar.
Buntut kritik tersebut, Nur Syamsiah melaporkan 30 orang ke kepolisian. Tapi dua tahun kasus berproses, kepolisian hanya menyisakan satu tersangka: Ramsiah Tasruddin.
“Kalau orang mengatakan terbebani atau tidak, ya pasti terbebani. Masalahnya kan ini tersangka, seumur-umur kita tidak pernah kan terpikir,” ungkap Ramsiah.
“Pastilah ada juga yang membekas di hati, kepikiran,” ia melanjutkan.
Selalu ada yang membekas. Seperti setelah terbit penghentian penyidikan atas kasusnya. Sekalipun perkara tak dilanjutkan, tetap ada yang tak bisa tergantikan selama masa-masa ia dijerat dengan pasal UU ITE.
“Kebebasan berekspresi saya direnggut. Yang pasti, waktu,” Ramsiah mengingat-ingat. Ia kemudian melanjutkan, “Pada intinya waktu, itu susah diganti dengan materi. Ketika saya bekerja, lalu dipanggil polisi, diminta kesaksian, saya pasti datang, saya taat kalau dipanggil”.
Saat tersandera status tersangka, Ramsiah juga sempat diminta untuk tidak urun bicara di grup WhatsApp hingga tak diperbolehkan mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus. Sejak berstatus tersangka pula, karir Ramsiah di kampus ikut mandek. Ia hanya boleh mengajar tanpa menduduki jabatan struktural. Pelantikan sebagai Wakil Dekan I pun kandas. Seminggu sebelum dilantik, surat penetapan tersangka datang ke ruangannya.
Baca juga: Empat Tahun Menunggu Kepastian Hukum
Padahal sebelum ditetapkan tersangka, karir Ramsiah di kampus terbilang moncer. Selama delapan tahun menjadi dosen, ia telah menduduki pelbagai jabatan, mulai dari sekretaris jurusan diploma, pengganti antar waktu ketua prodi jurnalistik dan kepala prodi ilmu komunikasi.
“Disamping saya tidak jadi dilantik menjadi Wakil Dekan I kala itu, beberapa momen penting kegiatan saya tidak diikutkan dengan asumsi saya menjalani proses hukum tersangka,” ucap dia lagi.
Masa-masa memanggul status tersangka adalah bagian sulit dalam hidup Ramsiah. Tapi jalan untuk terlepas dari status tersangka dengan mengupayakan penghentian penyidikan kasusnya, juga bukan perkara yang mudah.
UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang telah mengatur bahwa penghentian penydikan merupakan wewenang penyidik. Ketentuan ini menyebutkan tiga hal yang menjadi alasan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pertama, penyidik tidak menemukan cukup bukti untuk melanjutkan kasus; kedua penyidik menemukan bahwa kasus tersebut ternyata bukanlah suatu tindak pidana; ketiga dihentikan demi hukum.
Kendati demikian bunyi perundangan, yang terjadi di lapangan tak sesederhana itu. Meski kasus Ramsiah misalnya, ditengarai kurang pembuktian—ditunjukkan dengan hilir-mudiknya berkas perkara dari kepolisian ke kejaksaan—nyatanya tak segampang pula kasus lantas dihentikan.
Sepanjang empat tahun mengupayakan penghentian kasus, Ramsiah mesti bolak-balik tak terhitung jumlah, utamanya dalam tiga tahun belakangan.
“Yang gencar itu 2020, 2021 dan 2022 itu bisa sebulan sekali atau tiga bulan sekali, bergantung penyidiknya.” Ramsiah tak menampik dua tahun pertama menjadi momen terberat menghadapi kasus. “Tahun ketiga keempat itu saya jalani saja, saya enjoy, karena banyak yang backup saya.”
Koordinator Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE), Muhammad Arsyad membeberkan sedikitnya lima kali pihak kejaksaan mengembalikan berkas perkara hingga kemudian baru terbit SP3. Saling lempar antara kepolsian dan kejaksaan ini menurutnya sudah jadi problem klasik yang kerap ditemui saat mendampingi perkara.
“Kami sempat bertanya ke penyidik, kenapa lambat dilakukan SP3? Dia (polisi) berharap dengan dia mengirim, karena tidak cukup alat bukti, maka jaksa yang diminta untuk mengeluarkan SP3. Lah jaksa bilang, kalian (polisi) yang menetapkan tersangka kok kami (jaksa) yang diminta menghentikan perkara,” terang Arsyad saat dihubungi Jaring.id pada Rabu (28/9/2022).
Dugaan lain yang mengemuka, menurut Arsyad, salah satu faktor keengganan polisi menerbitkan SP3 lantaran berkaitan dengan penilaian kinerja. “Ketika kami berkomunikasi dengan beberapa orang di kepolisian, saat polisi melakukan SP3 itu akan menjadi catatan buruk bagi penyidik kepolisian dan akan dimintakan pertanggungjawaban juga pemeriksaan, kenapa menetapkan tersangka tapi ujung-ujungnya di-SP3-kan,” beber dia.
Saat hal tersebut dikonfirmasi ke pihak kepolisian, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Asep Edi Suheri belum menjawab lugas. Ia hanya menanyakan detail kasus dan menjanjikan akan memastikan langsung ke penyidik yang bersangkutan.
“Biar nanti saya cek penyidiknya. Saya cek dulu kasusnya,” jawab Asep singkat kepada Jaring.id pada Kamis (27/10/2022).
‘Hantu-hantu’ Kasus Menggantung
Arsyad menyayangkan sikap aparat yang terkesan mengulur waktu penghentian kasus serta tabiat saling lempar di antara penegak hukum. Sebab, lagi-lagi yang kena getahnya adalah warga yang digantungkan status hukumnya.
“Simalakamanya ada di korban, si oknum polisi yang grasa-grusu menaikkan status tersangka, giliran alat bukti tak bisa dia penuhi, dia tidak mau menghentikan perkara itu,” tukas Arsyad yang juga menjadi pengacara tersebut.
“Apakah dia pernah berpikir bagaimana nasib orang yang dijadikan tersangka? Di SKCKnya kan pasti ada catatan,” ia menggugat.
Bukan sekali dua ia didatangi korban-korban yang tersandera jerat pasal UU ITE. Ada yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, kehilangan kesempatan promosi atau naik jabatan, berisiko mendapat stigma di lingkungan masyarakat bahwa para korban tak beda dengan pelaku kejahatan lain, tak lagi leluasa menyampaikan pendapat di media sosial, hingga dirundung cemas akan dipenjarakan.
Yang paling mendasar menurut Arsyad, ketakjelasan status hukum ini akan berdampak secara psikologis. Selain tak jarang menghadapi aparat yang seliweran, korban yang kasusnya menggantung akan hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran ancaman penahanan.
“Setiap saat mereka dihantui akan dilakukan penahanan. Jadi tiap kami komunikasi, pasti menangis, yang ditanyakan, ‘bagaimana kasus saya? Kira-kira saya tidak ditahan kan, Bang?’ Itulah yang paling sering kami dapatkan untuk teman-teman yang statusnya menggantung,” cerita Arsyad.
Kisah lain dialami Anindya Shabrina Prasetiyo. Aktivis mahasiswa yang memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua tersebut hingga kini masih berstatus tersangka, sejak ditetapkan pada November 2018.
Anin salah satu yang bertemu ‘hantu-hantu’ itu akibat kasusnya digantung polisi. Ia mengaku telah kehilangan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Ada bayang-bayang kekhawatiran setiap kali hendak berpendapat di media sosial, menulis, atau menyampaikan paparan dalam diskusi juga seminar di kampus-kampus.
Itu mengapa ia memilih lebih berhati-hati. “Nanti takutnya kasusku dinaikkan. Masa’ menunggu kedaluarsa dulu baru bisa menulis,” ungkap Anin saat diwawancara Jaring.id pada 21 Oktober 2021 lalu.
Anindya dijerat dugaan pencemaran nama sesuai Pasal 27 ayat 3 UU ITE jo. Pasal 45 ayat 3 UU ITE dan penyebaran kebencian sesuai Pasal 28 ayat 2 jo. Pasal 45A ayat 2 UU ITE. Ia dilaporkan pada 25 Juli 2018 lewat surat LP/B/658/VII/2018/JATIM/RESTABES SBY.
Pelaporan tersebut terkait status Anin di Facebook miliknya. Saat itu, Anin menyampaikan kronologi dugaan tindakan sewenang-wenang polisi di asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya. Ia menulis bahwa dirinya menjadi korban tindakan represif polisi dan pelecehan seksual. Anin diseret sembari dibentak dengan kata-kata kasar. Dalam kejadian itu Anin mengaku payudara sebelah kanannya diremas ketika diseret beramai-ramai.
Lima tahun berlalu, kasus Anindya tak kunjung rampung. Alih-alih selesai perkaranya, Anindya mengaku kerap dimanfaatkan kepolisian untuk meminta penjelasan maupun keterangan ihwal aksi mahasiswa yang berkaitan dengan Papua, buruh, hingga mahasiswa. Tak jarang kepolisian datang ke rumahnya untuk sekadar mengorek informasi kegiatan demonstrasi.
Setiap kali akan ada demo terkait Papua, Anin tak luput disambangi polisi. “Sehari sebelum aksi, pasti Anin didatangi pihak kepolisian. Walaupun alasannya silaturahmi dan lain sebagainya, tapi secara tidak langsung itu memberikan warning bahwa hai status kamu masih tersangka lho,” tutur Arsyad dalam kesempatan lain.
Kasus lain menimpa Ravio Patra. Ia menghadapi dua laporan UU ITE. Pertama terjadi pada 2016 terkait statusnya di Facebook yang mengungkap kedok motivator. Status ini berujung penetapan tersangka. Kasus kedua terkait statusnya di Twitter. Ravio mengunggah pernyataan menyoal staf khusus, Billy Mambrasar. Kini, kasus Ravio tak kunjung rampung.
Sementara kasus yang menimpa Siti Rubaidah sudah berlangsung 10 tahun. Seorang ibu rumah tangga yang dilaporkan suaminya—saat itu menjabat wakil wali kota Magelang, dituduh mencemarkan nama karena membikin petisi yang ditujukan kepada Gamawan Fauzi, mantan Menteri Dalam Negeri. Ia meminta Mendagri mengambil sikap atas tindak kekerasan rumah tangga yang dilakukan pejabat publik.
Baca juga: Hari-hari Hadapi Depresi Menahun
Koordinator PAKU ITE, Muhammad Arsyad menyatakan secara angka, kasus-kasus yang menggantung persentasenya kurang dari 5 persen atau jika dihitung ada belasan jumlahnya. Tapi ia menekankan, ketakjelasan status hukum ini bukan sekadar banyaknya perkara, melainkan soal hidup individu-individu yang direnggut hak-haknya.
“Kami tidak melihat soal angka, tapi kita melihat kesempatan dan hak-hak dasar seseorang yang dengan mudah dicerabut. Angka 12 (kasus menggantung) itu sudah fantastis ya, karena orang-orang ini yang mengadukan kasusnya, yang tercatat,” tukas Arsyad.
Kasus-kasus yang tak mendapatkan kejelasan status hukum membikin korban UU ITE seperti tersandera. Mereka seakan keluar dari jeruji penjara hanya untuk melenggang ke halaman penjara yang teramat luas. Jangankan berpendapat, untuk menggunakan media sosial pun mereka khawatir kasusnya akan diangkat kembali.
Mengulur Kepastian Status Hukum Masuk Kategori Pelanggaran HAM
Keluhan ihwal ketidakpastian status hukum ini juga diakui Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti. Meski memang ini tak terbatas pada laporan terkait UU ITE. Berdasarkan laporan yang masuk ke lembaganya, saban tahun rata-rata Kompolnas menerima 3.000-4.000 pengaduan.
“90 persen dari pengaduan tersebut mempermasalahkan kinerja reserse. Mayoritas mengeluhkan pelayanan buruk, termasuk penanganan kasus yang berlarut-larut atau ketidakpastian status hukum,” terang Poengky kepada Jaring.id pada Kamis (29/9/2022).
Ia pun menuturkan, dalam menangani perkara terkait UU ITE, banyak masyarakat mengeluh bahwa kepolisian lebih disibukkan menangani konflik yang muncul akibat unggahan-unggahan di media sosial ketimbang memburu pelaku-pelaku kejahatan siber.
Bahkan, Poengky melanjutkan, penyidik polisi kadang dengan mudah segera menjadikan seseorang sebagai tersangka jika kasus itu menyangkut pejabat. Sekalipun pejabat yang bersangkutan tidak melapor ke polisi.
Karena itu ia berharap penyidik polisi sungguh-sungguh menjadikan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi UU ITE sebagai panduan dalam menangani laporan kasus ITE. “Sehingga akan meminimalisir keluhan ketidakpastian hukum.”
Ia pun mengingatkan penyidik kepolisian untuk segera menerbitkan SP3 bila memang tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana dan, dihentikan demi hukum. Untuk menerbitkan SP3 maka gelar perkara harus dilakukan.
“Jika penyidik mengulur-ulur waktu mengakibatkan lamanya diperoleh kepastian status hukum, maka hal tersebut sebetulnya masuk kategori pelanggaran HAM karena setiap orang berhak untuk segera mendapatkan kepastian hukum,” ia menambahkan.
Itu sebab, Kompolnas mendorong penyidik untuk memedomani dan mengimplementasikan SKB UU ITE dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai, lanjut Poengky, ada kesalahan dalam menerapkan langkah hukum. “Jika memang memenuhi syarat untuk SP3 maka harus segera dilakukan SP3 untuk memberi kepastian hukum,” tegas dia.
Bertolok pada pelbagai situasi ini, Poengky lebih lanjut menilai bahwa profesionalitas penyidik Polri dalam menangani kasus-kasus terkait UU ITE perlu ditingkatkan. “Khususnya para penyidik di daerah-daerah, mengingat kurangnya kuantitas dan kualitas SDM, sarana-prasarana, dan anggaran yang kecil jika dibandingkan dengan kerumitan perkara yang dihadapi.
Dikonfirmasi terpisah mengenai kejelasan status hukum belasan kasus UU ITE yang masih menggantung, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Asep Edi Suheri menyatakan belum bisa memberikan jawaban.
“Nanti saya cek dulu ke para Kasubdit ya, Mba. Dengan kasus sebanyak itu tentunya semua berproses, saya pastikan dulu sampai di mana prosesnya. Mohon waktu ya, Mba,” kata Asep.
Studi ICJR pada 2021 tentang penerapan UU ITE di Indonesia menemukan sejumlah masalah dari sisi perumusan hingga penerapan beleid. Bukan saja terkait praktik penafsiran unsur pasal yang tidak jelas, melainkan juga problem berupa rendahnya standar pembuktian dan relasi kuasa dalam perkara.
Karena itu salah satu rekomendasi yang muncul kala itu adalah penegakan hukum kasus-kasus terkait ITE harus disertai perbaikan hukum acara pidana. Selain buruknya proses penanganan UU ITE oleh penegak hukum, celah lain yang menurut Arsyad turut menyumbang penyebab berlarut-larutnya perkara adalah soal kepastian kedaluwarsa.
“Ini kan KUHP akan direvisi, kami juga berharap ada kepastian kedaluwarsa dalam penanganan kasus, itu juga harus dijelaskan. Memang salah satu cara ya dengan melakukan revisi UU ITE, supaya hal-hal seperti ini (mengulur-ulur dan menggantung kasus) tidak menjadi kebiasaan penyidik ke depannya,” pungkas Arsyad.
Adapun kasus yang berlarut, mestinya pun bisa dinyatakan kedaluarsa. Hal ini sesuai Pasal 78 KUHP. Isinya, mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, jangka waktu kedaluwarsa satu tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, jangka waktu kedaluwarsa 6 (enam) tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, jangka waktu kedaluwarsanya 12 tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, jangka waktu kedaluwarsanya 18 tahun.
Sayangnya, tidak sedikit korban UU ITE masih berstatus tersangka meski sudah bertahun-tahun kejadian tersebut berlalu. Satu kasus Ramsiah kini bisa dibilang selesai dan penyidikannya dihentikan, tapi nama-nama lain yang status hukumnya tak jelas masih mengantre. Ada Andi Hidayat yang sejak 2019 menjadi tersangka, ada Anindya yang dirundung was-was sejak 2018, ada Ravio Patra, Randy Saputra, juga nama-nama lainnya.
Karena itu saat mati-matian mengupayakan penghentian kasus, Ramsiah paham betul bahwa perjuangannya bolak-balik juga dioper-oper dari penegak hukum satu ke yang lainnya itu bukan perkara kasusnya saja. Akan tetapi juga soal korban-korban UU ITE lain yang kasusnya masih digantung.
Karena itu ia pun berharap korban-korban ITE lain tak patah arang mengupayakan kepastian status hukum. Ramsiah mengaku terbuka jika ada korban lain yang ingin berdiskusi ihwal pengalamannya berperkara terkait UU ITE.
“Bagi mereka, bagi siapapun yang terjerat UU ITE, selalu yakin sepanjang kalian benar, jangan berputus asa.. walaupun memang kita harus bolak-balik, yakinlah pasti bisa,” Ramsiah memberi semangat.
“Dan, saya juga berharap ke depan revisi UU ITE itu betul-betul terjadi. Yang dijerat UU ini memang yang betul-betul melanggar, bukan sekadar pasal baper, jadi ajang balas dendam, dan lain sebagainya,” lanjut Ramsiah.