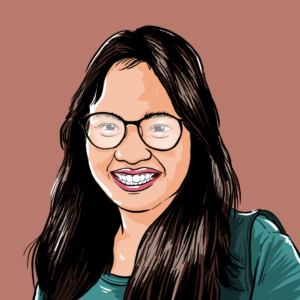Ramadio tak duduk lama di kursi nomer satu Kabupaten Buton Utara. Setelah sempat sebagai pelaksana tugas (plt) Bupati Buton Utara pada Jumat, 25 September 2020, ia diberhentikan sementara oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut usulan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi yang disampaikan lewat surat nomor 132.74/4830 tertanggal 30 September 2020.
Pelantikan Ramadio sempat memancing polemik. Pasalnya, ketika itu ia menyandang status tersangka kasus dugaan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Meski demikian, ia tak langsung ditahan.
“Kami melihat kalau masih status tersangka dan tidak ditahan maka masih boleh melaksanakan tugas,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nur Endang Abbas kepada Jaring.id pada Kamis, 1 Oktober 2020.
Kepolisian Sektor Bonegunu Resort Muna menetapkan Ramadio dan seorang muncikari sebagai tersangka kejahatan seksual pada 22 Desember 2019. Ia, diduga memperkosa anak perempuan usia 14 tahun di Buton Utara. Sementara Pengadilan Negeri Raha telah menjatuhi vonis enam tahun penjara untuk muncikari, proses hukum Ramadio berlarut-larut.
Direktur Yayasan Lambu yang juga mendampingi korban, Ina Yustina Fendrita mengatakan salah satu penyebab belum dilakukannya penahanan karena tersangka berstatus wakil bupati. Merujuk Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri untuk menyidik dan menahan wakil dan kepala daerah.
“Kami pernah menanyakan kepada Polda Sultra apakah izin penyidikan dan penahanan sudah diajukan? Jawabannya waktu itu mereka sedang mengajukan dan menunggu izin dari kemendagri. Tapi kok hampir setahun prosesnya pelaku tak kunjung ditahan,” kata Yustina dalam konferensi Pers bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada Selasa, 29 September 2020.
Saat ini penanganan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Ramadio telah dialihkan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra). Menurut Yustina, hal tersebut membuat pengawasan dari pendamping semakin sulit. Pun penanganan kasus ikut melambat. Dua kali berkas diajukan Polda Sultra, keduanya ditolak Kejaksaan Tinggi Negeri Sulawesi Tenggara.
Yustina menduga ada kecerobohan ketika penyusunan berkas sehingga kasusnya dianggap tidak layak. Alasan penolakan berkas kedua, lanjutnya, juga tak masuk akal lantaran Kejati meminta dihadirkan saksi yang melihat langsung kejadian.
“Tidak mungkin ada saksi yang melihat langsung pemerkosaan karena terjadi di ruang tertutup,” kata Yustina.
Merespons lambatnya penanganan, Yayasan Lambu Ina melayangkan surat pengaduan ke Komisi Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Kejaksaan pada Juli 2020. Yayasan Lambu Ina menilai ada upaya kepolisian maupun kejaksaan untuk menghambat proses penanganan kasus kejahatan seksual wakil bupati sehingga berlarut-larut.
***
Kepala Bidang Humas Polda Sultra La Ode Proyek membantah ada usaha menghambat penanganan kasus. Segendang sepenarian dengan Kajati, ia mengatakan lamanya penanganan kasus disebabkan sulitnya membuktikan terjadinya perbuatan asusila. Polda, lanjutnya, telah mengembalikan berkas dan dinyatakan lengkap oleh Kajati pada 16 September 2020.
La Ode menolak mengomentari alasan penarikan kasus dari Polres Muna ke Polda Sultra. Ia juga tak membeber alasan mengapa Ramadio tidak ditahan selama proses penyidikan.
“Sekarang objek hukumnya sudah di Kajati Muna, kami tidak berkapasitas menjawab lagi,” katanya ketika dihubungi Jaring.id pada Sabtu, 3 Oktober 2020.
Kasus Ramadio ramai di publik setelah Komnas Perempuan dan Yayasan Lembu Ina menggelar konferensi pers pada 29 September 2020. Dalam kegiatan itu, Komnas meminta Kementrian Dalam Negeri mengevaluasi pengangkatan Ramadio sebagai plt bupati.
Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah menilai hukum pidana yang dipakai menangani kekerasan seksual dan menuntut adanya saksi yang melihat kejadian mempersulit penanganan kasus. Hal ini kerap menyebabkan banyak kasus ditolak oleh penegak hukum karena kurangnya saksi dan bukti.
Ia menilai kasus Ramadio menggambarkan sulitnya menjerat pejabat publik yang melakukan kejahatan seksual. Pemeriksaan dan penahanan kepala daerah masih memerlukan persetujuan dari menteri. Di saat yang sama, pejabat publik punya relasi kuasa yang dapat mempengaruhi proses hukum.
“Jaminan hukum dan komitmen mengatasi kekerasan seksual mengalami hambatan berlapis ketika terduga pelaku ada pejabat publik,” kata Siti Aminah.
***
Sepanjang 2018 – Januari 2020, Komnas Perempuan mencatat kekerasan seksual yang dilakukan pejabat publik sebanyak 115 kasus. Sebanyak 26 kasus diantaranya dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Sisanya sebanyak 20 kasus dilakukan anggota Polri, 16 kasus melibatkan guru, dan 12 kasus terkait dengan anggota TNI.
Selain kasus Ramadio, dugaan kekerasan seksual pejabat publik maupun tokoh masyarakat yang menjadi perhatian khusus Komnas Perempuan adalah kasus plt Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Papua Alosius Giay dan anak Kiai di Jombang Mochammad Subchi Azal Tsani.
Sayangnya, kekerasan seksual yang diduga dilakukan plt kepala RSUD Papua Alosius Giay terhadap pelajar usia 18 tahun sudah mendapat surat penghentian penyidikan dan penuntutan dari Polres Jakarta Selatan pada Februari 2020. Sementara kasus Mochammad Subchi yang diduga memperkosa santri, berkasnya berkali-kali ditolak kajati Jatim.
Data Komnas Perempuan, dari kasus perkosaan yang terjadi periode 2016-2019, hanya 29 persen yang dilaporkan ke polisi. Dari jumlah tersebut hanya 22 persen diantaranya yang sampai ke persidangan, sedangkan sisanya kandas di masalah pembuktian atau berujung mediasi.
Andaipun kasus rampung, Siti Aminah mengatakan, kasus kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik sering tidak memberikan keadilan kepada korban. Ia mencontohkan dugaan pemerkosaan oleh Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenaga Kerjaan Syafri Adnan Baharuddin kepada asistennya. Dewan Jaminan Sosial Nasional menyatakan Syafri terbukti melakukan pemerkosaan lewat surat nomor 49/DJSN/II/2019 tanggal 11 Februari 2019. Namun, Syafri melaporkan balik korban dengan tuduhan penyebaran berita bohong menggunakan UU ITE. Kasus tersebut berakhir dengan pengakuan tertulis korban bahwa dirinya tidak pernah mengalami pemerkosaan.
“Akhirnya korban menerima tawaran mediasi dari pelaku dan pelaku mencabut laporannya. Proses ini menyebabkan korban mengalami gangguan kejiwaan dan sempat dirawat di rumah sakit,” katanya.
Di tengah proses hukum, Syafri dinyatakan lolos seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI sampai tahap uji kelayakan di DPR RI. Siti menilai lolosnya Syafri menunjukkan dalam seleksi pejabat publik riwayat kekerasan seksual tidak menjadi pertimbangan dalam seleksi pejabat publik.
***
Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu Maksoem menilai pengangkatan pejabat publik seharusnya dilakukan ketika pejabat sudah terbebas dari dugaan tindak pidana terutama kekerasan seksual. Kasusnya wajib dibuka untuk membuktikan benar atau tidaknya dugaan kepada pelaku. Jika pelaku benar melalukan kekerasan seksual tetapi kasusnya tidak pernah dibuka maka potensi kerentanannya lebih tinggi.
“Karena sebetulnya penguasa punya relasi kuasa kepada bawahannya. Kalau tidak diselesaikan berpotensi melakukan keberulangan tindakan kekerasan seksual kepada orang yang lebih lemah stratanya dari dia,” kata Ninik Rahayu ketika dihubungi pada Kamis, 1 Oktober 2020.
Ninik menambahkan kekerasan seksual bukan delik aduan sehingga kepolisian punya kewajiban menemukan dan mengungkap pelaku. Sehingga ketika ada penyelesaian kasus kekerasan seksual yang mandek, Ia menilai ada proses maladministrasi yang dilakukan aparat penegak hukum maupun lembaga perlindungan anak dan perempuan yang dibentuk pemerintah.
“Mereka tidak menjalankan kewajibannya sebagai aparat keamanan yang menjaga masyarakat dari tindakan kekerasan seksual, apalagi pelakunya pejabat publik,” katanya.
Pendiri Institut Perempuan Valentina Sagala menilai kekerasan seksual tidak bisa dipandang semata-mata sebagai kasus kesusilaan tetapi kejahatan terhadap tubuh manusia yang bisa dialami perempuan dan laki-laki. Kekerasan seksual terjadi ketika kuasa pelaku sebagai superordinat sementara korban sebagai subordinat.
“Dalam kasus kekerasan seksual pejabat publik dan ASN, disitulah terlihat dengan jelas ada relasi kuasa yang timpang. Dia laki-laki dengan perempuan sudah ada relasi gender yang timpang, ditambah status pelaku dan korban ini juga menimbulkan ketimpangan,” katanya.
Dengan adanya ketimpangan tersebut, Valentina menilai hukum seharusnya memastikan keadilan dalam menangani kekerasan seksual. Sayangnya, Indonesia belum memiliki terobosan hukum menangani kekerasan seksual karena belum memiliki undang-undang yang mengatur kekerasan seksual. Penanganan kasus kekerasan seksual masih mengandalkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih melindungi tersangka ketimbang korban.
Valentina yang tergabung dalam Tim Substansi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mengatakan dalam draft RUU PKS terdapat terobosan hukum untuk pejabat publik pelaku kekerasan seksual. Pejabat publik yang terlapor melakukan kekerasan seksual tidak perlu mendapat izin Kemendagri untuk diperiksa dan ditahan.
Selain itu, dalam RUU PKS dikenakan pemberatan sanksi sepertiga kepada pelaku yang punya relasi kuasa dengan korban seperti pejabat publik, ASN, dan aparat penegak hukum. Masyarakat juga diberi kewenangan mengawasi jalannya proses hukum kasus kekerasan seksual.