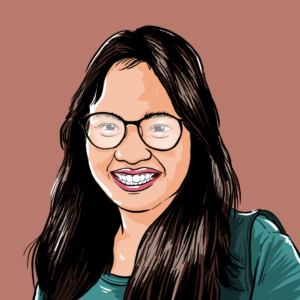Tata lampu gantung di media pamer Jakarta Creative Hub (JCH), Jakarta Pusat menyoroti salah satu karya berupa percakapan antara satu karakter kartun dengan warga Malaysia yang multietnik.
“Untuk dilahirkan sebagai Cina, apakah itu pilihan kamu?”
“TIDAK.”
Pertanyaan yang sama ditulis berulang. Ditujukan kepada etnis lain di Malaysia, seperti India dan Melayu. Kartunis di balik karya tersebut seakan punya unek-unek ketidakpuasan, sekaligus gemas dengan sikap intoleran di negerinya, utamanya ketika kontestasi politik di negeri jiran berlangsung. Pada 2018 lalu misalnya, di mana tidak sedikit dari warga yang menolak pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD).
“Lahir dalam suku tertentu bukanlah pilihan kamu. Itu adalah kehendak Tuhan. Jadi, siapa yang memberimu hak untuk bersikap rasis?” begitu tanya kartunis dalam karya yang dipamerkan melalui festival keberagaman bertajuk Beda Ragam, Saling Sapa garapan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN).
Arsiran sederhana tersebut dibuat kartunis Malaysia, Zulkiflee Anwar Haque (Zunar). Pada masa rezim Najib Razak (2009-2018), kartunis politik kelahiran 1962 ini berkali-kali berlawan dengan pemerintah melalui karikatur. Berkali-kali pula ia menghadapi dakwaan penjara lantaran dianggap melakukan pencemaran nama baik dan melanggar Undang-Undang Penghasutan 1948. Selain dilarang bepergian ke luar negeri hingga 2018, dari 19 buku kumpulan kartun, 12 di antaranya dilarang beredar. Bahkan pemerintah Negeri Jiran sudah menangkap tiga penerbit yang mencetak buku kartun Zunar.
“Sesuai aturan Malaysia, nama penerbit harus diletakkan di halaman depan buku, jika tidak maka buku dianggap ilegal. Supaya penerbit mau mencetak, maka saya tutup hitam nama penerbit di sampul depan. Saya kirim nota ke polisi, jika ingin tahu siapa pencetaknya silakan gosok yang ditutup hitam dan menang, ” ungkap Zunar disambut tawa puluhan peserta diskusi, Rabu, 9 Januari 2020.
Selepas pemilu, ia bertekad “membangun kembali bangsa” Malaysia melalui penerbitan buku kumpulan karikatur antirasisme berjudul Rebuilding Nation. Buku yang terbit akhir 2019 lalu itu memuat sebanyak 48 karikatur yang hendak menolak praktik diskriminasi rasial. Menurut Zunar, pemilihan perdana menteri Malaysia pada 2018 lalu telah merusak toleransi dan keberagaman di negerinya. Kata dia, kebencian dan sentimen rasial masih bertahan, meski pemilu telah selesai.
“Di Malaysia kebanyakan orang menghujat berdasarkan emosi, kurang punya fakta atau kurang diberi pendidikan,” ungkap Zunar.
Sama halnya dengan Indonesia, polarisasi akibat perbedaan pilihan politik masih terjadi, meski pemilu telah selesai. Alissa Wahid, Koordinator Jaringan GusDurian mengungkapkan bahwa penggunaan pesan intoleran dalam pemilu berdampak jangka panjang. “Pemilu kemarin ibarat menancapkan paku ke papan yang mana bekas lubang akan tertinggal sekalipun paku sudah dicabut,” ungkap Alissa.
Gelombang sentimen agama di Indonesia mula-mula dipantik dalam sekam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta pada 2017. Di tengah kontestasi politik, sebagian masyarakat menggunakan isu penistaan agama sebagai komoditas untuk mendeskreditkan salah satu kandidat, yakni Basuki Purnama (Ahok). Bekas Gubernur DKI Jakarta itu dijerat Pasal 156a tentang Penistaan Agama. Tak sampai di situ, isu serupa juga mewarnai pemilihan presiden 2019. “Sentimen agama itu biasa antar kelompok. Sayangnya begitu ada kontestasi politik dan perebutan kekuasaaan itu jadi sumbu untuk menghancurkan satu sama lain,” kata Alissa.
Hal ini, menurut Alissa, yang menyebabkan pergeseran praktik keagamaan di Indonesia yang mula-mula inklusif menjadi ekslusif tidak menerima perbedaan. Pergeseran ini berbahaya bila tidak ada perlindungan terhadap kelompok minoritas. Kata dia, kondisi ini diperburuk lemahnya perlindungan hukum terhadap kelompok minoritas. Mereka kerap menjadi korban jika berhadapan dengan mayoritas. “Aparat penegak hukum meletakkan “kerukunan” jadi nomor satu dengan mengorbankan hak kontitusi kelompok minoritas,” kata Alissa.
Melalui Jaringan Gusdurian yang tersebar di 140 kota, Alissa membangun ruang aman bagi kelompok rentan. Melalui gerakan ini, Alissa mengadvokasi dan mengampanyekan toleransi hingga ruang keluarga. Pasalnya, menurut dia, konservatisme beragama kerap bertumbuh di tengah keluarga. Salah satu hal yang Alissa soroti ialah gerakan perempuan pulang ke rumah, narasi penerimaan poligami, hingga Indonesia tanpa pacaran semakin memarginalkan perempuan dan anak.
“Jika kita tidak merespon dengan cepat, paling cepat dua puluh tahun lagi status kependudukan, perempuan, anak akan berubah,” ia meyakinkan.
Hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah, Jakarta yang dirilis tahun 2017 misalnya, menunjukkan 51,1% mahasiswa/siswa beragama Islam memiliki opini intoleran terhadap aliran Islam minoritas. Di antara aliran Islam minoritas tersebut terdapat Ahmadiyah dan Syiah.
Peneliti Human Right Watch (HRW), Andreas Harsono menyatakan bahwa Indonesia mengalami peningkatan intoleransi sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu, pemerintah memperkuat pasal penodaan agama pada 2004. HRW mencatat sedikitnya 125 orang dipenjara karena dianggap melakukan penodaan agama. Sementara data lain menunjukkan adanya penutupan terhadap 1056 Gereja. Kata dia, tindakkan intoleran ini ditandai dengan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada 2004.
Oleh sebab itu, menurut Andreas, salah satu jalan agar diskriminasi berkurang ialah dengan cara menghapus seluruh regulasi yang mendiskriminasi. Di samping itu, peran wartawan juga penting dalam mengungkap kasus diskriminasi yang dialami kelompok minoritas. Kata dia, selain berani menulis, wartawan juga perlu terlepas dari bias. Hasil survei Pantau pada 2012 menyebut jurnalis justru mereproduksi kebencian terhadap kelompok minoritas yang tercermin lewat pemilihan diksi.
“Bias di kalangan wartawan salah satu persoalan, belum lagi lembaga yang memfasilitasi diskriminasi semakin diperkuat. Banyak pemimpin kita tidak tahu atau yang tahu tetapi tidak berani,” ujar Andreas.
Sementara itu, Janet Steele, Professor of Media and Public Affairs and International Affairs Columbian College of Art & Science menyebut praktik jurnalisme yang baik akan membantu meningkatkan toleransi di tengah masyarakat. Praktik jurnalisme yang baik paling tidak harus memenuhi sembilan elemen jurnalisme, antara lain memberitakan kebenaran, loyalitas kepada masyarakat dan melakukan verifikasi. Meski demikian, menurut Janet, wartawan tidak harus melulu fokus pada kasus, melainkan juga mencari solusi fberupa upaya yang sudah dilakukan masyarakat dalam melawan intoleransi. “Media yang independen lebih penting,” kata Janet.