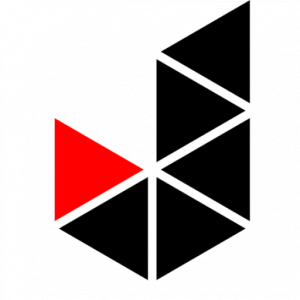Presiden Jokowi bergerak cepat memroses daftar nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Sementara di Senayan, para politikus tidak hanya bersiap memeras 10 nama, tapi meloloskan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Presiden Joko Widodo tidak perlu waktu hingga 14 hari—sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002—buat mempelajari 10 nama calon pimpinan lembaga antikorupsi yang disodorkan panitia seleksi pada Senin, 2 September 2019.
Tak lebih dari 2 kali 24 jam, Jokowi telah menyerahkan daftar nama capim untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka adalah Alexander Marwata, Firli Bahuri, I Nyoman Wara, Johanis Tanak, Lili Pintauli Siregar, Luthfi Jayadi, Nawawi Pamolanggo, Nurul Ghufron, Roby Arya Brata dan Sigit Danang Joyo.
Anggota Komisi III DPR RI, Taufiqulhadi mengatakan, proses seleksi pekan depan—minggu kedua September—akan dibuka dengan pembuatan makalah. Setelah itu, DPR baru melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 10 orang capim KPK yang disetujui presiden. Politikus dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) ini menilai tidak ada yang perlu dipermasalahkan dari nama-nama tersebut.
“Tidak ada yang bermasalah,” ujar Taufiqulhadi saat dihubungi Jaring.id melalui sambungan telepon pada Rabu, 4 September 2019.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mempertanyakan langkah buru-buru Jokowi. Padahal sebelumnya, presiden sempat menyatakan tidak ingin tergesa-gesa menyerahkan daftar nama yang diputuskan pansel capim KPK ke DPR.
“Jokowi tergesa-tergesa tanpa ada pertimbangan jelas. Kalau mau menerima masukan masyarakat tidak bisa satu hari. Ini kontradiksi dari pernyataan Jokowi,” ujar Kurnia di sekretariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Rabu, 4 September 2019.
Usai menerima pansel capim KPK yang diketuai Yenti Ganarsih di Istana Merdeka pada Senin, 2 September 2019, Presiden Jokowi menyatakan perlunya masukan dari masyarakat untuk mengoreksi kerja pansel. Namun, gerak cepat Jokowi menyerahkan daftar nama tersebut ke DPR kemarin, Rabu, 4 September 2019, menunjukan bahwa presiden tidak benar-benar ingin menerima masukan masyarakat. Padahal, menurut Kurnia, pertimbangan masyarakat maupun masukan internal KPK merupakan unsur utama dalam proses penyaringan pimpinan lembaga antirasuah.
“Kalau sudah diserahkan sulit (mencoret-red),” ungkap Kurnia.
Pegawai KPK, Nanang Farid Syam menyesalkan keputusan Jokowi yang tidak mendengar aspirasi internal KPK. Menurut penasihat Wadah Pegawai KPK ini, daftar nama capim yang disetor Jokowi ke DPR masih bermasalah.
Dari 10 nama, tercatat masih ada capim yang tidak melaporkan jumlah harta kekayaan (LHKPN) secara berkala. Bahkan di antara nama tersebut ada yang diduga melanggar etik dan menerima gratifikasi, serta memiliki gagasan yang kontraproduktif dengan upaya memberantas korupsi.
“(Karena itu-red) tidak ada alasan bagi kami untuk diam,” kata Nanang.
Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi kawal capim KPK, seperti ICW, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (NU) mewanti-wanti agar Presiden Jokowi tidak salah memilih pimpinan KPK. Pasalnya dari 10 kandidat hasil pansel, nama Firli Bahuri masih berada dalam daftar.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan ini diduga pernah melanggar Pasal 65 dan 66 Undang-Undang KPK ketika bertugas sebagai Deputi Penindakan KPK. Pasal itu melarang pegawai mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK tanpa alasan yang sah.
Dalam tahap uji publik dan wawancara calon pimpinan KPK di Sekretariat Negara, Jakarta akhir pekan lalu, pertemuan Firli dengan Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, pihak yang sempat diduga terlibat korupsi dana divestasi Newmont Nusa Tenggara menjadi bahan pertanyaan pansel capim KPK. Selain itu, pansel capim KPK juga mempertanyakan dugaan gratifikasi berupa biaya inap hotel selama dua bulan yang diterima Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan.
“Soal gratifikasi, bisa jelaskan bahwa pada waktu pindah dari Lombok ke Jakarta, menginap di hotel kurang lebih 2 bulan dan ada pihak tertentu yang membayar?” tanya Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih mengklarifikasi dugaan gratifikasi yang diterima Firli.
Di hadapan pansel capim KPK, Firli mengakui pernah menginap di sebuah hotel bersama anak dan istrinya mulai 24 April hingga 26 Juni, tanpa menyebutkan tahun. Kendati demikian, ia mengaku membayar tagihan hotel lebih dari Rp 55 juta menggunakan uang pribadi.
“Saya masih punya harga diri. Saya tidak pernah korbankan masa depan saya. Saya 35 tahun menjadi polisi tidak pernah meminta uang,” jawab Firli seperti terdokumentasikan dalam akun Youtube Kementerian Sekretariat Negara RI yang diunggah pada 29 Agustus 2019.
Selain dugaan pelanggaran etik, komitmen pemberantasan korupsi capim KPK lain juga diragukan. Keraguan ini muncul ketika sejumlah kandidat, antara lain Roby Arya Brata, Luthfi K. Jayadi, dan Nurul Ghufron ingin membekali KPK dengan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Bahkan Roby Arya, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet sesumbar tidak akan mengusut kasus korupsi di institusi Polri dan Kejaksaan.
Menurut Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada (UGM), Zaenur Rohman, pernyataan Roby berbahaya karena tidak sesuai dengan tujuan pembentukan KPK, yakni sebagai trigger mechanism.
“Institusi penegak hukum harusnya dijadikan prioritas pencegahan dan penindakan KPK,” ungkap Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada (UGM), Zaenur Rohman kepada Jaring.id Selasa, 3 September 2019.
KPK Tak Butuh Revisi
Belum surut gelombang calon pimpinan dengan rekam jejak bermasalah, di saat hampir bersamaan KPK harus menghadapi gelombang kedua, yakni pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses pengambilan keputusan untuk membahas RUU ini berlangsung tak lebih dari 10 menit. Tak ada keberatan ataupun interupsi penolakan dari anggota DPR. Pendapat setiap fraksi yang biasanya dibacakan, kali ini langsung diserahkan secara tertulis kepada pimpinan dewan.
“Apakah pendapat fraksi terhadap RUU usul Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dapat disetujui menjadi usul DPR RI?” tanya pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR Utut Adianto di Gedung Nusantara Dua, Senayan, Jakarta.
“Setuju,” jawab masing-masing anggota fraksi sebelum menyerahkan pandangan tertulis kepada Ketua DPR, Bambang Soesatyo.
Anggota DPR, Arsul Sani menjelaskan, persetujuan dewan terhadap revisi UU KPK sebagai usulan DPR merupakan kelanjutan dari pembahasan RUU yang sama pada 2016 lalu. Saat itu, DPR dan pemerintah sepakat menunda pembahasan rancangan tersebut.
Namun, Pasal 45 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa penyusunan RUU harus dilakukan berdasarkan program legislasi nasional (Prolegnas). Di luar itu, berdasarkan Pasal 23 (2) UU yang sama, DPR bisa mengajukan RUU di luar prolegnas dengan sejumlah syarat, seperti dalam keadaan luar biasa, konflik atau bencana alam. Sementara itu, rencana revisi UU KPK digulirkan dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Selasa malam, 3 September 2019.
“DPR, khususnya Baleg merasa bahwa di akhir masa (jabatan periode 2014-2019-red) inilah saatnya penundaan itu diakhiri. Tentu, kami semua harus menghormati,” jelas Arsul Sani, Kamis, 5 September 2019.
Adapun pokok pembahasan utama dalam RUU tersebut, menurut Sani, ialah terkait dengan pembentukan dewan pengawas KPK, izin penyadapan dan kedudukan KPK dalam rumpun eksekutif dan kewenangan menghentikan penyidikan perkara (SP3). Ia menargetkan, proses pembahasan RUU rampung sebelum masa tugas DPR berakhir pada akhir September mendatang.
“Percayalah, semua yang ada di DPR tidak ingin juga KPK lemah,” Arsul menyakinkan.
Ketua KPK, Agus Rahardjo tidak sepakat dengan klaim tersebut. Menurutnya, revisi UU KPK justru membuat lembaganya tergiring ke ujung tanduk. Dari 70 pasal yang dikemas DPR, sejumlah pasal diyakini Agus akan membuat KPK dependen. Pasalnya dalam draf RUU, KPK diletakkan ke wilayah kekuasaan eksekutif seperti tertera dalam Pasal 1 dan 3, sedangkan pegawainya dinyatakan sebagai pegawai negeri sipil, sehingga harus mematuhi aturan terkait aparatur sipil negara (ASN).
Selain berpotensi merusak independensi, menurut Agus, ada delapan persoalan lain yang terkandung dalam RUU KPK, yakni terkait dengan izin penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, pembatasan sumber perekrutan penyelidik dan penyidik, proses penuntutan yang perlu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, pemangkasan kewenangan strategis penuntutan, pengalihan perkara dan membatasi kewenangan KPK untuk memeriksa LHKPN.
“Hal seperti ini akan membuat kerja KPK terbelenggu dan sangat mudah diganggu berbagai pihak,” kata Agus lewat keterangan tertulis yang diterima Jaring.id, Kamis, 5 September 2019.
Itu sebab, Agus meminta Presiden Jokowi menolak pembahasan revisi UU KPK. Ia meyakini fungsi lembaganya saat ini belum perlu diubah sebagaimana yang diinginkan DPR.
“RUU KPK inisiatif DPR tidak akan mungkin dapat menjadi undang-undang jika presiden menolak dan tidak menyetujui RUU tersebut,” pungkas Agus Rahardjo. (Abdus Somad/Damar Fery Ardiyan)