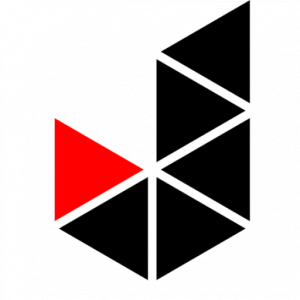Lima tahun terakhir Willy Wicaksono bermukim di Kota Ambon. Ia memimpin program Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) yang diinisiasi oleh The United States Agency for International Development (USAID). Program ini berdurasi lima tahun dan dijalankan di Maluku, Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur. Namun tahun ini merupakan akhir dari seluruh kegiatan yang digelar APIK.
“Kami tutup enam bulan lebih cepat dari jadwal,” ujar Willy, Senin 20 Januari 2020.
Program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang digelar APIK, seperti sekolah lapang iklim bagi petani dan nelayan tak lagi mendapat suntikan dana. Ini menyusul setelah Amerika Serikat memutuskan angkat kaki dari Paris Agreement.
“Membangun ketangguhan memang tidak mudah, tetapi masyarakat Maluku punya modal kuat untuk beradaptasi,” tegas Willy.
Modal yang dimaksud Willy adalah tradisi dan kearifan lokal. Orang-orang Maluku dapat membaca tanda-tanda alam, sehingga mereka bisa menentukan kapan harus memulai masa tanam dan kapan mesti melaut. Namun, menurut Willy, praktik pola tanam yang dijalankan petani Maluku selama ini belum memenuhi standar ilmu pertanian.
Tanda Alam
Bagi masyarakat Maluku, gelegar gemuruh selama tiga malam berturut-turut merupakan pertanda perubahan musim dari hujan ke kering. Kondisi demikian yang membuat para petani bersiap meladang. Sementara jika awan terlihat bersisik seperti ikan—dalam bahasa lokal disebut awan basisik—memberi tanda dimulainya musim tangkap. Pengetahuan ini diwariskan turun temurun dan sudah dipraktikkan selama ratusan tahun.
“Kami menyebutnya nanaku. Kami ini ya petani tetapi sekaligus nelayan. Jadi harus bisa melihat tanda-tanda iklim,” tutur Imron Soumena (49), petani sekaligus sekretaris desa Negeri Lima, Maluku Tengah, Selasa 21 Januari 2020.
Selain nanaku, petani Maluku juga mengenal istilah dusung atau teknik budidaya polikultur yang mana dalam satu lahan terdapat pelbagai jenis tanaman. Selain rempah dan umbi-umbian, masyarakat kerap mengombinasikan area tanam dengan pohon buah manggis maupun durian. Menurut guru besar etnobotani dari Universitas Pattimura, Marcus Pattinama, praktik dusung ini telah membantu petani Maluku bertahan hidup saat panen cengkeh atau pala sedang seret.
“Dusung ini semacam praktik agroforestri ala orang Maluku,” ujar Marcus, Kamis 23 Januari 2020.
Namun menurut Imron Soumena, tanda-tanda alam yang sebelumnya ampuh menjadi petunjuk siklus tanam maupun melaut, kini tak lagi bisa diandalkan. Perubahan iklim membuat nanaku tidak 100 persen akurat.
“Kalau kita pikir sudah masuk musim tanam, ternyata malah hujan terlalu lebat malah merusak tanaman,” keluh Imron.
Di sinilah peran sekolah lapang iklim yang digagas USAID APIK jadi sangat krusial. Program ini mengombinasikan kearifan lokal dan data saintifik yang disediakan oleh Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika. Petani di Maluku jadi dapat membaca tanda-tanda perubahan iklim dengan lebih akurat.
Di samping itu, APIK juga membantu petani melakukan proses produksi pascapanen. Pasalnya, metode pengeringan bunga cengkeh yang hanya mengandalkan panas matahari tidak lagi efektif. Bila cuaca terik, proses penjemuran hanya butuh waktu dua hari. Namun ketidakpastian cuaca seringkali menghambat proses ini. Sebagai gantinya, menurut Maun Kusnandar, Community Specialist USAID APIK Maluku, petani sebetulnya bisa melakukan pengasapan terhadap bunga cengkeh. Namun proses tersebut dapat menekan kualitas cengkeh. Hal ini yang mengakibatkan harga cengkeh di pasaran anjlok.
“Kami mendorong agar masyarakat menggunakan solar dryer untuk mengeringkan cengkeh saat cuaca tidak mendukung,” ungkap Maun Kusnandar, Selasa 21 Januari 2020.
Solar dryer ialah alat sederhana seharga Rp 400 ribu yang dapat membantu proses pengeringan cengkeh. Berbentuk seperti keranda dengan lapisan plastik UV 6 persen. Menurut Maun, proses pengeringan menggunakan alat ini lebih efisien dan tidak mengorbankan kualitas cengkeh. Selain tidak berkerut, cengkeh yang dikeringkan melalui proses solar dryer berwarna coklat tua dengan aroma yang lebih kuat.
“Kalau kita jemur di atas terpal bunga cengkeh cenderung berwarna hitam dan susut. Aromanya juga berkurang,” cerita Apik Soulisa, petani cengkeh Negeri Lima, Rabu 22 Januari 2020.
Meski begitu, Apik menyesalkan belum dapat menjangkau seluruh desa di Maluku. Selama ini lembaganya baru menyalurkan 40 unit solar dryer ke beberapa desa.
Peta jalan ketangguhan
Selama lima tahun beroperasi di Maluku, APIK hanya bisa menjangkau 12 desa. Padahal di provinsi ini terdapat 1.200 desa yang juga menghadapi masalah perubahan iklim. Potret masalah ini terekam dalam laporan kerentanan iklim Provinsi Maluku yang diterbitkan USAID APIK pada 2018. Laporan yang berbasis data historis iklim Maluku selama 30 tahun terakhir ini memproyeksikan perubahan iklim yang dapat terjadi di masa depan. Dalam riset tersebut, data historis iklim di Ambon menunjukkan curah hujan selama periode 1981-2010 cenderung mengalami kenaikan.
“Catatan kejadian bencana di Provinsi Maluku selama seratus tahun terakhir menunjukkan bencana terkait iklim merupakan bencana yang paling sering terjadi dan paling banyak menyebabkan kerugian,” tulis para peneliti dalam laporan tersebut.
Dua peniliti dalam riset tersebut ialah Gene Junnaedhi dan Tri Laksono dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Mereka memproyeksikan bahwa iklim Maluku hingga 2025 akan mengalami peningkatan suhu. Keduanya menggunakan hasil statistical downscaling dari IPCC Global Climate Model yang menunjukkan skenario kenaikan suhu udara antara 0,5⁰C sampai 1,5⁰ C.
“Grafik proyeksi rata-rata suhu tahun 2025 menunjukkan Maluku mengalami kecenderungan naik di suhu minimum yang menandai bahwa wilayah ini telah terindikasi terjadi perubahan iklim,” tulis keduanya dalam laporan tersebut.
Laporan ini menjadi modal penting bagi pemerintah Provinsi Maluku untuk membangun strategi adaptasi dan mitigasi iklim yang berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan agar potensi sumber daya alam dan keanekarahaman hayati yang tersebar di 1.340 pulau tidak rentan terhadap perubahan iklim. Kepala Bidang Ekonomi Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Ilham Tauda mengklaim bahwa isu perubahan iklim sudah tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024.
“Kami adalah pemerintah daerah pertama yang memiliki roadmap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam hal upaya pembangunan berkelanjutan,” ujar Ilham Tauda, Senin 21 Januari 2020.
Peta jalan (roadmap) yang dirilis pada 2017 ini berisi langkah-langkah taktis dan strategis agar Maluku dapat menghadapi ancaman perubahan iklim. Pasalnya, menurut Ilham, dampak anomali cuaca kian nyata dirasakan masyarakat Maluku. Antara lain terhadap sektor perikanan, pertanian dan perkebunan, serta transportasi laut. Oleh sebab itu, menurut Ilham, masyarakat Maluku perlu punya pendekatan ekonomi lain.
“Dari sisi anggaran saja APBD kita sangat tidak mencukupi,” ujarnya.
Belanja anggaran tahunan Maluku berkisar Rp3,2 triliun, di mana 60% di antaranya habis untuk belanja langsung dan tidak langsung. Sisanya diperuntukkan bagi sektor pendidikan (20%) dan kesehatan (10%).
“Anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim disebar di beberapa sektor yang jumlahnya sangat kecil,” tambah Ilham.
Menyiasati hal tersebut, pemprov Maluku berupaya mengajukan anggaran khusus pembiayaan program-program unggulan, seperti restorasi lahan gambut dan revitalisasi kebun cengkeh kepada pemerintah pusat.
“Kami juga sedang menjalin kerjasama dengan lembaga donor internasional,” cerita Ilham.
Menggagas peta jalan perubahan iklim bisa dianggap langkah yang inovatif dari pemerintah Maluku. Namun entah berapa lama lagi masyarakat Maluku dapat meraup untung dari limpahan aroma harum cengkeh.
“Menghadapi perubahan iklim ini kita berkejaran dengan waktu,” kata Ilham.
*Tulisan ini merupakan bagian kedua dari liputan yang didukung dana hibah oleh Earth Journalism Network dan Resource Watch, organisasi nirlaba yang fokus pada penelitian di bidang keberlanjutan.