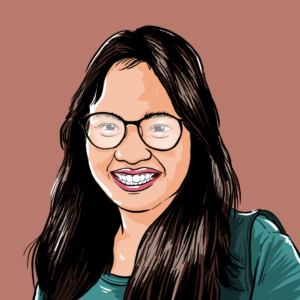Pemerintahan Myanmar yang dikuasai Jenderal Militer Min Aung Hlaing memberlakukan darurat militer di sejumlah daerah, seperti di Mandalay—kota terbesar kedua di Myanmar pada Senin, 8 Februari 2021. Ini merupakan respon militer terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat beberapa hari sebelumnya. Pada unjuk rasa akhir pekan lalu di Yangoon, para demonstran berbondong-bondong mengenakan pakaian warna merah—warna yang identik dengan partai bentukan Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). “Kami akan terus bergerak, terus menuntut hingga kami mendapatkan demokrasi. Akhiri kediktatoran militer ini,” ujar salah satu pengunjuk rasa, Myo Win, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia, Minggu, 7 Februari 2021.
Dengan dalih keselamatan warga, Jenderal Min Aung Hlaing melarang warga berunjuk rasa, berkumpul dengan jumlah lebih dari lima orang, dan meneruskan pemberlakuan jam malam mulai Pukul 8.00 malam sampai 4.00 pagi waktu setempat. Pihak militer juga tak segan membatasi akses masyarakat terhadap internet, jaringan telepon, siaran televisi dan radio. “Perintah ini akan berlaku hingga waktu yang belum ditentukan,” demikian pernyataan pers pemerintah Myanmar di Mandalay, Senin 8 Februari 20 21.
Pemerintah Myanmar mengklaim bahwa unjuk rasa yang menuntut militer menerima hasil pemilu, membebaskan Penasihat Negara, Aung San Suu Kyi dan menjalankan demokrasi tersebut sudah mengkhawatirkan. “Itulah kenapa perintah ini melarang warga berkumpul, berbicara di publik, ataupun berdemo dengan mobil,” demikian pengumuman pemerintah.
Direktur Women Peace Network, Wai Wai Nu menilai pembatasan akses informasi di Myanmar telah merugikan masyarakat. Saat ini, masyarakat berada di tengah rumor yang sulit untuk dikonfirmasi. Salah satu kabar yang beredar ialah tentang penyiapan penjara-penjara oleh pihak militer. Kata Wai Nu, rumor yang berkembang mengakibatkan warga yang punya pengalaman buruk ditekan pemerintahan diktator, seperti masyarakat Rohingnya di Rakhine panik. “Di Rakhine jaringan terputus, sangat sulit menghubungi mereka. Dan mereka sangat ketakutan bagaimana dengan nasib mereka selanjutnya,” kata Wai Nu dalam siaraan pers bertajuk Myanmar Military Coup’s Implications on Human Rights and Democracy pada Selasa, 2 Februari 2021 melalui aplikasi Zoom.
Hingga Selasa, 9 Februari 2021, kondisi di Myanmar semakin mencekam. Demonstrasi yang dilakukan masyarakat direspon dengan aksi represif oleh aparat di Ibu Kota Naypytaw. Seorang pengunjuk rasa wanita bahkan dilaporkan tertembak di kepala. Mengutip AFP, demonstran perempuan yang ditembak tersebut berusia 20 tahun.
Wai Nu menilai bahwa kondisi tersebut tentu akan memperburuk kondisi masyarakat di Maynmar. Utamanya minoritas yang selama kepemimpinan Suu Kyi tidak banyak mengalami kemajuan. Kudeta militer, menurutnya, akan berdampak pada proses rekonsiliasi. “Bagi saya, ini bukan tentang Aung. Tetapi tentang kediktatoran militer dan kudeta itu sendiri. Kami tidak ingin orang-orang di Myanmar dan Rohingnya ada di bawah rejim diktator. Kami menentang diktator militer dan meminta dukungan kalian,” ujar Wai Nu.
Dia berharap masyarakat international turut mengecam dengan keras situasi di Myanmar. Sanksi berupa embargo militer, serta pembatasan terhadap rekan bisnis militer dinilai mampu menekan Jenderal Min Aung Hlaing.
Ketua Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, Charles Santiago sependapat dengan Wai Nu. Selain embargo senjata, menurutnya, penutupan akun bank militer dan segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit akan efektif dilakukan. “Harus ada tindakan konkret menekan pemerintah Myanmar saat ini,” ujar Charles.
Sejauh ini, tidak sedikit petinggi negara dan organisasi internasional yang mengecam kudeta yang diakukan Militer Myanmar. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menyebut akan memobilisasi tekanan internasional untuk memastikan kegagalan kudeta militer di Myanmar. Sedangkan organisasi Amnesty Internasional mendesak agar pemerintah segera membuka akses telekomunikasi. Wakil Direktur Regional untuk Kampanye Amnesty International, Ming Yu Hah tidak ingin keputusan militer menempatkan warga pada risiko yang lebih besar dari pelanggaran HAM. “Menutup internet di tengah kudeta yang tidak menentu, krisis kemanusiaan dan pandemi kesehatan adalah keputusan yang keji dan sembrono,” ujar Ming Yu Hah dalam siaran pers yang diterima Jaring.id pada Sabtu, 6 Februari 2021.
Sementara itu, Indonesia menyerukan agar militer Myanmar mengikuti piagam ASEAN dan Deklarasi HAM ASEAN. Piagam ASEAN menyebut kepatuhan terhadap aturan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan HAM, dan menghormati kebebasan mendasar.
Sebelumnya, lewat saluran televisi Militer Myawaddy Television, Militer Myanmar mengumumkan masa darurat pemerintahan selama setahun ke depan terhitung sejak Senin, 1 Februari 2020. Pengumuman itu diikuti pengambilan kekuasaan dari pemerintah sipil ke tangan Jenderal Militer Myanmar Min Aung Hlaing. Pengumuman dilakukan usai militer menangkap sejumlah pemimpin sipil, seperti penasihat negara sekaligus pimpinan partai National League for Demokrat (NLD) Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint serta sejumlah anggota legislatif terpilih dari NLD pada Senin dini hari.
Kudeta militer Myanmar berpangkal dari tudingan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) Myanmar yang digelar 8 November 2020 lalu. Dalam pernyataan yang dibacakan melalui televisi Myawaddy, dikutip Reuters, kelompok militer menemukan selisih daftar pemilih yang disusun Komisi Pemilihan Umum (UEC). Kelompok militer mengklaim bahwa UEC gagal menyelesaikan dugaan kecurangan dalam penyusunan daftar pemilih.
“Untuk melakukan pemeriksaan terhadap daftar pemilih dan untuk mengambil tindakkan, kewenangan pembuatan hukum negara, pemerintahan dan yurisdiksi diserahkan kepada panglima tertinggi sesuai dengan Konstitusi 2008 Pasal 418,” demikian pernyataan Militer.
Penolakan terhadap hasil pemilu juga gencar disuarakan partai oposisi yang didukung Militer, Union Solidarity and Development Party (USDP). Mereka mendukung militer untuk terlibat memastikan proses pemilihan dengan adil dan transparan. Mereka bahkan mendorong pemilihan ulang. Padahal berdasarkan perhitungan UEC, NLD sudah memenangkan 396 kursi dari total 479 kursi di parlemen rendah dan tinggi. Jumlah ini setara dengan 83 persen kursi parlemen.
UEC melalui laman resminya membantah kecurangan yang diakibat kesalahan daftar pemilih. Pasalnya penyusunan daftar pemilih dilakukan terbuka dan melibatkan banyak pihak, antara lain Departemen Administrasi Umum dan Kementerian Imigrasi. Daftar pemilih tersebut juga telah diperbarui setiap bulan dan diumumkan kepada warga agar bisa mengoreksi kesalahan terkait identitas. Proses koreksi ini dilakukan selama tiga pekan, mulai Juli-Agustus 2020.
Daftar pemilih juga bisa diakses lewat laman findyourpollingstation.uec.gov.mm serta aplikasi selulerfindyourpollingstation.apk. Kepada calon peserta pemilu di masing-masing kecamatan, daftar pemilih bahkan didistribusikan dalam kepingan cakram padat (compact disc). “Itu secara transparan didistribusikan ke partai politik untuk memberikan dukungan yang diperlukan untuk daftar pemilih,” kata UEC dalam pernyataan resminya pada 28 Januari 2020.
Jika masih terdapat ketidakpuasan dalam proses pemilu, UEC mengimbau agar keluhan disampaikan kepada Pengadilan Pemilihan. Pengadilan akan memeriksa seluruh dokumen, termasuk daftar pemilih di depan kedua belah pihak yang bersengketa. Sejauh ini, UEC sudah menangani 287 aduan keberatan dengan 94 di antaranya kasus pemilih dan 193 kasus terkait calon legislator.
Sebanyak 12 Lembaga pemantau pemilu di Myanmar menyebut bahwa sengketa suara pada pemilihan lalu terkendala kurangnya kerangka hukum penyelesaian perselisihan pemilu. Pengamat juga menyoroti lemahnya implementasi penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi COVID-19. Kelompok pemantau menyerukan agar seluruh pihak mengedepankan dialog dan diskusi serta perlunya mengubah kerangka hukum pemilu ke depan.
“Kami mendesak semua partai politik lain dan Tatmadaw untuk menghormati hasil pemilu dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang berbeda untuk memastikan stabilitas pasca pemilu dan transisi kekuasaan yang damai,” seperti tertulis di laman People Alliance for Credible Electoral pada 29 Januari 2020.
Khin Omar, Ketua Progresive Voice—organisasi pejuang HAM di Myanmar menilai militer telah memanfaatkan isu kecurangan pemilu untuk merebut tampuk kekuasaan yang sah. Kudeta ini tidak lepas dari hasil Pemilu 2020 di mana kelompok militer kehilangan kekuatan di pemerintahan. Situasi ini tak jauh berbeda dengan hasil pemilihan sebelumnya ketika mayoritas masyarakat Myanmar memilih NLD lewat pemilu 1999 dan 2015.
“Sangat mengejutkan karena mayoritas dimenangkan NLD. Sehingga ini (kudeta) ditujukan untuk menghentikan anggota parlemen terpilih menjalankan pemerintahan,” ujarnya dalam konferensi pers pada Selasa 2 Februari 2020.
Lebih jauh, Khin melihat bahwa kudeta militer dipengaruhi motif pribadi dari Panglima Militer Myanmar, Min Aung Hlaing. Pasalnya dalam lima bulan ke depan, Min akan memasuki masa pensiun. Dengan kemenangan telak NLD, maka ia akan segera kehilangan kontrol terhadap pemerintahan dan parlemen. Kondisi ini tentu disebut tidak bagus bagi bisnis militer yang berlangsung sepanjang transisi demokrasi Myanmar. “Dalam sepuluh tahun terakhir adalah militer dan anggota keluarganya serta kroni bisnisnya yang paling diuntungkan dari “Demokrasi Transisi” Myanmar,” ujar Khin.