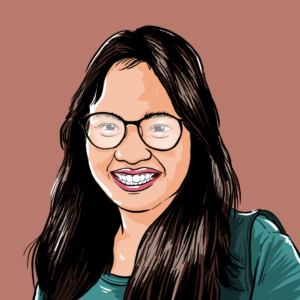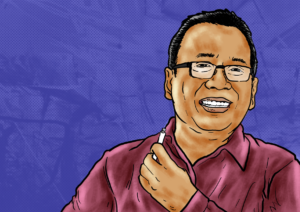Penggunaan ruang digital oleh kontestan pemilihan umum tak terelakkan dalam kondisi pandemi. Beberapa negara mencpba menerapkannya, termasuk Indonesia. Namun, hal tersebut bukan tanpa cela. Di Singapura, partai oposisi dijerat oleh Undang-Undang Antihoaks. Sementara itu, petahana di Sri Lanka punya keuntungan memanfaatkan infrastruktur media sosial untuk berkampanye.
Kondisi Indonesia tidak jauh lebih baik. Salah satu penyebabnya adalah massifnya penggunaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk memejahijaukan kritik. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat terdapat 285 kasus pemidanaan dengan menggunakan aturan ini dalam periode 2008-2019. Kondisi pandemi memperparahnya. Sejak wabah Covid-19 terdapat 110 tersangka yang dijerat UU ITE. Dari jumlah tersebut, 38 pelapornya merupakan pejabat publik seperti kepala daerah, kepala instansi, menteri dan aparat keamanan.
Tom Gerald Daly, Assosiate Professor Melbourne University, dalam kuliah daring bertema “Apakah Kampanye Jarak Jauh dan Kampanye Online menjamin Kebebasan Politik,” menyatakan bahwa kampanye daring rawan dijadikan sarana bagi kekuasaan untuk menjerat lawan politik. Jaring.id merangkum kuliah daring yang dihelat pada Rabu, 14 Oktober 2020 tersebut.
Tantangan melangsungkan pemilu di tengah pandemi
Pertama hambatan fisik menjangkau pemilih dengan terbatasnya aktivitas kampanye yang boleh dilakukan. Masih sulit meninggalkan cara kampanye lama. Mungkin kita punya alat kampanye daring, tetapi ada keterbatasan jangkauan dan akses terhadap kampanye daring baik oleh kandidat dan publik.
Kedua, Anda mungkin melihat disparitas teknologi dan akses terhadap teknologi di berbagai negara. Dalam satu negara saja sudah ada perbedaan kemampuan dan akses. Ketiga, saat ini tren tidak dilibatkannya publik dalam pengambilan kebijakan semakin menguat selama pandemi. Keempat, sejumlah negara mengalami kemunduran dalam penyampaian informasi terutama media lokal sebagai dampak pandemi.
Kelima, misinformasi dan disinformasi semakin tinggi karena pandemi. Keenam, sulitnya menjangkau publik untuk sosiaslisasi regulasi aturan pemilu. Ketujuh, menguatnya negara untuk membungkam kritik. Kedelapan, kita khawatir partisipasi pemilih turun.
Tentu tantangan ini berbeda-beda terutama untuk kawasan Asia Pasifik yang sangat beragam menurut ukuran negaranya, perbedaan pendapatan, kemampuan negara dan sebagainya. Dan itu berdampak pada penanganan pandemi dan pemilu. Beberapa negara ada yang mampu mengendalikan pandemi sebelum pemilu dimulai seperti Korea Selatan, Selandia Baru, serta Kaledonia Baru. Akan tetapi ada yang menunda hingga dua kali seperti Sri Lanka.
Kunci sukses Korea Selatan melangsungkan Pemilu
Korea Selatan salah satu negara yang pertama kali menyelenggarakan pemilu di tengah minimnya referensi pemilu saat pendemi. Korea Selatan tidak hanya sukses melangsungkan pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga menunjukkan inovasi dan partisipasi yang tinggi. Pertama, pendekatan Korea Selatan adalah membangun kepercayaan publik bahwa penyelenggaran pemilu menjamin keselamatan pemilih.
Kedua, transparansi lewat ragam informasi daring untuk menggapai kandidat dan pemilih. Ketiga adanya aturan jelas apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan kandidat saat kampanye. Keempat, inovasi kandidat melakukan kampanye daring menggunakan video, aplikasi, dan media sosial. Kelima, pemilihan dini menguntungkan Korea Selatan agar semakin banyak orang menggunakan hak pilihnya. Terakhir adanya aturan keselamatan yang jelas dan efektif saat pemungutan suara.
Selain berhasil melandaikan kurva sebelum pemilu, Korea juga diuntungkan tingginya kualitas demokrasi, kapasitas pemerintahan, aparatur pemerintahan yang beradaptasi dengan teknologi, dan tingginya akses internet yang mencapai 95 persen populasinya.
Selain Korea Selatan, Mongolia juga salah satu negara yang sukses menggelar pemilu di masa pandemi. Mereka berhasil mengatasi pendemi dengan angka kematian 0. Mereka menduplikasi praktik kampanye yang dilakukan di Korea Selatan. Meskipun tingkat penetrasi internet Mogolia hanya 20 persen, tetapi berhasil mendapat partisipasi (pemilu) tinggi sebesar 73 persen.
Pemerintah dan Teknologi
Anda tidak bisa serta merta menerapkan apa yang ada di Korea Selatan, misalnya mengalihkan semua pertemuan tatap muka ke dalam jaringan dan aplikasi. Dalam konteks politik, terjadi penghilangan kritik di laman-laman oposisi atau medium informasi terbuka. Itu menjadi masalah serius. Semakin daring, semakin pemerintah mampu menjangkau perilaku-perilaku ini.
Kita sudah melihat ini dilakukan di negara yang punya perjalanan demokrasinya buruk, seperti Hungaria. Pemerintah membangun situs pengecekan berita bohong, tetapi apa yang sebetulnya mereka lakukan adalah menyerang politisi oposisi. Anda bisa melihat mekanisme itu sangat mudah dilakukan di periode pemilu, dalam konteks terkonsentrasinya kekuatan di pemerintah. Kita melihat itu terjadi di Sri lanka, itu masalah serius.
Pandemi dan Otoritarianisme
Selama pandemi, kita melihat intensifikasi tren yang sudah ada. Pandemi bukan penyebabnya, tetapi pandemi mengakselerasinya. Contohnya tekanan terhadap suara oposisi menguat selama pandemi. Kami melihat semakin kuat dan jelas bentuknya selama pandemi. Saya mengatakannya beberapa negara menjadi otokrasi oportunis dan beberapa pemerintah memanfaatkan situasi sekarang untuk melanggengkan situasi buruk. Jika kamu punya sejarah perlawanan politik kuat yang merangkul teknologi daring, tentu situasinya tidak akan mudah memburuk. Di Korea Selatan, ada penerimaan lebih luas terhadap sumber terbuka (open source) dan open goverment. Sama halnya dengan Taiwan. Itu justru menguntungkan mereka di era pandemi dengan semakin meningkatkan tren baik bagi mereka.
Kampanye daring
Kasus di Mongolia menjadi satu hal yang perlu diteliti lebih jauh. Apakah benar media sosial berdampak terhadap partisipasi pemilu di sana? Kita memang melihat banyak informasi di Twitter tapi itu belum cukup. Saya selalu khawatir kita terlalu memberikan sudut pandang positif terhadap penggunaan teknologi dan terkadang sangat bersandar pada kepercayaan terhadap teknologi ketimbang kenyataan sebenarnya. Selain isu kebebasan politik, perlu disinggung kesetaraan. Beberapa orang punya akses internet yang baik dan yang lain tidak. Beberapa orang tidak punya akses ke forum publik yang sudah terdigitalisasi. Ini menjadi masalah besar dengan rendahnya akses ke internet.
Saya punya perasaan campur aduk tentang kampanye dalam jaringan. Salah satu hal contoh baik adalah Korea Selatan dan kita berharap bisa direplikasi. Saat ini, kampanye dalam jaringan dilihat sebagai hal yang baik, tetapi kita juga harus seimbang dan terbuka melihat kemungkinan buruk dan juga peluang lain. Isu ini tidak akan menghilang begitu saja, bahkan ketika pandemi sudah usai. Kampanye daring akan selalu hadir dengan beragam permasalahannya.
Harapannya adalah potensi kekerasan mengecil seiring dengan sedikitnya kontak fisik. Namun, di saat yang sama, WHO mengingatkan soal infodemic pada April lalu. Ini bukan hanya soal semakin banyaknya berita palsu atau rumor, tetapi juga kasus pengambinghitaman beberapa komunitas minoritas seperti yang terjadi di India. Mereka dituding tidak menerapkan aturan jaga jarak untuk meminimalisir penularan Covid-19. Ada juga ujaran kebencian yang membuat situasi menjadi sulit, terutama ketika terjadi dalam periode pemilu.
Meregulasi media sosial
Kita tahu platform media sosial sangat resisten terhadap ide meregulasi ucapan di platform mereka. Isu regulasi sangat problematik, khususnya ketika diletakkan dalam konteks usaha pemerintah untuk menekan kebebasan berpendapat. Brazil misalnya, baru saja mengesahkan Undang-Undang Berita Palsu dan membuat media sosial bertanggung jawab terhadap apapun yang ada di platform mereka. Mereka harus melapor, mengubah komunikasi, dan ada kekhawatiran penyalahgunaan aturan ini untuk melakukan sensor. Teknologi raksasa enggan diregulasi ketika sejumlah regulasi memang diperlukan. Namun, ada juga kekhawatiran soal regulasi berlebihan apabila aturan dibuat dengan tidak hati-hati.
Pelajaran dari pandemi
Pertama, menormalisasi pengawasan teknologi untuk melacak individu dengan tujuan komersial atau politik. Ada target mikro, efek gema, kabar bohong, serta fragmentasi informasi yang membuat realitas berbeda. Itu salah satu masa depan yang kita lihat.
Kedua, apa yang kita lihat di Korea Selatan adalah teknologi bersifat netral. Sekadar alat yang bergantung pada bagaimana ia digunakan. Ada banyak cara memanfaatkan teknologi, seperti Taiwan dengan teknologi crowdsource, open source, dan desentralisasi informasi. Hal ini bisa didorong dalam konteks pemilu misalnya dengan buletin daring. Pengalaman berbagi informasi yang jauh dari konsentrasi kekuatan eksekutif semoga bisa dilihat dengan cara yang berbeda di masa depan.
Teknologi dan partisipasi politik
Kita masih melihat ke jenis partisipasi politik dalam bentuk keanggotaan partai, jumlah perolehan suara, dam partisipasi pemilih. Partisipasi itu sendiri berubah. Change.org misalnya, membuat survei yang menunjukkan peningkatan jumlah orang yang menandatangani petisi daring hingga 81 persen selama pandemi. Padahal, beberapa tahun belakangan ada narasi penurunan partisipasi dan menjauh dari politik. Jadi saya pikir kita harus memperluas bentuk keterlibatan publik.
Akan tetapi kita juga harus kembali ke bentuk kampanye tradisional. Bagaimanapun satu hal yang disadari dari pandemi adalah posisi kita sebagai hewan sosial yang perlu konteks dukungan fisik. Kita perlu ada di satu tempat bersama-sama secara fisik, merasakan sebagai komunitas manusia yang tidak bisa disimplikasi atau didigitalisasi. Kampanye daring sangat berguna, tetapi kita harus memikirkannya sebagai alat tambahan yang tidak menggantikan bentuk sebelumnya.