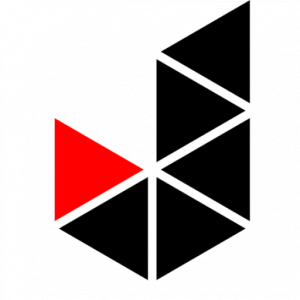TEPAT di Hari Demokrasi Internasional, Kamis, 15 September 2022, kelompok transgender masih tersingkir dari politik Indonesia. Belasan ribu transpuan, atau bahkan lebih, kehilangan hak pilih bersamaan dengan tercerabutnya identitas mereka sebagai warga negara Indonesia. Berulang kali hingar-bingar pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah menjadikan mereka hanya sebagai penonton, penghibur, atau bahkan komoditas propaganda. Kelompok minoritas ini adalah sebenar-benarnya korban di negara—yang katanya—demokratis.
Selama tiga bulan, sejak Juni 2022, Koran Tempo dan Jaring.id berkolaborasi dalam peliputan khusus untuk melihat lebih dekat situasi yang dihadapi transpuan di sejumlah daerah. Tim kolaborasi bertemu mereka di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur. Wawancara jarak jauh juga dilakukan bersama tokoh penggerak komunitas transpuan di Jawa Barat, Bali, hingga Aceh. Laporan pada edisi kali ini menjadi bagian pertama dari dua seri publikasi liputan khusus tentang transpuan di pusaran politik.
Kolaborasi peliputan tersebut terselenggara berkat dukungan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan The Asia-Pacific Regional Support for Elections and Political Transitions (RESPECT). Program tersebut juga melibatkan Philippines Center for Investigative Journalism (PCIJ) dan Lafaek News (Timor Leste).
***
Pukul enam seperempat di Desa Habi, Kangae, Sikka, Nusa Tenggara Timur udara masih terasa dingin. Suhu di dalam rumah sekitar 23 derajat celcius. Pagi itu, belum tampak masyarakat beraktivitas, kecuali Hendrika Mayora Victoria, transpuan yang sudah sejak 2018 lalu memilih identitas gendernya. Di tahun yang sama ia membentuk Fajar Sikka, sebuah organisasi transpuan di Kabupaten Sikka.
Sekretariat Fajar Sikka berukuran sekitar 40 meter persegi. Hanya sebagian dari dinding yang dilapisi cat. Sementara palang kayu tampak kokoh menopang atap berbahan asbes. Dari dalam rumah berlantai tanah ini Mayora menjalankan kegiatan sehari-hari. Sedari pagi ia wara-wiri seakan-akan tak peduli akan dingin saat menyiapkan pelbagai barang termasuk alat rias, seperti lipstik, bedak, dan spons berbentuk segitiga atau beauty blender. Saat semuanya rampung dikemasi, ia lama duduk di hadapan cermin. Pelan-pelan pergelangan tangannya menyapu kuas di seluruh area wajah. Saat gincu berwarna merah tuntas dipulas, ia memeriksa hasil riasan itu dengan mendongak kiri dan kanan.
Hari itu, Kamis, 21 Juli 2022, bukan hari yang biasa bagi Bunda Mayora—sapaan akrabnya. Ia hendak melakukan pendataan awal terhadap transpuan ke Kampung Adat Wologai, Desa Jopu, Ende yang berjarak 111 kilometer atau sekitar 3 – 4 jam perjalanan menggunakan mobil dari rumahnya. “Saya belum pernah ke sana,” ujar singkat Mayora kepada Jaring.id dan Tempo bergegas menumpangi mobil Avanza.
Kampung Adat Wologai merupakan salah satu daerah perbukitan di NTT. Jaraknya sekitar 43 kilometer dari pusat Kota Ende. Dari 900an jiwa penduduknya, menurut Mayora, ada sekitar 30 transpuan di Desa Jopu. Lima diantaranya berada di Kampung Adat Wologai. Dari jumlah itu hanya satu orang yang memiliki KTP. Artinya, kata Mayora, layanan sosial lainnya, seperti jaminan kesehatan termasuk hak pilih mereka pada gelaran pemilihan umum pun kandas akibat selembar dokumen kependudukan. “Kalau kami tidak melakukan pemetaan kami tidak tahu,” ujarnya, yang sejak pertengahan 2020 terpilih menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Habi, Sikka.
“Sebelum ke sini, kami lakukan pemetaan di pulau terluar Flores terhadap gender minoritas. Sayang sekali pulau terpisah dari Sikka. Listriknya pun pakai tenaga surya. Tapi saya sudah bertemu tokoh kunci. Kami akan melakukan pendataan lagi,” ia melanjutkan.

Kunjungan perdana ke Desa Jopu membuka mata Mayora mengenai kondisi transpuan yang tinggal di kaki Gunung Kelimutu. Sekalipun tidak semuanya bisa ditemui hari itu karena terhambat masalah kesehatan. “Perjumpaan awal di Jopu adalah hal baik,” tuturnya.
Jerih payah ini dilakukan Mayora guna memastikan hak-hak transpuan NTT sebagai warga negara, termasuk dalam politik. Terlebih Indonesia akan menggelar Pemilu 2024. Ia tidak ingin para transpuan hanya jadi penonton atau penggembira seperti yang sempat ia alami pada 2019 lalu. Fajar Sikka tengah merancang kegiatan pemetaan bertujuan untuk mengurus KTP secara kolektif. “Saya tidak punya identitas pada 2018, sehingga pada 2019 tidak memilih. Jujur, saat itu saya tidak punya KTP karena kabur dari rumah,” kisahnya.
Pendataan sementara Fajar Sikka, di wilayah Maumere terdapat sekitar 300 transpuan. Dari jumlah itu, baru sekitar 100 transpuan yang beroleh KTP. Sebagian besar dari mereka tidak menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2019. Pasalnya, salah satu syarat pemilih di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ialah memiliki KTP. Aturan terakhir ini yang tidak dimiliki Mayora dan transpuan lain di NTT.
Hilang Suara karena Berbeda
Sekitar September 2018 atau 8 bulan sebelum pemilihan presiden, wakil presiden, dan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) April 2019 lalu, Mayora pontang-panting menelusuri satu dusun ke dusun lain di Desa Habi untuk menyokong pemenangan salah satu pasangan calon. Berangkat pagi hari, lalu pulang jelang malam. Saat itu, ia gencar menyerukan kader salah satu partai besar kepada warga. “Saya master of ceremony di kampung-kampung pakai motor. Saya memperkenalkan. Inilah sosok kita,” kata Mayora yang saat itu mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf.
Namun tiga tahun setelah hiruk-pikuk itu usai, Mayora kembali merasa tersisih. Padahal sebelumnya, kelompok transpuan di sana diiming-imingi kemudahan ketika mengurus hak dasar, beroleh KTP, jaminan sosial, dan kesehatan. “Kami dijadikan alat untuk mendapatkan suara sendiri. Apakah kami diperhatikan? No way. Mungkin mereka sibuk. Mereka lupa dengan masyarakatnya,” ujar Mayora.
Kenyataan pahit serupa dialami Lola Pitaloka, transpuan asal Desa Bola, Kecamatan Bola, Sikka. Pada Pemilu 2019, ia berkeliling ke Kabupaten Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Nagekeo. “Setiap kampanye selalu digunakan. Saya ke desa-desa. Desanya se-Maumere. Kami dikontrak nyanyi sampai selesai. Sampai habis kampanye,” kata Lola.
“Tapi hasilnya (janjinya) tidak pernah ada. Percuma pilih. Habis dapatkan kursi, mobil kaca tutup rapat-rapat,” lanjutnya dengan suara parau.
Sementara salah satu transpuan yang didata Mayora ialah Vincensius Laperlaka. Panggilannya Inces. Sedari lahir ia tinggal di Desa Jopu, karenanya ia piawai menyulam benang menjadi kain khas daerah itu. Di sana ia tinggal bersama tiga saudara dan ibu yang telah lanjut usia. “Pekerjaan pokok saya adalah membuat tenun ikat,” ujar Inces lantang di rumahnya yang beralas tanah, beratap jerami, dan berdinding anyaman bambu.
Sebagai penopang utama ekonomi keluarga, Inces bisa memproduksi satu tenun ikat berukuran 1×2 meter tiap dua pekan. Hasilnya dijual seharga Rp 500 ribu – 1 juta. Produksi tenun ikat bisa berhenti tatkala Inces diminta untuk menjadi relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf. Sebab di kalangan masyarakat adat, ia terkenal pandai bernyanyi dan memiliki kedekatan dengan tokoh Gereja. “Saya menjadi relawan Jokowi selama tiga bulan. Kami ada kunjungan ke desa lalu saya diminta pimpin doa makan sebelum dan setelah makan. Ketika berdoa semoga Jokowi menjadi presiden terpilih kita,” ia menceritakan.
Tapi sejak itu, kondisi kelompok transpuan di kampungnya masih sama. Mereka masih sulit mendapatkan pelayanan, utamanya membikin KTP. “Ketika kami datangi pemerintah desa. Kami sampaikan hak kami, seperti kebutuhan mengurus KTP dan mengurus KK. Minta bantuan itu. Kami disuruh urus sendiri (tidak dibantu pemerintah),” kata Inces.
Satu-satunya jalan beroleh pelayanan, kata dia, ialah meminta tokoh keagamaan untuk mengurus kartu kependudukan. “Saya membantu mengurus KTP mulai 2020-an. Karena kami ada pastor akhirnya dibantu. Lalu satu minggu baru dapat (KTP). Kalau tidak dibantu pastor tidak akan dapat,” ungkapnya miris.

Kendati memiliki KTP, belum tentu transpuan mendapatkan hak mencoblos. Pada pemilihan lalu, ia mengaku tidak bisa menggunakan hak pilih meski sudah memiliki formulir C-1 dan KTP. Petugas pemungutan suara (TPS) saat itu menduganya sebagai pemilik identitas ganda. Sebab nama yang tertera dalam dokumen pemilihan ialah Inces, sementara di KTP nama lahir lah yang tercantum. “Dianggap dua warga negara. Saya bilang saya memiliki satu KTP,” ujarnya mengingat peristiwa tiga tahun lalu.
Sejauh 1943 kilometer dari Maumere, Jeny tak kuasa menahan tangis mengingat masa-masa awal ketika tiba di Yogyakarta hampir dua dekade silam. Saat ia diusir dari rumahnya di Subang, Jawa Barat, pelataran Stasiun Lempuyangan adalah rumahnya. Simpang lima Candi Prambanan adalah sumber penghidupannya selama bertahun-tahun sebagai pengamen jalanan.
Selama itu pula, Jeny tak pernah mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia, termasuk dalam politik. “Dua kali masa SBY, dua kali Jokowi, saya tidak bisa memilih,” kata Jeny yang menyadari hak-hak politik tersebut setelah mengikuti pelatihan paralegal yang digelar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta pada 2015. “Sebelumnya saya tak sadar ini, fokus yang penting bisa makan dan hidup.”
Sejak saat itu Jeny mengaku pontang-panting mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tiga kali permohonannya kandas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Ia selalu tak bisa memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk rekomendasi pindah domisili. Untuk mengurusnya, ia kudu pulang ke Subang. “Petugas tidak tahu keluarga sudah tidak mau menerima,” ujar Jeny ketika ditemui di markas Keluarga Besar Waria Yogyakarta.
Jerih payahnya baru terbayar Agustus tahun lalu. Lewat program advokasi kependudukan yang digelar Suara Kita, Jeny akhirnya mengantongi KTP. Belakangan, berbekal KTP tersebut, ia akhirnya punya kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Nomor Pokok Wajib Pajak, dan keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Suara Kita merupakan organisasi untuk advokasi kesetaraan dan keadilan bagi kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, dan interseks (LGBTQI). Beberapa tahun terakhir Suara Kita memang dikenal aktif melobi Kementerian Dalam Negeri, agar menaruh perhatian terhadap masalah yang dihadapi transpuan seperti Jeny. “Nomor Induk Kependudukan, KTP, itu paling utama,” kata Koordinator Suara Kita, Hartoyo pada Ahad, 12 Juni lalu.
Dalam pendataan sementara Suara Kita per September 2022, terdapat sekitar 32.991 jiwa transpuan di seluruh Indonesia yang diadvokasi untuk mendapatkan nomor kependudukan. Dari data itu, baru 4742 transpuan yang telah memiliki KTP. Artinya, di setiap tujuh orang transpuan, hanya satu orang di antaranya yang mengantongi dokumen kependudukan. “Kami bersama komunitas di daerah sedang melakukan pendataan swadaya agar transpuan bisa segera mendapatkan KTP,” kata Hartoyo.
Sebenarnya, Kementerian Dalam Negeri mulai bersikap progresif untuk pengurusan KTP bagi transpuan. Kementerian menempatkan transgender, bersama korban bencana alam, komunitas adat di daerah terpencil, orang terlantar dan miskin ekstrem, orang dengan gangguan jiwa, serta penyandang disabilitas, sebagai kelompok yang rentan dalam menjangkau pelayanan administrasi kependudukan.
Klaim Perlakuan Setara
Pada 26 Agustus 2021, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 470/11320/Dukcapil perihal Pendataan dan Penerbitan Dokumen Adminduk Bagi Penduduk Transgender. Surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut diklaim menjamin kemudahan dan persamaan perlakuan bagi transpuan dalam mengurus KTP.

Direktur Jenderal Penduduk dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa pemerintah menjamin pelayanan KTP bagi siapa saja, termasuk transpuan. “Pelayanan adminduk itu inklusif. Yang penting penuhi persyaratan, ikuti aturan, datang ke dinas dukcapil.” kata Zudan.
Kemendagri mengklaim per Desember 2021 jumlah penduduk Indonesia yang sudah memiliki KTP sebanyak 99,21 persen dari jumlah total penduduk. “Bila mau menggunakan hak pilihnya, penuhi saja persyaratannya,” tuturnya.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bidang Data Pemilih, Betty Epsilon Idroos pun menjamin semua transpuan bisa menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. “Transpuan atau transgender itu bagian dari warga negara Indonesia. Kami melayani pemilu ini dengan prinsip sama rasa dan sama rata,” kata Betty ditemui di ruangan kerjanya di KPU, Selasa, 13 September 2022.
Dari hal itu, KPU, kata Betty telah menjalankan bimbingan teknis bagi penyelenggara pemilu agar kelompok termarjinalkan terwadahi haknya untuk memilih. “Kami telah melakukan bimbingan tim ad hoc,” kata Betty.
Sementara terkait dengan masih adanya praktik diskriminasi dalam proses pemilu untuk transpuan, KPU akan menjadikan itu sebagai bentuk evaluasi bersama. Nantinya, kata Betty, petugas-petugas yang berada di tempat pemilihan umum akan dididik untuk lebih ramah terhadap kelompok transpuan. “Ini masukan bagi kami. Kalaupun ada silahkan beritahu tempatnya di mana jadi bisa awareness kami dalam melayani pemilih. Karena itu tugas kami untuk melayani pemilih,” kata Betty.
Masalahnya, menurut Hartoyo, pelaksanaan surat edaran tersebut tak merata, amat bergantung pada sensitivitas pemerintah daerah setempat terhadap transpuan. Walhasil, belum semua transpuan seberuntung Jeny.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah menilai masalah transpuan tak dapat memilih merupakan dampak dari cara pandang pemerintah yang melihat identitas gender dalam administrasi hanya laki-laki dan perempuan. Alih-alih diberi kondisi agar mampu (enabling condition) kelompok ini malah dianggap tidak perlu. “Ini persoalan struktural terkait dengan cara pandang dan kebijakan negara yg tidak ramah kepada mereka: soal pendataan penduduk yang utamanya berkaitan dengan identitas kelamin,” pungkasnya.
Oleh sebab itu, transpuan dalam pemilu menjadi kelompok termarjinalkan. Identifikasi gender, kata dia, telah memperburuk atau memicu perlakukan aparatur maupun masyarakat ketika hendak menggunakan hak pilih. “Transpuan termasuk kelompok paling termarjinalkan dalam pemilu karena ada persoalan struktural, kultural, hingga persoalan teknis,” jelas Hurriyah.
***
Koordinator Waria Crisis Center Rully Malay di Daerah Istimewa Yogyakarta menceritakan upaya politikus mendekati transpuan pada Pilpres 2019. Tim sukses dua partai oposisi pemenang Pilpres 2019 saat itu, mengumpulkan lima tokoh transpuan Yogyakarta di sebuah Restoran The House of Raminten. Selain Mami Rully, mereka yang diundang antara lain Ketua Keluarga Besar Waria Yogyakarta (Kebaya) Vinolia Wakijo, dan Pemimpin Pesantren Waria Al-Fatah, Shinta Ratri.
Politisi itu meminta lima tokoh transpuan membuat pernyataan sikap yang isinya menyatakan seorang capres mendukung LGBT sebagai bagian dari kampanye hitam. Tim sukses partai itu menjanjikan duit sebesar Rp 300 juta untuk pendanaan komunitas bila lima transpuan itu setuju. “Saya bilang terlalu riskan bagi transpuan untuk cawe-cawe dalam politik,” ujarnya.
Rully dan empat pentolan kelompok transpuan itu sadar bahwa mereka hanya dijadikan alat kampanye hitam parpol, bagian dari membawa politik identitas yang muncul musiman setiap ada agenda politik.
Meski langsung mendapatkan penolakan, tim sukses parpol tersebut getol merayu para transpuan supaya mau memberikan pernyataan. Mereka intens menelpon dan mengirim pesan melalui WhatsApp Rully Malay. “Kami tolak, tujuan mereka ingin menjatuhkan,” ujarnya.
Pola yang sama mereka dengar di kota lain, misalnya di Jawa Barat, Sulawesi, dan DKI Jakarta. Ketua Transpuan Jakarta Barat, Mama Echi menyatakan sempat terlibat dalam kampanye akbar di Gelora Bung Karno pada Sabtu, 13 April 2019. Ia dan ratusan transpuan diminta berdandan menggunakan pakaian putih dengan latar foto Jokowi. “Kalau kampanye sering banget. Tahun berapa lagi itu di Monas yang kita harus pakai baju adat. Itu termasuk saya dilibatkan juga,” kata Mama Echi sata ditemui di Kawasan Danau Cipondoh, Sabtu, 30 Juli 2022.
Kendati telah membantu dalam proses pemenangan Jokowi-Ma’ruf, menurutnya, transpuan belum mendapatkan hak dan jaminan hidup yang layak. “Jujur saja kalau untuk teman-teman transpuan itu inginnya diakui bahwa kami itu ada dan kami itu sama warga negara Indonesia,” ungkapnya.
Tim Kolaborasi
Penanggung Jawab: Muhammad Kholikul Alim (Jaring.id); Agoeng Wijaya (Koran Tempo)
Penulis: Abdus Somad, Reka Kajaksana (Jaring.id); Shinta Maharani, Imam Hamdi, Riri Rahayuningsih (Koran Tempo)
Penyunting: Muhammad Kholikul Alim, Damar Fery Ardiyan (Jaring.id); Agoeng Wijaya, Rusman Paraqbueq (Koran Tempo)
Foto: Shinta Maharani (Koran Tempo), Abdus Somad (Jaring.id)