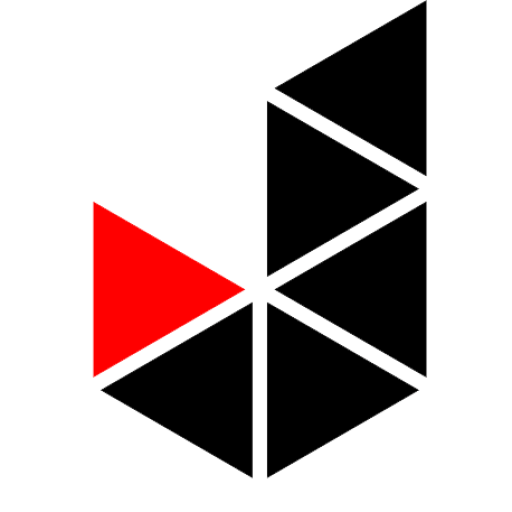John Sawicki, direktur Center for Internasional Relations di Duquesne University, Pittsburgh menganalisis, serangan bom bunuh diri setidaknya memiliki lima logika penting, yaitu 1) drama (karena mengejutkan dan membangkitkan emosi), 2) efektif dari sisi biaya, 3) rencananya berusia lama (bisa berbulan-bulan dan menunggu waktu yang tepat untuk dilaksanakan), 4) mendapat perhatian besar dari media, dan 5) risiko yang relatif kecil bagi otak penyerangan.
Demi logika itulah, kemudian organisasi teroris mulai menggunakan perempuan dan anak-anak sebagai pasukan bom bunuh diri. Penggunaan perempuan dan anak-anak secara tepat mendukung lima logika di atas, dan ada satu tambahan keuntungan: perempuan dan anak-anak lebih tidak dicurigai oleh aparat keamanan, dan karenanya mereka bisa lebih mudah mendekati target serangan. Ketika mereka berhasil meledakkan diri, nilai dramanya jadi lebih besar dan perhatian media pun akan semakin besar pula (perhatian media terhadap serangan bom bunuh diri oleh perempuan dan anak-anak empat kali lebih besar dibandingkan serangan bom bunuh diri oleh lelaki).
Andai pun perempuan dan anak yang jadi pembom bunuh diri terdeteksi oleh aparat keamanan, tindakan pencegahan yang dilakukan aparat—misalnya dengan menembak mereka—malah akan menguntungkan citra kelompok teroris. Sebabnya, hampir dalam semua budaya dan hukum perang, perempuan dan anak-anak selalu jadi kelompok yang harus dihindarkan dalam aksi kekerasan. Jika aparat keamanan melakukan aksi pencegahan dan terpaksa melakukan kekerasan, kelompok teroris dapat menyebarkan propaganda “negara membunuh perempuan dan anak”.
Jadi, bagi kelompok teroris, penggunaan perempuan dan anak-anak selalu menguntungkan, tak peduli apakah mereka berhasil meledakkan diri atau tidak. Karena bagaimana pun serangan bom bunuh diri bukanlah bertujuan untuk membunuh per se tapi sebagai pesan yang mengintimidasi lawan.
Selain itu, ada “keuntungan budaya” dalam penggunaan perempuan dan anak-anak sebagai pembom bunuh diri. Perempuan dan anak-anak adalah warga kelas dua dalam budaya patriarki (di mana budaya ini masih sangat kuat di kawasan Asia dan Afrika). Dengan bergerak di lingkungan budaya patriarki, kelompok teroris tidak perlu bersusah payah untuk merekrut atau mendidik perempuan dan anak-anak untuk menjadi pembom bunuh diri, karena beberapa alasan.
Pertama, balas dendam. Banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban tambahan dalam situasi konflik, misalnya dalam perang. Dalam masyarakat patriarki, perempuan dan anak-anak yang kehilangan suami, ayah, atau keluarganya, mudah untuk dibuat merasa tidak berdaya (misalnya untuk merasa bahwa mereka tidak bisa hidup atau tidak berharga tanpa suami dan ayah) dan akhirnya mudah untuk diarahkan melakukan tindakan fatalistik dengan alasan untuk membalas dendam atas kematian suami, ayah, dan keluarga terdekatnya, apalagi jika dijanjikan akan langsung masuk surga.
Alasan ini tercermin dalam kasus penyerangan kelompok yang dikenal sebagai Black Widow (Janda Hitam), yaitu perempuan-perempuan Chechnya yang melakukan serangkaian aksi teror di Rusia, untuk membalas dendam kematian suami atau ayah mereka, dengan dibalut semangat keagamaan dan nasionalisme Chechen. Dalam catatan Chicago Project on Security and Threats (CPOST), lembaga riset yang berbasis di University of Chicago, Rusia menjadi negara keempat terbanyak yang dijadikan target serangan bom bunuh diri oleh perempuan.
Kedua, penyucian diri. Banyak perempuan yang menjadi sasaran kekerasan langsung dalam situasi konflik, misalnya perkosaan massal. Dalam banyak budaya, aksi perkosaan massal terhadap perempuan musuh, bukan bermotif seksual semata, tapi bertujuan untuk menghancurkan martabat dan mental musuh. Perempuan dalam situasi konflik yang pernah diperkosa, sangat rentan untuk direkrut jadi pembom bunuh diri, dengan alasan untuk membalas dendam dan menyucikan diri. Dalam kasus terorisme, mulai terungkap banyak perempuan yang diculik dan diperkosa oleh para penculiknya, kemudian dijadikan sebagai pembom bunuh diri. Dalam sebuah pengungkapan di Irak pada 2009, misalnya, aksi penculikan dan pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan yang akan dijadikan pembom bunuh diri dikoordinir oleh seorang perempuan bernama Samira Ahmed Jasiim yang diberi gelar Ummi Al Mukmin (Ibu Kaum Beriman). Dia bertanggung jawab dan mengkoordinasi 80 kali aksi perkosaan terhadap perempuan yang akan direkrut jadi pembom bunuh diri. Samira mengaku telah mengirim 28 perempuan jadi pembom bunuh diri. Kelompok teroris di Afrika, Boko Haram, juga melakukan metode yang sama—penculikan dan perkosaan—untuk membuat perempuan dan anak-anak jadi pembom bunuh diri.
Ketiga, naik status sosial. Sebagai warga kelas dua di dalam masyarakat patriarki, perempuan dan anak-anak yang melakukan aksi ekstrem seperti bom bunuh diri, dapat menaikkan status sosial dia dan keluarganya. Biasanya pelaku bom bunuh diri akan dianggap sebagai syahid, dan karenanya keluarganya pun akan dipandang terhormat oleh masyarakatnya. Selain itu, perempuan dan anak-anak yang bersedia jadi pembom bunuh diri bisa dijadikan alat untuk “memanas-manasi” kaum lelaki di masyarakat tersebut. Karena dalam masyarakat patriarki, lelaki akan merasa kehilangan kehormatan jika tidak bisa melakukan tindakan yang bisa dilakukan perempuan. Situasi semacam ini terdeteksi dalam kasus pembom bunuh diri Palestina.
Bom Bunuh Diri Anak dan Gejalanya
Perekrutan perempuan sebagai pembom bunuh diri sudah dilakukan sejak 1990-an, terutama dalam aksi serangan Palestina ke Israel. Berdasarkan data intelijen Israel, dari 147 serangan bom bunuh diri di Israel, delapan di antaranya dilakukan oleh perempuan. Sementara perekrutan anak-anak sebagai pembom bunuh diri adalah fenomena yang relatif baru.
Di negara-negara yang sedang mengalami konflik dan berurusan langsung dengan terorisme, seperti Afrika sub-Sahara, Afganistan, Irak, dan Pakistan, sejak lama terdeteksi ada perekrutan anak-anak untuk dijadikan anggota kelompok-kelompok teroris. Anak-anak itu dididik untuk menjadi penerus kelompok-kelompok teroris di masa depan.
Dalam laporan PBB tahun 2017, diperkirakan sejak 2009 sebanyak 8.000 anak-anak telah direkrut dan digunakan oleh Boko Haram di Nigeria. Dalam laporan itu tertulis, anak-anak laki-laki dipaksa untuk menyerang keluarga mereka sendiri untuk menunjukkan kesetiaan kepada Boko Haram, sementara anak-anak perempuan dipaksa menikah, mencuci, memasak dan memanggul peralatan dan senjata. Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia juga secara konsisten menerima laporan-laporan tentang anak-anak yang digunakan sebagai tameng hidup dan untuk meledakkan bom.
Pada 2014, mulai ditemukan gejala merekrut anak-anak untuk dijadikan pembom bunuh diri. Gejala itu berupa penyergapan oleh kelompok teroris ke sekolah-sekolah dan menculik ratusan murid sekolah-sekolah itu. Juga ditemukan adanya CD berisi video aksi bom bunuh diri yang diberi ilustrasi musik di kamp-kamp Taliban di Afganistan dan Pakistan. Di tahun yang sama, aktivitas penyerangan dan penculikan ke sekolah-sekolah juga dilakukan Boko Haram di Afrika sub-Sahara. Sejak itulah, aksi serangan bom bunuh diri yang dilakukan anak-anak menunjukkan peningkatan signifikan.
Sementara itu di Suriah, pada 2015 saja PBB telah memverifikasi 274 kasus anak-anak yang direkrut oleh ISIS untuk dijadikan petempur. Dari kasus-kasus itu tercatat ada 18 kasus ISIS menggunakan anak-anak berusia 7 tahun untuk bertempur. ISIS juga menggunakan anak-anak itu untuk mengeksekusi tawanan dengan cara menyembelih atau membakar mereka. Situasi mengerikan juga terjadi Irak, di mana pada Juni dan September 2015 ISIS menculik lebih dari 1.000 anak di Mosul.
Sebagai bom manusia, anak-anak dianggap sama efektif dan efisien seperti perempuan. Ada satu tambahan keuntungan lagi, anak-anak mudah dimanipulasi dan diberi imajinasi tentang surga. PBB merinci enam alasan mengapa anak-anak direkrut organisasi-organisasi teroris.
Pertama, untuk keterlihatan dan propaganda. Kelompok teroris semakin sering menyiarkan gambar atau video aktivitas mereka yang menggunakan anak-anak. Dalam analisis terhadap enam bulan data propaganda ISIS diketahui mereka telah menyiarkan 254 kejadian yang memasukkan gambar anak-anak, di mana 38 persen dari gambar itu menunjukkan anak-anak yang terlibat dalam aksi kekerasan atau terlihat dan terbiasa dengan kekerasan. Gambar-gambar itu ditujukan untuk membuat publik terkejut, dan di saat yang sama menunjukkan kekuatan dan kekejaman kelompok itu.
Kedua, persoalan demografi. Di negara-negara miskin terjadi pergeseran demografi, sebagai bagian dari penyebaran HIV/AIDS, yang membuat jumlah anak-anak meningkat tajam berbanding dengan keseluruhan populasi, dan kondisi itu menyebabkan anak-anak sebagai kelompok yang paling mungkin untuk direkrut atau diculik.
Ketiga, harapan masyarakat. Dalam beberapa situasi, kelompok bersenjata—termasuk teroris—diterima oleh masyarakat sebagai alat pertahanan untuk menghadapi kelompok lainnya atau untuk menghadapi aparat negara. Dalam situasi itu, anak-anak bisa jadi didorong oleh keluarganya untuk bergabung dengan kelompok bersenjata. Tapi dalam situasi di mana kelompok bersenjata tidak disukai masyarakat, kelompok bersenjata akan secara aktif merekrut anak-anak karena mereka lebih mudah diperdaya ketimbang orang dewasa.
Keempat, pertimbangan ekonomi dan efektivitas. Dengan merekrut anak-anak, kelompok-kelompok teroris mendapatkan banyak keuntungan ekonomis. Misalnya, tentara anak-anak bisa dibayar murah (atau tidak dibayar sama sekali), dan mereka tidak membutuhkan makanan sebanyak orang dewasa. Selain itu, dengan semakin banyaknya varian senjata ringan yang murah, telah mengurangi kesenjangan kemampuan menggunakan senajata antara orang dewasa dan anak-anak. Dengan senjata yang lebih kecil dan ringan, anak-anak sama berbahayanya dengan orang dewasa.
Kelima, kontrol. Anak-anak lebih mudah dikontrol secara fisik dan mental, membuat mereka lebih mudah dibuat setia kepada tokoh-tokoh di dalam kelompoknya dan mudah mengikuti keyakian dan perilaku orang yang mereka hormati. Anak-anak juga dianggap sebagai investasi untuk generasi mendatang.
Keenam, keuntungan taktis. Anak-anak, terutama anak perempuan, semakin banyak yang digunakan sebagai mata-mata, membawa material dan melakukan serangan bunuh diri. Alasannya, anak-anak tidak memahami risiko tindakan yang mereka lakukan, dan karenanya mereka tidak tampak gugup saat melakukan tugas yang diberikan, sehingga membuat mereka mudah untuk mendekat pada target serangan.
Refleksi pada Kasus Bom Bunuh Diri Sekeluarga di Indonesia
Dari pemaparan di atas, terlihat teroris dan aktivitas terorisme memiliki pola, baik dalam pembentukan ideologi, pembentukan organisasi, aktivitas teror, dan perekrutan. Dalam hal penggunaan perempuan dan anak dalam aktivitas teror, Indonesia sudah seharusnya waspada, karena hal itu sudah terjadi dalam kasus bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo. Juga harus diwaspadai, teroris di Indonesia melakukan taktik baru dalam aksi teror, yaitu melibatkan seluruh anggota keluarga. Aksi semacam ini belum pernah terdeteksi dilakukan oleh kelompok teroris mana pun di dunia. Mungkin banyak keluarga yang berisi teroris semua—ayah, ibu, dan anak-anaknya—namun tidak pernah terjadi mereka melakukan aksi teror bunuh diri secara bersama. Kejadian di Sidoarjo dan Surabaya sangat mungkin memberi inspirasi pada banyak keluarga teroris untuk melakukan hal yang sama.
Pembentukan ideologi teroris di Indonesia sudah ada sejak lama, bahkan bisa dirunut sampai era perang kemerdekaan, misalnya dalam kasus pemberontakan DI/TII di bawah kepemimpinan Kartosuwiryo. Artinya, ideologi mempertahankan atau menyebarkan iman dengan kekerasan sudah memiliki akar yang cukup dalam di negeri ini.
Demikian pula dengan pembentukan organisasi teroris. Dengan pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan kepolisian Indonesia, kita bisa mengetahui kelompok-kelompok teroris di Indonesia berjaringan satu dengan lainnya, dan berafiliasi pula ke kelompok teroris transnasional seperti Al Qaeda dan ISIS. Jaringan internasional mereka juga tidak main-main, karena banyak orang Indonesia sudah terlibat dengan aktivitas teror sejak perang Afganistan melawan Uni Soviet, sampai yang baru-baru ini, bergabung dengan ISIS dalam konflik di Suriah dan Irak. Artinya, anggota kelompok teror di Indonesia bisa dikatakan sudah banyak belajar mengenai strategi dan taktik teror, dan menguasai teknik pembuatan alat-alat teror.
Pembentukan organisasi juga pasti telah diikuti dengan indoktrinasi kepada setiap anggota dan keluarga intinya. Keterlibatan perempuan dan anak di dalam jaringan teroris di Indonesia, tampaknya telah terjadi melalui proses indoktrinasi di dalam keluarga. Proses itu akan sangat sulit diawasi, dan bahayanya sangat laten, karena dilakukan di dalam sel-sel yang sangat kecil di tengah keluarga, dan sama sekali tidak terlihat di permukaan. Berbeda, misalnya, dengan yang dilakukan Al Qaeda atau ISIS di Afganistan, Afrika dan Timur Tengah, di mana mereka merekrut, mendidik, dan melakukan indoktrinasi secara massal kepada anak-anak di satu tempat tertentu sehingga relatif mudah dideteksi.
Yang harus diwaspadai ke depan, serangan bom bunuh diri sekeluarga bisa kembali terjadi, karena potensi itu cukup besar. Keluarga Indonesia umumnya berkultur kolektif, di mana anggota keluarga melihat dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari keluarga itu untuk selamanya. Orang tua akan selamanya menjadi orang tua—yang harus diikuti dan dihormati—walau anak-anaknya sudah dewasa. Begitu pula dengan anak, yang selamanya harus memosisikan diri sebagai anak walau mereka telah dewasa. Sifat keluarga yang seperti ini, bisa jadi potensi berbahaya ketika sudah bercampur dengan ajaran ekstrem, karena satu tindakan orang tua, bisa jadi diikuti atau diteruskan oleh anak-anaknya.
Banyak keluarga Indonesia yang juga punya kecenderungan tidak mau meninggalkan anak—biasanya karena rasa sayang dan rasa khawatir anak-anaknya akan terlantar. Kecenderungan seperti ini yang berkelindan dengan logika teroris bisa melahirkan aksi fatal seperti yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo.
Yang juga harus diwaspadai—jika kita bercermin pada kasus di Timur Tengah, Afganistan, Pakistan, Afrika, dan Chechnya—adalah gelombang serangan bunuh diri yang dilakukan oleh perempuan dan anak dari para teroris lelaki yang mati terbunuh dalam aksinya, yang sudah dieksekusi negara, atau yang masih ada di dalam penjara-penjara.
Pun demikian kita harus mewaspadai potensi lain yang bisa dimanfaatkan kelompok-kelompok teroris: orang-orang yang mencari penyucian diri atau pengampunan akibat dirinya merasa telah melakukan perbuatan tercela atau merasa telah ternodai. Sudah sewajarnya kita waspada, dan mencari cara bagaimana agar para korban kekerasan—terutama perempuan dan anak-anak—tidak jatuh ke rangkulan kaum ekstremis. Karena pola itu pula yang digunakan di Timur Tengah dan Afrika. Bahkan mereka melakukan program penculikan dan perkosaan secara massif dan sistematis, untuk menciptakan manusia-manusia yang merasa telah “kotor”, dan mereka berhasil mengubah banyak manusia menjadi bom. (Zaky Yamani, penulis lepas)
Referensi
“A Look at the History of Suicide Attacks”, Opinion, National Public Radio, 19 Juli 2005, https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4760240
Ahmed, Nafeez, “Unworthy Victims: Western Wars Have Killed Four Million Muslims Since 1990”, http://www.stopwar.org.uk/index.php/news-comment/2615-unworthy-victims-western-wars-have-killed-four-million-muslims-since-1990
Demirzen, Ismail, “A Sociological Perspective to Suicide Bombing”, Istanbul Universitesi, Ilahiyat Fakultesi, 2011
“Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice System”, United Nations Office on Drugs and Crime, 2017
Hilal, Maha, “The War on Terror Has Targeted Muslim Almost Exclusively”, di dalam Foreign Policy in Focus, 11 September 2017, https://fpif.org/the-war-on-terror-has-targeted-muslims-almost-exclusively/
Horowitz, Michael C, “The Rise and Spread of Suicide Bombing”, di dalam Annual Review of Political Science Vol. 18:69-84, Mei 2015, https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-polisci-062813-051049
Lewis, Jeffrey William, “The Human Use of Human Beings: A Brief History of Suicide Bombing”, di dalam Origins Vol. 6, Issue 7, History Departments at The Ohio State University, April 2013, http://origins.osu.edu/article/human-use-human-beings-brief-history-suicide-bombing/page/0/1
Munir, Muhammad, “Suicide Attacks and Islamic Law”, di dalam International Review of the Red Cross, Volume 90 Number 869, Maret 2008
“Number of Casualties Due to Terrorism Worldwide between 2006 and 2016”, Statista The Statistic Portal, https://www.statista.com/statistics/202871/number-of-fatalities-by-terrorist-attacks-worldwide/
“Number of Worldwide Kidnappings Due to Terrorism from 2007 to 2016”, Statista The Statistic Portal, https://www.statista.com/statistics/250557/number-of-kidnappings-due-to-terrorism/
Overton, Iain and Dodd, Henry, “A Short History of Suicide Bombing”, 23 Agustus 2013, https://aoav.org.uk/2013/a-short-history-of-suicide-bombings/
Poushter, Jacob dkk, “Concern about Islamic Extremism on the Rise in Middle East, Negative Opinions of Al Qaeda, Hamas and Hezbollah Widespread”, Pew Research Center, 2014
Sawicki, John, “A Tragic Tren, Why Terrorists Use Female And Child Suicide Bombers”, di dalam jurnal Health Progress, www,chausa.org, Juli-Agustus 2016
“Suicide Bombing Terrorism During The Current Israeli-Palestinian Confrontation (September 2000-December 2005)”, Intelligence and Terrorism Center at the Center for Special Studied, Januari 2006